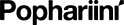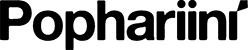Memimpikan Ekuilibrium

Saya jenuh, bicara tentang pandemi. Sialnya, topik ini sangat menarik dan ultra-relevan, tapi saya kehabisan bensin untuk tetap antusias. Jadi, saat diajak Pophariini untuk membuat esai tentang adaptasi industri di kala pandemi, saya banyak berpikir tentang intensi dari apa yang saya mau tulis. Lalu saya putuskan untuk memberikan tantangan kepada diri sendiri. Paragraf pembuka ini jadi paragraf terakhir di mana Anda akan membaca kata “pandemi”. Saya akan menulis tentang pandemi tanpa menggunakan kata-kata itu lagi, di sepanjang sisa esai ini. Ini janji saya: hanya ada lima kata pandemi di tulisan ini.
Untuk bisa mengerti dengan cara yang lebih komprehensif, mari kita cermati kondisi scene lokal satu dekade terakhir (2010 – 2019) dengan menggunakan lensa hukum ekonomi sederhana yang dipopulerkan oleh Adam Smith: Law of Supply and Demand. Silakan sisir internet jika ingin mempelajari teori ini lebih jauh.
Mari mulai dari aspek supply: didorong oleh invasi kultur digital, selama 2010 – 2019 kuantitas dan kualitas pegiat musik lokal meningkat dan jadi sangat beragam. Berbagai segmen musik disesaki oleh talenta-talenta baru yang segar. Bukan hanya dari aspek musisi saja, tapi juga ekosistem yang mendukungnya: venue, kolektif kreatif, inisiatif media, vendor produksi, event organizer, tim dokumentasi, manajemen artis, agensi dan sebagainya. Internet membuka akses semua pelaku untuk mendidik diri sendiri dan meningkatkan mutu secara kolektif.
Lalu dari segi demand juga tidak kalah menarik untuk ditinjau. Ketersediaan musisi di berbagai scene, juga infrastruktur yang mendukungnya menghasilkan demand komersil yang mengagumkan. Ada beberapa indikator sederhana: Banyaknya musisi – solo atau grup, niche atau mass, dari berbagai genre – yang mampu menghidupi diri mereka sendiri 100% menggunakan musik. Khusus untuk jenis musik yang lebih niche, profesi musisi perlahan tidak lagi harus disambi dengan kerja kantoran, atau jadi kegiatan ekstrakurikuler anak-anak orang kaya yang pulang dari Amrik atau Eropa saja. Profesi ini, mulai menyeruak jadi legit, bisa digeluti dan menghidupi. Gap disparitas sosialnya perlahan tertutup.
Didorong oleh invasi kultur digital, selama 2010 – 2019 kuantitas dan kualitas pegiat musik lokal meningkat dan jadi sangat beragam. Internet membuka akses semua pelaku untuk mendidik diri sendiri dan meningkatkan mutu secara kolektif.
Indikator kedua: Acara-acara musik menyeruak dan berdegup: party-party Senopati, festival musik lintas generasi, gig band-band internasional, sponsor brand-brand wangi, endorsement media sosial yang gemerlap. Perputaran uang perlahan semakin kencang. Market semakin sehat. Internet juga memudahkan aksi lokal Indonesia untuk ditemukan di kancah global: di-sign label internasional, tur di luar Indonesia dan seterusnya.
Skenario hukum ekonomi Adam Smith seyogyanya berakhir dengan elok, yakni dengan terciptanya equilibrium – titik bertemunya produsen (musisi dan ekosistemnya dan konsumen (penikmat musik) sehingga menciptakan kesepakatan harga yang sehat dan lestari. Sayangnya, 2020 datang dan semuanya berhenti.
Bayangkan industri musik Indonesia adalah sebuah mobil tua yang melaju sangat cepat di jalan bebas hambatan. Dalam akselerasi yang tinggi, pengemudi akan fokus menyetir dengan baik dan selamat, tanpa mempedulikan faktor-faktor lain yang sebenarnya selalu ada di kiri kanan sepanjang perjalanan. Mobil tua tersebut lalu dipaksa menjadi pelan, terjebak macet atau bahkan berhenti total karena salah satu rodanya pecah. Pengemudi yang tadinya terlalu fokus mengendarai mobilnya, jadi bisa memperhatikan pemandangan sekitar, apa yang terjadi di kiri kanan – bahkan hal-hal yang tidak pernah dia sadari sebelumnya menarik perhatiannya.
Skenario hukum ekonomi Adam Smith seyogyanya berakhir dengan elok, yakni dengan terciptanya equilibrium – titik bertemunya produsen (musisi dan ekosistemnya dan konsumen (penikmat musik) sehingga menciptakan kesepakatan harga yang sehat dan lestari. Sayangnya, 2020 datang dan semuanya berhenti
Saat melaju lebih perlahan, hal-hal yang tidak pernah kita cermati sebelumnya akan terlihat lebih jelas. Analogi di atas adalah pengantar dari bagian kedua dari tulisan ini, yakni hal apa saja yang menyeruak ke permukaan saat industri musik Indonesia dipaksa berhenti.
Tentang penemuan
Awalnya, setiap sore dan malam di Instagram selama beberapa minggu ada 6-10 lingkaran bertuliskan “LIVE”. Isinya beragam, tapi tidak banyak yang berkesan. Terkadang hanya orang-orang cari perhatian, atau mereka yang ingin unjuk talenta spontan. Kehilangan rutinitas membuat semua orang panik dan mencari cara untuk tetap terhubung melalui media sosial. Di luar sana, tentunya industri musik sudah lumpuh: tidak ada lagi acara, pembatalan di kiri kanan. Gelap gulita.
Saat opsi offline sudah tidak berlaku lagi, hanya tinggal satu destinasi yang tersisa: jagat maya dan segala belantaranya. Yang terjadi selanjutnya: semua pegiat musik belajar bagaimana memindahkan apa yang mereka lakukan di dunia nyata, agar bisa dinikmati di dunia maya. Baik pelaku dan penikmat harus berdamai dengan fakta bahwa ini bukanlah dunia yang mereka tahu. Bagaimana merangkum pengalaman menikmati musik langsung agar masuk akal saat disajikan dari layar ponsel, tablet, televisi atau komputer.
Semuanya belajar: Musisi dan ekosistemnya mengungsi, penonton dan konsumen juga belajar menikmati sajian musik dalam format yang “baru”.
Sounds From the Corner – kolektif yang saya kelola – punya berbagai studi kasus. Sejak awal 2020, kami buat berbagai eksperimen. Mulai dari konser tunggal, party sepuluh jam, festival skala internasional, session musik mandiri, sampai mengadakan diskusi rutin yang menggunakan format live di Youtube. Sebagian besar berhasil, ada yang flop – namun tidak ada yang harus disesali.
Semuanya belajar: Musisi dan ekosistemnya mengungsi, penonton dan konsumen juga belajar menikmati sajian musik dalam format yang “baru”.
Satu-satunya definisi kebodohan di fase ini adalah tidak mau bereksperimen karena terlalu takut untuk gagal.
Tantangan utamanya jelas adalah attention span – bagaimana membuat penonton betah dan committed menonton di depan layar. Tantangan keduanya, saat sudah harus mengandalkan bentukan ini sebagai cara cari hajat, para pegiat harus putar otak untuk bikin sajian berkualitas tinggi agar konsumen mau membayar. Hasil dari dua tantangan tersebut, tidak sedikit yang memutuskan untuk all out dari aspek visual: migrasi Online menjadi rentetan sajian sinematik yang mengasyikkan.
Saat melihat ke belakang, fakta bahwa dalam kurang dari dua tahun, kita berhasil untuk membangun penemuan baru DAN mengedukasi audiens untuk menerima format baru dan asing ini merupakan hal yang impresif dan patut diapresiasi. Saat dunia normal kembali, saya juga harap keberhasilan migrasi online kita ini tidak sepenuhnya ditinggalkan – karena dalam ketidak nyamanan ini, justru hadir banyak dobrakan yang indah dan menyenangkan.
Tentang penghidupan
Seiringan dengan matinya industri pertunjukkan, hal lain yang mati adalah sumber pemasukan musisi. Dari era 2010-2019, alasan utama kenapa scene lokal bisa berdaya adalah sebagian besar pemainnya menggantungkan diri kepada performance live sebagai model bisnis karir mereka. Opsi manggung untuk cari duit paling sederhana dan payoutnya paling real: Manggung, berinteraksi dengan penonton, dibayar, selesai. Format ini juga yang paling masuk akal, karena live performance beririsan dengan banyak ekosistem industri: EO, dokumentasi, venue, F&B, manajemen artis, merchandise, sponsor, dan seterusnya.
Saat dunia normal kembali, saya juga harap keberhasilan migrasi online kita ini tidak sepenuhnya ditinggalkan – karena dalam ketidak nyamanan ini, justru hadir banyak dobrakan yang indah dan menyenangkan.
Saat industri pertunjukkan redup, otomatis penghidupan semua orang di dalamnya juga lumpuh. Konser online belum sekokoh itu sehingga bisa secara instan menggantikan sumber pemasukkan mereka dari manggung. Tidak sedikit yang langsung mengandalkan presence digital (walaupun banyak yang beli followers palsu) mereka dan berpindah menjadi content creator / key opinion leader. Kita semua tahu bahwa strategi ini tidak sustainable, dan jauh dari identitas utama mereka. Cukup untuk menambal sementara.
Kembali ke analogi mobil yang berjalan perlahan. Di dunia yang lebih lambat, musisi yang kehilangan pemasukan jadi punya waktu lebih untuk meninjau lagi keberlangsungan hidup mereka, dan realitas penghidupan mereka. Selain manggung, dari mana lagi mereka seharusnya menerima uang?
Periode 2010 -2019, obrolan perihal royalti selalu ada namun tidak pernah seserius sekarang. Topik ini beberapa kali menjadi perhatian, ketika musisi sadar betapa besar potensi penghidupan yang bisa mereka dapatkan – khususnya ketika manggung terhenti. Kembalinya isu ini diawali dengan Peraturan Pemerintah yang mewajibkan kafe dan diskotik wajib membayarkan royalti lagu. Musisi lalu sadar, bahwa mereka punya PR besar merapikan dan memperjuangkan hak royalti mereka. Di luar Indonesia banyak musisi yang menyandarkan penghidupan mereka kepada royalti musik, sehingga tidak harus sibuk manggung berkali-kali setiap akhir pekan.
Periode 2010 -2019, obrolan perihal royalti tidak pernah seserius sekarang. Topik ini menjadi perhatian, ketika musisi sadar betapa besar potensi penghidupan yang bisa mereka dapatkan – khususnya ketika manggung terhenti.
Sudahlah tidak mumpuni, ternyata ada desas-desus kasus kolusi sistemik di ranah ini. Tempo merilis artikel “Penunggang Kuda Sistem Royalti”, berisi analisis dugaan adanya praktek curang dalam mendulang uang hasil royalti. Pembuatan PT berlapis yang melibatkan banyak nama familiar, termasuk gitaris band rock anti korupsi, mantan pemimpin redaksi majalah musik dan mantan suami Krisdayanti.
Sementara orang-orang tua diduga makan duit royalti, di periode ini generasi muda menciptakan sesuatu yang konkret dan berisi. Hal kedua seputar penghidupan yang ingin saya cermati adalah dobrakan kreatif yang manfaatnya langsung dirasakan musisi. Saya bicara tentang The Storefront, toko musik digital yang mengutamakan kemaslahatan musisi sendiri. Promotor lokal Noisewhore berulang kali menyampaikan keluh kesah mereka tentang bagaimana raksasa streaming musik Spotify tidak berpihak kepada musisi, sentimen yang rata tersebar secara global, tidak hanya di Indonesia. Tidak hanya berhenti di situ, mereka lalu merilis The Storefront. Toko musik Storefront menyediakan rilisan fisik, digital dan ragam bentuk produk musik lainnya.
Yang paling menyita perhatian saya adalah manifesto yang mereka terapkan dalam menjalankan bisnis. The 90% initiative – yang artinya semua musisi akan memiliki 90% dari apapun yang mereka jual di platform ini. Tidak ada perantara, sama sekali. Yang kedua, The Transparency Act – secara reguler mereka menerbitkan laporan sales mereka sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dan transparansi. Gestur sederhana ini krusial sekali bagi saya. Yang terakhir Own Your Music – musisi diberikan kebebasan mengatur ownership yang ingin mereka miliki. Tidak ada template yang memaksa. Saya mendapatkan berbagai anekdot dari musisi bagaimana mereka bisa merasakan dampak real dan immediate dari Storefront, di fase di mana mereka tidak bisa manggung.
Sementara orang-orang tua diduga makan duit royalti, di periode ini generasi muda menciptakan sesuatu yang konkret dan berisi. Saya bicara tentang The Storefront, toko musik digital yang mengutamakan kemaslahatan musisi sendiri
Tentang keberlangsungan
Saat mobil berhenti melaju, si pengemudi jadi punya waktu untuk melakukan inspeksi mobilnya. Mungkin ada bagian yang penyok, cat yang tergores atau malah ada onderdil usang yang harus diganti. Di fase ini, musisi yang terpaksa pivot dari rutinitas mereka banyak yang berbenah diri. Banyak yang rehat, ada yang malah menemukan gairah baru, tapi tidak sedikit yang malah memutuskan untuk berhenti secara permanen karena sadar sudah tidak sejalan dengan rekan seperjuangan mereka.
Saat NAIF mengumumkan bubar, saya tidak habis pikir tentang satu hal: apakah ini akan terjadi jika jadwal manggung mereka tetap padat sepanjang tahun? Mungkin tidak. Saat ada tragedi terjadi, hal-hal yang tidak tersorot di situasi normal kemungkinan besar akan mencuat, dan jadi perhatian bersama.
Tanpa harus mengerdilkan efek negatifnya, saya pikir periode ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang kita jalani. Karena bubar, bukanlah satu-satunya output yang mungkin terjadi dari proses introspeksi. Tidak sedikit yang memutuskan untuk mengganti haluan dan fokus mereka, mengedepankan strategi yang berbeda. Menurut saya, apapun output yang terjadi dalam periode ini yang terpenting adalah berusaha mencerna makna, dan belajar menyambut kelapangan dada.
Di fase ini, musisi yang terpaksa pivot dari rutinitas mereka banyak yang berbenah diri. Banyak yang rehat, ada yang malah menemukan gairah baru, tapi tidak sedikit yang malah memutuskan untuk berhenti secara permanen karena sadar sudah tidak sejalan dengan rekan seperjuangan mereka.
Saya cukup yakin, saat Anda membaca esai ini, “musibah” ini belum berakhir. Satu-satunya hal yang pasti, adalah ketidakpastian itu sendiri. Apa yang saya jabarkan di atas, adalah contoh berbagai upaya kita merayakan ketidakpastian. Dalam prosesnya untuk pulih, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita serap dan amalkan untuk masa depan.
Saya sangat amat gelisah, semangat dan penasaran menyambut 2022. Kembali ke hukum penawaran dan permintaan yang mendasari esai ini, saya masih memimpikan ekuilibrium, situasi di mana supply dan demand yang sehat menghasilkan titik ideal yang lestari dan saling menguntungkan. Walaupun terasa masih jauh, saya optimis hal itu bukanlah utopia.
Eksplor konten lain Pophariini
Lirik Lagu Hari Yang Mantap Tercipta Sangat Personal oleh Gusti Irwan Wibowo
“Hari Yang Mantap” jadi salah satu lagu dari album ENDIKUP milik mendiang Gusti Irwan Wibowo yang paling banyak berseliweran di media sosial sejak kepergiannya. Tak hanya karena musik dan liriknya yang ringan, tapi juga …
Vendaz Tuangkan Kejujuran Emosional dalam Single 111
Proyek musik solo asal Tulungagung, Vendaz kembali menyapa pendengar lewat rilisan terbaru berjudul “111”. Dirilis hari Jumat (01/08), lagu ini menjadi ruang paling personal bagi Fendy, otak di balik Vendaz untuk menyampaikan keresahan terdalamnya …