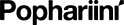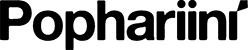Otak Atik Musik di Era Elektronik

Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga industri kreatif, khususnya musik, AI membuka peluang baru yang tidak terbatas.
Perkembangan AI dalam industri musik ikut memengaruhi paradigma dalam penciptaan sebuah lagu, sekaligus mempererat integrasi antara musik dengan teknologi. Pengaruh paradigma tersebut dapat dilihat dengan kemunculan berbagai macam platform AI untuk melakukan produksi lagu secara individu, salah satunya adalah Rightsify.
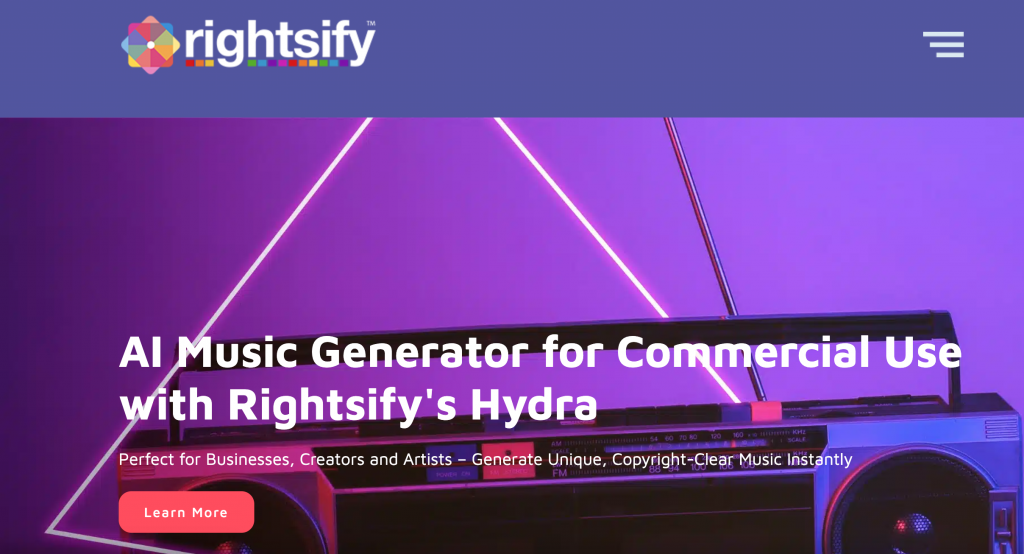
Halaman utama situs Rightsify / Dok. rightsify.com
Platform yang didirikan pada 2013 ini, awalnya lahir sebagai agen lisensi sinkronisasi televisi, film, dan iklan. Seiring perkembangan zaman, Rightsify beradaptasi menjadi agen lisensi musik global yang menyediakan musik untuk hampir semua kasus penggunaan. Tak hanya itu, Rightsify juga menyediakan fitur bernama Hydra yang berfungsi sebagai generator musik untuk bermacam keperluan komersial.
Dengan hadirnya platform generator musik berbasis AI, tentu akan memudahkan orang-orang yang ingin melakukan produksi lagu secara mandiri.
Pro-Kontra dari Pelaku Industri Kreatif
Hal ini tampaknya mengundang perhatian Rendi Pratama selaku produser dari LaMunai Records, salah satu studio dan label rekaman yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan.

Suasana di dalam LaMunai Records / Dok. Pribadi
Saat wawancara langsung di studio LaMunai, Kamis (4/4/2024), Rendi mengatakan bahwa platform seperti Rightsify justru memiliki nilai positif karena dapat membantu proses home studio menjadi lebih baik.
“Platform kecerdasan buatan seperti Rightsify ini bagus-bagus aja malahan. Di samping mempermudah pekerjaan musisi, mau tidak mau kita juga harus bisa kompromi sama teknologi,” ujar Rendi.
Namun, di balik kemudahan itu, Rendi tetap merasa bahwa penggunaan generator AI dapat menyebabkan kinerja di studio rekaman sedikit terganggu.
Menurut Rendi, beberapa profesi seperti engineer, produser, dan musisi pendukung akan memiliki nasib seperti tukang parkir, tidak begitu diperlukan. Semua hal yang terkait dengan profesi tadi dapat digantikan oleh mesin.

Rendi Pratama selaku founder dan produser LaMunai Records (Kanan) / Dok. Pribadi
“Misalkan single songwriter, dengan platform kayak Rightsify, dia enggak perlu belajar main gitar lagi. Bahkan, dia enggak perlu hire pemain drum atau piano untuk mengisi kekosongan di lagu ciptaannya. Cukup meminta AI membuat aransemen piano atau drum yang dibutuhkan. Singkatnya, dia enggak perlu tenaga ekstra, dan bisa memangkas biaya produksinya pula,” jelas Rendi.
Pun demikian, Rendi menyebut, hingga saat ini belum ada perubahan signifikan dari penggunaan generator AI yang dapat memengaruhi kinerjanya di studio LaMunai.
Itu disebabkan oleh mayoritas musisi yang pada kenyataannya masih membutuhkan dukungan langsung dari produser, studio, serta label rekaman untuk menghasilkan karya-karya mereka.
“Kebanyakan artis atau musisi itu pendapatan utamanya dari manggung. Sebelum sampai ke tahap manggung, perlu pihak-pihak kompeten seperti kami (produser, studio, dan label rekaman) untuk membantu proses penciptaan konsep sampai tahap publikasi lagunya nanti. Makin banyak yang suka sama lagunya, kemungkinan manggung juga lebih tinggi,” tambahnya.
Di sisi lain, kehadiran generator AI seperti Rightsify justru membuat Rendi merasa tertantang untuk menghasilkan lagu menggunakan platform tersebut.
Bahkan, Rendi turut mewakili LaMunai Records untuk menyampaikan label rekamannya terbuka bagi musisi yang melibatkan kecerdasan buatan dalam proses pembuatan lagu mereka.
“Pokoknya enggak ada batasan. Justru saya pengin coba menggunakan AI atau minta orang untuk membuat lagu menggunakan AI karena itu bisa jadi terobosan baru. Toh hasil karyanya akan tetap diterima sama label ini,” kata Rendi.
Melihat dari kacamata industrinya, Rendi menyebutkan bahwa dengan AI, transformasi pada proses kreatif di industri musik akan semakin bebas dan terbuka ke depannya.
Menyadari hal itu, sejumlah musisi tanah air, terlebih musisi dengan latar belakang pendidikan khusus bidang kesenian, mulai dihantui keresahan baru terhadap industri musik yang nantinya dapat dikuasai kecerdasan buatan. Salah satunya adalah Bernadette Denisa Dhaniswara.

Bernadette Denisa Dhaniswara / Dok. Yulio Onta
Sebelum menekuni dunia profesional, musisi yang akrab disapa Denisa ini pernah menempuh pendidikan di SAE Institute Jakarta pada 2016, dan lulus dengan gelar Bachelor of Arts (BA) Audio pada 2020.
Selama berkarier, Denisa mengaku bahwa latar belakang pendidikannya sangat berperan dan membantu pengerjaan proyek-proyek lagunya.
“Aku jadi lebih paham tentang sound apa yang cocok digunakan dalam lagu yang aku buat, lengkap dengan karakter mixing dan mastering yang seperti apa. Walaupun enggak recording, mixing, dan mastering sendiri, pengetahuan ini benar-benar membantu untuk mengarahkan tim yang bekerja sama denganku,” ucap Denisa saat diwawancara secara daring, Selasa (16/4/2024).
Kini, peran dan proses yang dilakukan Denisa saat membuat lagu dapat dilakukan oleh kecerdasan buatan. Artinya, orang-orang tidak perlu mengikuti pendidikan khusus dan memiliki keahlian tertentu untuk menciptakan sebuah karya.
Selain keresahan tadi, Denisa menganggap penggunaan generator AI di industri musik dapat menghilangkan unsur-unsur keseruan di dalamnya.
Bagi Denisa, momen paling menarik dari seorang seniman saat berkarya adalah ketika seniman tersebut melibatkan unsur manusiawi ke dalam karya yang dikerjakan. Salah satunya adalah mood atau suasana hati.
“Seniman atau musisi pasti pernah mengalami momen tidak bisa berkarya kalau tidak dalam mood ini. Aku pribadi sangat mencoba tidak bergantung dengan mood itu, tetapi cukup sulit. Menarik sih kalau membandingkan bagian lagu yang dikerjakan saat lagi mood dan saat tidak mood,” katanya.
Denisa juga menambahkan, dirinya masih memerlukan dinamika yang terbilang konvensional sebelum merilis lagu atau album, termasuk dukungan dari pihak kru dan manajemen.
“Setiap bikin album, aku pasti bikin referensi daftar putar dan visual moodboard agar bisa bekerja dengan rapi saat sesi penulisan lirik. Ini biar kebayang sama tema lagu dan mood yang mau disampaikan. Kemudian aku bertemu dengan produser dan tim yang lain untuk bikin song structure yang pas sebelum akhirnya rekaman untuk demo,” ujar Denisa.

Denisa bersama tim kreatifnya / Dok. Yulio Onta
Bagi sebagian orang, unsur-unsur manusiawi yang dituang dan dilibatkan ke dalam sebuah karya adalah ‘nyawa’ dari karya itu sendiri.
Namun, nyawa yang terbentuk dari integritas, kreativitas, dan perasaan tersebut dapat hilang akibat adanya kecerdasan buatan. Ini pula yang mendorong Denisa untuk tetap menciptakan lagu tanpa bantuan AI.
“Menurutku, AI memang dapat membantu proses pra produksi atau perencanaan, tetapi tidak akan membuat itu main function dari proyek yang aku kerjakan. Other than being scared of this Industry being too dependent on it (AI), aku ingin pekerjaan ini berasal 100% dari diriku bersama tim,” tambah Denisa.
Kasus Hukum Penggunaan AI
Selain tak lepas dari pro-kontra dalam penggunaannya sehari-hari (terlebih bagi pelaku industri kreatif), rupanya AI juga telah memasuki ranah hukum.
Dilansir Reuters dalam artikel berjudul “Music labels’ AI lawsuits create copyright puzzle for courts” (3/8/2024) menyebutkan, Recording Industry Association of America (RIAA) mengajukan gugatan terhadap perusahaan AI Suno beberapa waktu yang lalu.
Dalam artikel tersebut, Suno dituduh melakukan pelanggaran hak cipta terkait penyalinan data rekaman suara berskala besar tanpa izin yang jelas.

Ilustrasi perusahaan pengembang AI / Dok. Freepik
Beberapa trek vokal yang disalin terdengar identik dengan beberapa artis terkenal seperti Michael Jackson, Bruce Springsteen, dan ABBA. Namun, gugatan itu dibantah oleh para pengembang AI Suno yang mengklaim bahwa RIAA memiliki kesalahpahaman tentang cara kerja dari perangkat AI milik mereka.
Suno menjelaskan, model pelatihan yang dilakukan perangkat AI mereka bukanlah sekadar menyalin dan mengulang trek yang sudah dilindungi hak cipta. Dalam prosesnya, rekaman suara yang mereka peroleh akan dieksplorasi dan dianalisis terlebih dulu dengan mengidentifikasi pola suara, serta berbagai gaya musik yang berbeda.
Algoritma pembelajaran mesin tadi kemudian didaur ulang menggunakan jaringan neural untuk mensintesis suara dengan akurasi tinggi, sehingga nantinya dapat digunakan orang-orang untuk menghasilkan kreasi baru. Selain itu, pihak Suno juga berpendapat bahwa bentuk penyalinan yang mereka gunakan masih termasuk dalam penggunaan wajar.
Melansir laporan The Verge berjudul “AI music Startups Say Copyright Violation is Just Rock and Roll” (2/8/2024), Suno mengaku tindakan mereka masih dapat dianggap sah menurut doktrin fair use dalam hukum hak cipta.
Doktrin klasik fair use sendiri memang merupakan pilar yang menjadi salah satu prinsip utama hak cipta, dan telah diterapkan secara global. Bahkan, doktrin ini juga digunakan oleh beberapa penyedia AI lain yang mengambil data pelatihan dari internet terbuka, seperti OpenAI, Google, dan Apple.
Meski demikian, argumen milik Suno tetap ditepis oleh RIAA dan gagal memperoleh persetujuan untuk menggunakan karya berhak cipta sebelum meluncurkannya ke pasar.
Menurut RIAA, tindakan Suno dinilai tidak adil karena dianggap mencuri karya nyata seorang artis, mengekstraksi nilai intinya, serta mengemasnya kembali untuk bersaing dengan yang asli.
Lebih lanjut, Cable News Network (CNN) juga melaporkan adanya surat terbuka dari organisasi nirlaba bernama Artist Rights Alliance (ARA) terkait penghentian penggunaan AI yang dapat melanggar dan merendahkan hak-hak seniman.
Dalam rilisnya yang berjudul “Katy Perry, Billie Eilish, J Balvin and more lash out against ‘enormous’ AI threats that ‘sabotage creativity” (2/4/2024), ARA menyoroti ancaman seperti deepfake dan kloning suara yang bisa berdampak pada pendapatan royalti.
Ilustrasi penggunaan deepfake dari kecerdasan buatan / Dok. Freepik
Menanggapi persoalan di atas, Gubernur Tennessee (negara bagian Amerika Serikat) Bill Lee, akhirnya mengeluarkan dan menandatangani Ensuring Likeness Voice and Image Security (ELVIS) act yang berdampak pada tata kelola hak cipta.
Perlu diketahui, Tennessee memang memiliki perhatian khusus terhadap industri musik karena musik telah mendukung lebih dari 61.617 pekerjaan di seluruh negara bagian Amerika Serikat, dan menyumbang sekitar 5,8 miliar dolar AS terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di sana.
UU yang diberlakukan sejak 1 Juli 2024 ini mengatur persoalan seputar deepfake dan soundlike, mencakup penggunaan suara serta kemiripan seseorang oleh generator kecerdasan buatan.
Selain memperluas larangan penggunaan suara milik seseorang tanpa izin (selain nama, foto, dan kemiripan), ELVIS act juga memungkinkan perusahaan rekaman untuk mengajukan tindakan yang bersangkutan dengan nama artis mereka.
UU ELVIS act sendiri ditargetkan kepada platform-platform media sosial, layanan streaming, dan pengembang generator AI dengan mempersempit pengecualian pada fair use dan iklan.
Penggunaan AI Secara Tidak Bertanggung Jawab
Sementara itu, berbeda dengan Tennessee, para pengambil kebijakan di Indonesia justru belum memiliki hukum dan diskursus yang tegas untuk menanggapi persoalan di atas.
Direktur Industri Kreatif, Musik, Film, dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Mohammad Amin Abdullah sempat menyatakan bahwa hingga kini, pihaknya belum menerima laporan apa pun terkait kecerdasan buatan.

Mohammad Amin Abdullah / Dok. Indonesiana.id
“Kita lihat dulu perkembangannya ya karena sampai sekarang kita (Kemenparekraf) juga belum pernah mendapat semacam klaim atau apa pun yang bersangkutan dengan AI,” ucap Amin ketika diwawancara langsung dalam salah satu forum terbuka di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Minggu (11/8/2024).
Pada kenyataannya, teknologi AI untuk membuat deepfake sebenarnya sudah tidak asing untuk dijumpai di Indonesia, terlebih pada platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Hal ini menyebabkan banyak akun berisi produk deepfake mulai bermunculan. Biasanya, akun tersebut akan menyebarkan produk berupa cover lagu dari artis atau tokoh terkenal lainnya.
Beberapa contohnya dapat kita temukan pada akun bernama @ferrenza, @kevinowl1, serta @cumamaudipanggilsayang di platform media sosial TikTok. Ketiganya bukan hanya berisi kumpulan deepfake dari musisi luar dan dalam negeri saja, melainkan juga dari beberapa tokoh politik, seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, hingga Donald Trump.
Salah satu akun bernama @tokoperabotmurah7, bahkan menggunakan suara dan wajah dari mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam salah satu kontennya di TikTok.
Video berdurasi 33 detik itu menampilkan sosok Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa dirinya akan membagikan sprei dan bedcover secara gratis menjelang masa akhir jabatannya.
Selain @tokoperabotmurah7, penyebaran video serupa juga ikut dilakukan oleh beberapa akun TikTok lainnya dengan menggunakan deepfake dari tokoh yang berbeda. Pada akun bernama @spreypremiumviral, kita dapat menyaksikan video berupa deepfake dari Prabowo Subianto dan Najwa Shihab yang tengah mendiskusikan promosi penjualan sprei.
Lebih lanjut, video itu memperlihatkan sosok Prabowo yang mengatakan bahwa promosi penjualan sprei bukan bertujuan untuk mencari untung, melainkan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Solusi Terkait Regulasi AI di Indonesia
Belajar dari kasus yang dialami oleh perusahaan pengembang AI Suno, tentu Indonesia harus lebih responsif untuk segera meregulasi perkembangan AI dalam industri kreatifnya.
Tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak artis atau seniman dari penggunaan atau pencurian data, tetapi juga untuk menghindari penggunaan AI secara semena-mena oleh pihak tertentu.
Koordinator Penelitian Koalisi Seni, Ratri Ninditya, mengatakan bahwa Indonesia harus memprioritaskan kepemilikan data dari yang bersangkutan, terlebih musisi/seniman, sebagai langkah utama untuk meregulasi penggunaan AI.

Ratri Ninditya (Ninin) / Dok. Gratiagusti Chananya Rompas
“Kalau dia (pengembang AI) bisa memiliki dan memanfaatkan data-data tadi, sudah selayaknya dia memberikan bayaran buat data-data yang diambil itu. Negara juga bisa meregulasi pemanfaatan atau penarikan datanya akan jadi milik siapa nanti,” jelas Ratri saat wawancara dalam seminar terbuka Koalisi Seni di kawasan Melawai, Jakarta Selatan (3/5/2024).
“Secara logika, pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan atau pengembang AI ini adalah terkait mining data yang mereka ambil dari pihak tertentu itu tadi. Selama dia (orang yang menggunakan AI) menghasilkan sesuatu dari memanfaatkan karya ciptaan orang lain, berarti dia sudah wajib memberi bayaran atas penggunaan karya-karya itu,” tambah Ratri.
Selain itu, Ratri juga menyebutkan persoalan royalti harus dibagikan secara adil dan merata untuk semua yang terlibat dalam penciptaan suatu karya. Pengamat yang juga dikenal sebagai seorang penyair ini menegaskan bahwa para pengembang AI juga harus memiliki perhatian dari pengambil kebijakan atas andil mereka sebagai penyedia platform pendukung, terutama bagi musisi atau seniman yang ikut menggunakannya.
“Setiap musisi atau seniman yang digunakan karyanya jelas harus menerima royalti dari pemanfaatan karya mereka, tetapi kita juga perlu memerhatikan hak dari penyedia AI pula. Begini, perangkat AI kan sangat bergantung dengan kualitas prompter (instruksi yang diberikan pada model kecerdasan buatan) yang mereka miliki. Nah, yang membuat prompt itu tadi juga manusia. Jadi royalti untuk yang bikin prompter juga harus diberikan,” tutur Ratri.
Berdasarkan pengamatan Ratri, mayoritas musisi atau seniman di Indonesia saat ini masih menganggap AI berada pada level teman diskusi atau brainstorm saja, dan belum menjadi alat utama mereka dalam berkarya.
Pun demikian, Ratri juga mengaku suatu saat, AI bisa saja berada pada level yang lebih tinggi, dan dapat menggantikan peran dari beberapa pekerjaan di sektor industri kreatif.
“Memang tidak akan sepenuhnya menggantikan sih. Ya, gini deh umpamanya. Sekarang aja kalau bayar tol udah enggak ada orang dan dilayani oleh mesin. Walau begitu, kadang-kadang mesinnya suka error, terus dibantu orang lagi. Di industri kreatif juga sama, mungkin memang enggak menggantikan sepenuhnya, tetapi pasti dapat mengurangi beberapa pekerjaan,” ucapnya.
Menyadari semua itu, dapat disimpulkan bahwa setiap perkembangan dari efisiensi teknologi pasti mempunyai risiko tersendiri di dalamnya. Namun, manusialah yang tetap akan memegang peranan utama.
Dalam kasus ini, AI digadang-gadang dapat menggantikan atau bahkan menghilangkan beberapa pekerjaan. Ini tidak hanya berlaku pada sektor industri kreatif saja, tetapi juga pada sektor-sektor industri lainnya.
Oleh sebab itu, para pengambil kebijakan di Indonesia sangat diharapkan agar segera menciptakan regulasi yang tepat sasaran untuk menangani persoalan beserta risiko-risiko yang ditimbulkan dari kehadiran kecerdasan buatan.
Eksplor konten lain Pophariini
Vendaz Tuangkan Kejujuran Emosional dalam Single 111
Proyek musik solo asal Tulungagung, Vendaz kembali menyapa pendengar lewat rilisan terbaru berjudul “111”. Dirilis hari Jumat (01/08), lagu ini menjadi ruang paling personal bagi Fendy, otak di balik Vendaz untuk menyampaikan keresahan terdalamnya …
Othersuck Rilis Kita Adalah Satu, Serukan Persatuan Lewat Nada Parodi
Band asal Blora, Othersuck merilis single bertajuk “Kita Adalah Satu” pada Rabu (25/07). Lagu ini menjadi penanda semangat baru dari unit yang digawangi Rio Cepuk pada vokal, Asik dan Yugo (gitar), Ricky Wongso (bas, …