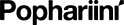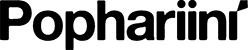Ribut-Ribut Royalti, Cerminan Mental Pribumi

Atmosfer kemenangan menyeruak dari para anggota AKSI (Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia) lewat kanal media sosial masing-masing anggotanya. Upaya untuk menegakkan keadilan dan mengentaskan gap sosial dengan membangun narasi antara ‘pencipta lagu yang miskin dan penyanyi yang kaya’ dirasa mulai membuahkan hasil. Masa kejayaan pencipta lagu tampak cerah terlihat.
Sementara teman-teman penyanyi tier satu mulai saling berkomunikasi. Bertanya satu sama lain. Mencari validasi atas kasus yang berjalan; Ari Bias VS Agnez. Upaya tersebut membuahkan hasil, lebih dari 30 penyanyi bersepakat membuat asosiasi bernama VISI (Vibrasi Suara Indonesia). Salah satunya Duta Sheila On 7. Bahkan kawan berkelakar, “Jika pak Duta sudah posting sesuatu, artinya ekosistem musik Indonesia sedang tidak baik-baik saja.” Salute untuk aktor intelektual di baliknya. Yang mengupayakan tegak lurus UU Hak Cipta dan berjuang dengan cara yang elegan (berserikat).
Kenapa elegan menjadi penting? Karena sejatinya yang diperjuangkan untuk ekosistem yang lebih baik, bukan mencari siapa yang salah lalu diberikan ganjaran hukum pidana sebagai efek jera. Hukum pun dibuat bukan untuk mewakili satu kelompok saja.
Klaim pendapatan yang tidak semestinya diamplifikasi menjadi cerita yang menyedihkan dan tidak adil. Hanya ratusan ribu yang didapat dari salah satu pintu royalti (performing rights), lantas menghakimi pihak lain berbuat curang. Padahal masih ada nilai royalti lain yang tidak diungkap, yang nilainya jauh lebih besar dan sudah dinikmati hasilnya.
Sayangnya, pihak LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) juga enggan memberikan klarifikasi. Memilih tidak menanggapi. Sehingga narasi ‘pencipta miskin’ mulus mendapat simpati publik.
Sementara prinsip royalti yang diterima dari LMK adalah passive income yang sifatnya tidak tetap, ia bisa menyusut ataupun meroket sesuai dengan seberapa banyak lagunya digunakan. Maka penting sekali transparansi hadir di sini. LMK bisa membuka datanya.
Karena kenyataannya, hits lagu tidak berbanding lurus dengan besarnya pendapatan royalti. Kisah dari Melly Goeslaw di bawah ini akan membuka pikiran kita tentang bagaimana lagu bekerja dan menghasilkan nilai ekonomi.
“Saya sempat berandai-andai, sambil berhitung dengan pandangan awam. Misal nih lagu Cinta Sejati saya lagi hits, filmnya juga hits, yang download di iTunes banyak dan yang streaming di Spotify banyak. Logikanya yang bawain di karaoke harusnya juga banyak, di cafe juga banyak, di hotel dll juga banyak, penyanyinya juga juga manggung hampir setiap hari bawain lagi ini. Tapi saat menerima laporan dari LMK kok gak seindah yang dibayangkan?” ungkap Melly.
Ia pun mengaku kerap menyampaikan komplain ke LMK secara langsung namun tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas dan perhitungan yang transparan. “Oleh sebab itu Undang-undangnya lah yang perlu direvisi terutama yang berkaitan dengan tata kelola royalti. Menurut saya ini langkah terbaik daripada gugat menggugat. Dan sebaiknya kita semua mengawal hal ini hingga mencapai hasil yang baik bagi kita semua,” harap Melly.
Lebih lanjut, Melly mengatakan ada juga lagu yang sedang hits di era tertentu, rupanya tidak serta merta cocok digunakan di semua tempat. “Jadi kalau saya pergi karaoke sama ibu-ibu, mayoritas yang dinyanyikan itu ya lagu-lagu itu saja, meski ada pilihan lagu-lagu baru. Misal lagu ‘Gala Bunga Matahari’ Sal Priadi lagi hits banget, tapi di hotel, cafe, dan tempat karaoke tidak memutarnya karena tidak cocok, lagunya tentang kematian. Jadi orang lebih memilih lagu lain yang sesuai dengan perasaannya dan menutup acara karaoke selalu dengan lagu ‘Kemesraan’.”
Melly juga bercerita tentang lagu “Bagaikan Langit” dan “Salah” milik POTRET, konon semua acara membawakan lagu tersebut. “Tapi di mana? Ternyata di Jaksel saja. Jadi pasti kalau dilihat royaltinya ya tetap tidak sebesar gaung lagunya,” jelasnya.
Masalah Utama Itu Distribusi
April 2021, perkara soal royalti juga mencuat. Saat itu ramai dengan isu cover–mengcover yang hak ekonominya salah sasaran. “Gue yang ciptain, dia yang monetize di YouTube.” Kenapa sampai terjadi? Lagi-lagi karena administrasi dan LMK yang belum menjalankan perannya dengan baik.
Maret 2022, saya menulis soal royalti dengan judul “Bukan Soal Rupiah, Tapi Hak yang Terarah” di Pophariinii. Tiga tahun berselang, masalahnya masih sama. Yang diperjuangkan bukan hak, tapi soal rupiah. Sehingga perjuangan yang dilakukan seperti tak tentu arah.
Sebuah LMK menuntut pidana salah satu event organizer. Para pencipta kompak melarang penyanyi atau band menyanyikan karyanya. Yang terbaru, soal hak pertunjukan juga dikenakan pasal pidana. Di mana ganti rugi maksimal adalah tujuannya.
Sementara para ‘pemain kakap’ di industri musik menjalankan bisnisnya seperti biasa, mendulang rupiah. Jutaan lagu yang tidak diklaim, royaltinya tertampung di LMK-LMK. Lalu kemana uangnya? Bagi-bagi ke para ‘pemain’ adalah tuduhan yang paling mudah dicerna.
Lantas adakah yang meneriakkan dengan lantang soal ini? Tentang sebuah masalah utama soal distribusi. Semua senyap. Baru Agnez Mo di podcast Deddy yang berbicara. Karena ia terkena kasus. Speak up adalah hal yang tidak terhindarkan. Kepepet.
Tapi bagaimana situasi pra Agnez? Setahu saya, tidak ada yang mau saling tunjuk hidung. Karena apa? Karena semuanya teman satu sama lain. Kita telah berbudaya untuk saling hormat dan mengasihi. Apa pun masalahnya, kita mudah untuk saling memaafkan bukan? Ya, jadi lebih baik mempertontonkan langkah heroik dengan substansi yang berputar-putar dan tidak pada intinya. Straightforward memang bukan budaya timur. Terima saja.
Sengkarut royalti di industri musik ini dahulu (paling tidak satu dekade yang lalu) bukan isu yang sama besar dengan pembajakan. Dan kini menjadi isu prioritas setelah platform digital masuk dan menjadi alat hitung royalti dan medium baru untuk mendapatkan penghasilan. Era di mana semua bisa dimonetisasi dengan transparan. Era di mana kebutuhan hari-hari lebih besar daripada nilai kesepakatan awal yang sudah dibangun pencipta dengan penyanyi dan band kala itu.
Tafsir Serampangan
Namanya juga negara demokrasi, menuntut hak adalah hak setiap warga negaranya. Maka silakan diperjuangkan. Memilih dengan cara yang agresif pun dipersilakan tapi apakah sudah dikalkulasi secara matang dampak ke depannya? Ini yang harusnya jadi perhatian lebih dalam. Jangan sampai orang jadi takut bernyanyi dan enggan menciptakan lagu karena takut dituntut dengan pidana. Maka degradasi budaya pun bisa saja terjadi jika tafsir serampangan terhadap Undang-Undang untuk kepentingan diri sendiri terus dilakukan.
Akui saja kita memang malas. Malas mencerna produk hukum. Malas membereskan administrasi. Malas membicarakan kejelasan hak sejak awal. Malas memperjuangkan sesuatu yang nilainya belum terlihat. Namun kalau sudah ada angka, baru ribut! Hal yang paling parah, banyak yang memanfaatkannya untuk jadi ladang cuan.
Situasi ini mirip seperti yang dijelaskan pakar Asia Tenggara asal Prancis, Denys Lombard, yang menulis Le Carrefour Javanais (Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu). Lombard bilang para pejabat kolonial dahulu bingung mengapa orang Pribumi banyak berleyeh-leyeh daripada menyelesaikan pekerjaan dalam konteks kolonial. Atas dasar itu, Lombard menyimpulkan, sifat malasnya bukan melekat. Tapi karena kondisi tanam paksa dan bentuk perlawanan terhadap kolonial.
Musisi dan pencipta lagu memang sedang melakukan perlawanan sejak dulu. Bentuk kemalasannya adalah upaya perlawanan bagi para ‘kolonial’ di industri musik. Tapi mereka lupa, zaman sudah berubah. Indonesia sudah merdeka. Pemerintah pun selalu mendengar dan menuangkannya dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).
Alih-alih memperjuangkan hak yang belum terakomodir dalam UUHC, jika dilakukan dengan cara yang keliru justru hanya mempertontonkan sifat keserakahan dan manipulatif sebagai individu.
Tak ada cara lain menyikapi perjuangan para teman-teman komposer dan musisi dengan saling menurunkan ego dan kepentingan golongan, serta fokus kepada upaya rekonstruksi lembaga-lembaga yang sudah diatur oleh UUHC agar bisa transparan dan akuntabel.
Jika angka royalti yang tidak sesuai, maka perjuangkanlah angkanya. Jika izin yang jadi masalah, maka sepakatilah bentuk perizinan yang tidak menyusahkan dan menimbulkan kerugian baru. Jika industri ini bisa kompak, fokuslah pada dampak berganda yang bisa dihasilkan secara ekonomi. Hal ini akan jauh lebih bermanfaat untuk masa depan ekosistem musik Indonesia.
Eksplor konten lain Pophariini
Vendaz Tuangkan Kejujuran Emosional dalam Single 111
Proyek musik solo asal Tulungagung, Vendaz kembali menyapa pendengar lewat rilisan terbaru berjudul “111”. Dirilis hari Jumat (01/08), lagu ini menjadi ruang paling personal bagi Fendy, otak di balik Vendaz untuk menyampaikan keresahan terdalamnya …
Othersuck Rilis Kita Adalah Satu, Serukan Persatuan Lewat Nada Parodi
Band asal Blora, Othersuck merilis single bertajuk “Kita Adalah Satu” pada Rabu (25/07). Lagu ini menjadi penanda semangat baru dari unit yang digawangi Rio Cepuk pada vokal, Asik dan Yugo (gitar), Ricky Wongso (bas, …