Ruwetnya Hubungan Musik dengan Politik

Beberapa waktu ke belakang, warganet ramai membicarakan sejumlah musisi yang masuk pada arena politik atau kekuasaan. Pertama adalah Delpi Suhariyanto, personel band beraliran punk, Dongker, yang tercatat menjadi kader partai politik Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Kedua adalah Jogja Hip Hop Foundation yang manggung di Kompleks Museum Kedhaton Keraton Yogyakarta dalam rangka peringatan Serangan Umum 1 Maret.
Mengapa keputusan mereka dipermasalahkan oleh para netizen? Berdasarkan komentar para netizen yang terbaca di Twitter, alasan yang kerap muncul adalah mengacu pada sejarah punk yang lahir dalam semangat anti kemapanan, yang dengan demikian mestinya bersikap kritis atau bahkan menolak sistem super mapan bernama negara. Dengan demikian, keterlibatan anggota band punk dalam politik praktis adalah hal yang tidak hanya aneh, tapi bertentangan dengan spirit musik punk itu sendiri.
Kedua, terkait Jogja Hip Hop Foundation, Marzuki Mohamad atau Kill the DJ, sebagai pentolan grup hip hop dengan lirik berbahasa Jawa tersebut, beberapa kali terlibat aktivisme seperti protes atas penyerangan diskusi buku di LKIS Yogyakarta tahun 2012 dan kritik atas kebijakan penataan kota Yogyakarta lewat lagu berjudul “Jogja Ora Didol”. Dengan tampilnya grup yang berdiri tahun 2003 tersebut di Keraton, maka netizen menganggap hal demikian sebagai keberpihakan terhadap penguasa, yang seolah berlawanan dengan sikap Kill the DJ selama ini baik dari sisi aktivisme maupun lagu-lagu yang ditulisnya.
Beberapa waktu ke belakang, warganet ramai membicarakan sejumlah musisi yang masuk pada arena politik atau kekuasaan. Adalah Delpi Suhariyanto, personel band punk, Dongker, yang tercatat menjadi kader partai politik, dan Jogja Hip Hop Foundation yang manggung di Kompleks Museum Kedhaton Keraton Yogyakarta.
Kasus Delpi dan Jogja Hip Hop Foundation hanyalah dua contoh dari banyaknya kasus keterkaitan antara musik dan politik. Di Pilpres yang panas tahun 2019, kita tahu, Slank, bersama dengan beberapa musisi lainnya seperti Raisa, Yuni Shara, dan Andi /Rif memutuskan untuk memberi dukungan terang-terangan terhadap salah satu kandidat yakni Jokowi. Sementara di kubu seberangnya yakni kubu Prabowo, dukungan muncul dari para musisi seperti Nissa Sabyan, Pasha Ungu, Ariel Hermansyah, dan beberapa lainnya.
Pertanyaannya, etiskah musisi punya sikap politik tertentu? Atau lebih persisnya, etiskah musisi berpihak pada kekuasaan? Bahkan dalam kasus Delpi, pertanyaannya bisa lebih tajam: etiskah musisi menjadi bagian dari kekuasaan?
Musisi tertentu memiliki popularitas yang membuat mereka diidolakan oleh banyak orang. Dengan demikian, sikap dan omongan musisi tersebut menjadi didengarkan dan bahkan diikuti. Di sinilah irisan sederhana antara musik dan politik: sama-sama berhubungan dengan sikap orang banyak. Saat ramai musisi saling dukung mendukung capres pada pemilu 2014 maupun 2019 (dan pastinya nanti di tahun 2024), alasan mereka rata-rata sederhana, yang kira-kira bisa disarikan seperti ini, “Kami musisi punya massa, dan kami harus memanfaatkan popularitas kami untuk turut menentukan nasib bangsa.”
Di Pilpres yang panas tahun 2019 Slank, bersama musisi lainnya seperti Raisa, Yuni Shara, dan Andi /Rif memutuskan untuk memberi dukungan terang-terangan terhadap salah satu kandidat yakni Jokowi. Sementara kubu seberangnya yakni kubu Prabowo, dukungan muncul dari para musisi seperti Nissa Sabyan, Pasha Ungu, Ariel Hermansyah, dan beberapa lainnya.
Tentu sah-sah saja jika musisi atau kelompok musik mengarahkan penggemarnya sendiri pada suatu sikap tertentu. Namun bagaimana kita bisa menakar hubungan antara musik dan politik sehingga dalam suatu peristiwa dinilai etis, sedangkan dalam peristiwa lainnya dianggap kurang etis? Mengapa bisa, kita seolah menormalkan Raisa atau Nissa Sabyan yang mendukung salah satu pasangan capres, tetapi kemudian menganggap keterlibatan Delpi dan Jogja Hip Hop Foundation dengan kekuasaan sebagai suatu sikap hipokrit?
Faktor pertama yang bisa ditunjuk adalah perkara konsistensi. Kita cenderung kurang peduli pada sikap politik musisi pop yang dalam kiprahnya menghasilkan karya-karya yang “netral” dan “apolitis” seperti lagu cinta-cintaan atau pengalaman manusia pada umumnya. Pada Raisa yang kita kenal menyanyikan lagu “Jatuh Hati” atau “Could it Be”, rasanya kita tidak akan menuduhnya inkonsisten jika tiba-tiba banting setir masuk arena politik. Demikian halnya dengan Ahmad Dhani yang konsisten menciptakan hits-hits lagu cinta, juga ternyata memang direspons fine-fine saja saat terlibat politik praktis (kecuali tentu oleh musuh politiknya). Artinya, musisi yang tidak punya rekam jejak sikap politis, tidak akan dituduh macam-macam saat kemudian bersentuhan dengan domain politik.
Jika konsistensi menjadi salah satu alasan dalam menilai hubungan etis antara musik dan politik, maka teranglah mengapa orang-orang seperti Delpi Dongker atau Kill the DJ kemudian dicibir oleh sebagian netizen karena sikap mereka dianggap tidak sesuai dengan karya-karyanya selama ini. Pada musisi yang karya-karyanya sudah dikenal memiliki sikap politis, para pendengarnya cenderung memiliki harapan tersendiri terhadap sikap politis tersebut. Mungkin, para pendengarnya sudah merasa terinspirasi oleh cara pandang politik idolanya (yang kritis, yang melawan), eh ternyata idolanya tersebut malah berubah haluan(menjadi berada di pihak yang sama dengan yang dulu dilawan dan dikritisi).
Pertanyaannya, etiskah musisi punya sikap politik tertentu? Atau lebih persisnya, etiskah musisi berpihak pada kekuasaan? Bahkan dalam kasus Delpi, pertanyaannya bisa lebih tajam: etiskah musisi menjadi bagian dari kekuasaan?
Faktor kedua adalah tergantung pada bagaimana kita mengartikan apa yang dimaksud dengan “sikap politis”. Kita menuduh Delpi dan Kill the DJ telah mencampuradukkan musik dan politik. Namun lebih persisnya, bukan perkara campuraduk antara musik dan politik, tetapi campuraduk antara musik dan politik yang pro-penguasa. “Sikap politis” adalah hal yang lumrah dalam dunia musik: Harry Roesli mencipta lagu berjudul “Malaria” yang membuat ia kerap terkena teror rezim pemerintah Orba, Iwan Fals rajin membawakan lagu-lagu yang membuat telinga penguasa memerah seperti “Bento” dan “Bongkar”. Dalam posisi seperti Harry Roesli dan Iwan Fals, “sikap politis” diartikan sebagai sikap kritis terhadap penguasa, sekaligus keberpihakan terhadap “yang lemah”, “yang ditindas”.
Sikap politik yang pro-penguasa menjadi problem saat terdapat kebijakan penguasa yang dianggap merugikan rakyat. Misalnya, dalam konteks Yogya, belum lama ini terbit Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2021 yang melarang adanya unjuk rasa di wilayah Malioboro dan Keraton. Larangan tersebut secara tidak langsung menunjukkan sikap Keraton yang antikritik. Dengan maraknya pandangan semacam itu terhadap penguasa, maka keberpihakan Jogja Hip Hop Foundation pada Keraton dengan turut memeriahkan acara yang diselenggarakan oleh istana menjadi tampak mengecewakan di mata sebagian netizen.
Jadi, bagaimana seharusnya “sikap politis” musisi atau kelompok musik? Kelihatannya, jika seseorang atau band sudah sedari awal menyuarakan sikap politis tertentu, apa tidak lebih baik jika musisi atau kelompok tersebut berusaha konsisten di jalannya?
Jadi, bagaimana seharusnya “sikap politis” seorang musisi atau kelompok musik? Kelihatannya, jika seseorang atau band sudah sedari awal menyuarakan sikap politis tertentu, apalagi dengan keras, hingga meraup banyak penggemar yang mengikuti prinsip mereka, apa tidak lebih baik jika musisi atau kelompok tersebut berusaha konsisten di jalannya?
Menjadi konsisten tentu sukar, dan pasti dalam perjalanan hidup, terjadi beraneka perubahan dalam cara pandang seseorang. Jika kita berada di posisi Delpi misalnya, bertahan dengan idealisme punk kelihatannya memang tidak mudah mengingat posisi dirinya yang memang sudah lahir di tengah keluarga politisi. Dalam suatu wawancara di TikTok, Delpi sudah mendapat semacam peringatan dari kawan-kawan ayahnya, bahwa masuk politik akan membuat siapapun kehilangan nurani. Namun rasanya Delpi punya pertimbangan lain yang lebih personal, sehingga tawaran terjun ke arena politik sukar untuk ditampiknya. Demikian halnya dengan Jogja Hip Hop Foundation yang kelihatannya juga punya justifikasinya sendiri.
Di sisi lain, menjadi konsisten adalah sekaligus “bertanggung jawab” pada para penggemar yang pernah diubah cara pandangnya oleh si musisi atau si band tersebut. Jika Iwan Fals atau Slank telah membuat massanya menjadi kritis terhadap penguasa, maka rasanya menjadi kurang bertanggung jawab jika mereka tiba-tiba berubah haluan menjadi pro-penguasa. Pendengarnya kemungkinan “merasa ditinggalkan”.
Jika Iwan Fals atau Slank telah membuat massanya menjadi kritis terhadap penguasa, maka rasanya menjadi kurang bertanggung jawab jika mereka tiba-tiba berubah haluan menjadi pro-penguasa. Pendengarnya kemungkinan “merasa ditinggalkan”
Jika ditarik sedikit dari dunia filsafat, Jean-Paul Sartre, filsuf Prancis, adalah orang yang mendeklarasikan diri sebagai seorang ateis dan ia meraup banyak penggemar oleh karena sikap tegasnya tersebut. Di masa tuanya, Sartre mengaku bahwa menjadi ateis adalah pilihan yang melelahkan, tetapi ia merasa mesti tetap konsisten karena sudah banyak orang mengikuti jalannya.
Selain itu, “sikap politis”, terutama yang condong pro-penguasa, mesti mempertimbangkan kebijakan dari penguasa itu sendiri. Jika penguasa dinilai zalim dan merugikan, maka alangkah kurang etisnya jika musisi atau kelompok musik kemudian memutuskan untuk berpihak bersama mereka. Saat negara merepresi rakyat, membungkam pendapat, menghasilkan kebijakan yang menguntungkan segelintir orang, pada momen demikian justru musisi dan kelompok musik menjadi salah satu harapan yang bisa diandalkan orang-orang untuk berkeluh kesah, membuat masyarakat terhibur sejenak dengan mendengarkan lirik-lirik yang relevan dengan problem riil sehari-hari. Bahkan para musisi, lewat musik-musiknya, menjadi harapan juga untuk membuat telinga penguasa memerah, membuat otoritas merasa tersindir sehingga syukur-syukur dapat melakukan evaluasi dan mengubah kebijakan.
Jadi, susah juga ya, menjadi musisi yang punya sikap politis sedari awal? Harus konsisten, harus peka terhadap suara rakyat. Iya, memang sulit, maka itu, jika tidak benar-benar siap, tempuh saja jalur karir bermusik yang lebih aman dengan bersikap apolitis. Fokus saja pada lagu-lagu yang langsung relate dengan selera pasar seperti perkara cinta-cintaan atau perjuangan dalam mencari jati diri tanpa perlu ditambahkan bumbu-bumbu kritik pemerintah, perubahan sosial atau pesan-pesan khas SJW. Nanti kalau sudah terkenal, bisa kok tiba-tiba berkiprah di bidang politik dan memanfaatkan suara penggemar.
Eksplor konten lain Pophariini
Sajama Cut Cerita Rahasia Setiap Lagu di Album COWABUNGA
Sajama Cut resmi mengeluarkan album penuh terbaru berjudul COWABUNGA hari Jumat (11/07). Album ini menampilkan total 9 trek yang diedarkan bersama The Bronze Medal Recording Co. sebagai naungan. Ketika akhir April lalu menanyakan kepada …
Lullavile Melepas Album Penuh Perdana llierauoy
Setelah 2 tahun absen sejak perilisan single “Distorted”, unit alternatif Lullavile kembali menyapa pendengarnya lewat album penuh perdana mereka yang bertajuk llierauoy (24/06). Beranggotakan Enggar pada bas, Yami (drum), Uwi (gitar, vokal), …
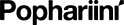





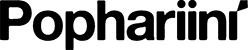

Mungkin ini yang nama nya penghakiman dan pertanggung jawaban karya ⚖️
Ariel Hermansyah siapa ya? Baru tau 🙏