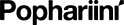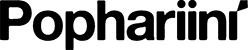Skena Musik Bandung Baik-Baik Saja Kok

Harus diakui awalnya saya memiliki keresahan yang sama dengan kebanyakan generasi Bandung 90an, terutama yang sudah memilih untuk menetap di Jakarta. Kanal Youtube, Noise Land episode Ada Apa Dengan Bandung? dipandu Oomleo dan Ardhito Pramono yang mengundang Riko Prayitno dan Alvin Yunata -dua nama yang besar di Bandung era 90/2000an- menjadi salah satu bentuk paling nyata perihal keresahan akan skena musik Bandung sekarang ini.
“Bandung sudah hilang pesonanya. Bandung masih kota kreatif?” Pernyataan itu melengkapi pernyataan yang bahkan pernah dilontarkan di 2019 kalau, “Bandung sudah kalah ketimbang kota lain”. Yang terakhir ini terjadi di 2019 dalam sebuah diskusi berjudul “Apakah Bandung Masih Menjadi Kota Musik?” yang saya hadiri saat itu di Saklar, Rumah Musik Harry Roesli yang digelar oleh Beritabaik.id
“Jadi kalau ditanya apakah Bandung masih menjadi kota musik? Enggak, Bandung mah sudah kalah dengan kota-kota lain. Bandung bukan kota musik, mungkin lebih tepat kalau Bandung adalah kota musisi,” ucap Bob Edrian (kurator, musisi, peneliti sound art), yang kemudian diamini oleh peserta lain. Ditambah pernyataan “Kita hanya terjebak dalam romantisme histori kalau Bandung adalah kota musik,” itu adalah salah satu kenyataan yang juga menohok banyak pihak.

Niskhra, Amenkcoy, Idhar Resmadi, dan Bob Edrian dalam diskusi “Apakah Bandung Masih Kota Musik?” / Foto: Beritabaik.id
“Bandung dulu mah gini.. Bandung dulu mah gitu..” pernyataan seperti ini juga kerap keluar dari mereka yang mengalami era kejayaan Bandung di 90/2000an, termasuk saya dan kebanyakan teman-teman seangkatan. Kami resah dan menuntut Bandung untuk begini-begitu. Lalu menawarkan bantuan, membuka pintu lebar-lebar pada generasi di bawah kami untuk mengangkat kota yang membesarkan kami ini. Tapi sebentar, memangnya apa yang terjadi di Bandung dan mengapa kami yakin kalau mereka membutuhkan bantuan?
Masa keemasan kultur independen Bandung terjadi di era 90 – 2010an. Pure Saturday, Puppen, Pas Band, gempita GOR Saparua yang bergeser ke gigs intim di pub kecil seperti Bar 69 dan TRL. Juga media alternatif seperti majalah Trolley dan Ripple. Clothing anak skateboard/ surfing/band yang tengah berjaya pun turut menjadi sponsor gigs musik. Puncaknya di 2010an kebanyakan radio Bandung memiliki program musik indie dipandu langsung oleh musisinya. Substereo di radio OZ FM, dipandu Rekti “The SIGIT” dan saya; Pop Circle di Rase FM dipandu Risa Sarawati (saat itu Homogenic/Risa Sarasvati) dan Felix Dass/Dimas Ario sebagai produser, Ucay (saat itu Rocket Rockers) dan Yas Budaya “Alone At Last” dengan “Rockomedy” di Hard Rock FM; plus program televisi STV, “Ziggie Wiggy” yang membahas skena musik Indie.
Para middle man seperti Marin Ramadhani dan Helvi (FFWD records) yang bergerak di balik layar menghubungkan band dengan pihak luar termasuk luar Bandung pun turut memperkuat rantai industrinya. Juga kehadiran Common Room di 2000an dan Spasial di 2010an sebagai hub kreatif yang mempertemukan musik, budaya dengan seni rupa kontemporer. Kesemua infrastrukturnya terasa begitu sempurna dan saling menopang.
“Bandung dulu mah gini.. Bandung dulu mah gitu..” pernyataan ini kerap keluar dari mereka yang mengalami era kejayaan Bandung di 90/2000an
Namun memasuki 2015 satu persatu elemen ini berguguran. Diawali dengan insiden AACC di 2008 yang berujung kepada sulitnya izin panggung musik indie. Media, clothing, tempat event/gigs di Bandung era 2010an berguguran dan hanya tersisa beberapa. Keresahan paling utama ketika pensi/gigs besar tidak menampilkan band Bandung sebagai bintang utama. Dari Barasuara, Danilla, Payung Teduh, Fourtwenty dan Kelompok Penerbang Roket. Bahkan festival internasional seperti Lalala Fest juga emoh mencantumkan band Bandung di posternya. Tentu hal ini tidak salah karena merupakan seleksi alam. Dan kalau merasa hal itu baik-baik saja, dan tidak ada yang salah, ini yang kemudian merisaukan kami para “abang-abangan” skena musik Bandung yang kini menetap di Jakarta.
Tapi ternyata Bandung 2010an – sekarang (sebelum pandemi) baik-baik saja. Abyan Nabilio alias “Acin” vokalis/gitaris The Panturas, menulis sebuah tanggapan yang menarik pada video Ada Apa Dengan Bandung dengan tulisan “Apa Kabar Bandung?”. Beberapa pernyataannya dipatahkan, seperti jumlah band Bandung yang masih banyak, dan parameter kesuksesan musisi dengan digit follower. Hanya memang papan iklan dan media belum bisa ditembus. Generasi sekarang juga merasa menanggung beban semu kejayaan Bandung era dulu. Problem lainnya adalah keenggan EO mengundang dan menghargai band daerahnya sendiri, juga kemungkinan bandnya sendiri belum menemukan bentuk manajemen yang baik serta yang unik adalah mungkin musisi Bandung memang tidak peduli dengan hal-hal duniawi.
Untuk yang terakhir harus diakui kalau attitude urang Bandung se-“antik” itu. Faktor kota yang dikelilingi pegunungan, cuaca dingin, kota yang relatif kecil mudah dijangkau ke mana-mana, membuat Bandung tidak akan pernah bisa disamakan dengan Jakarta. Karena Bandung sendiri adalah kota metropolitan terbesar sekaligus ibu kota Jawa Barat. Bila bicara sejarah di era kolonial dulu Bandung dirancang sebagai tiruan kota besar Eropa dan sempat dimaksudkan untuk menggantikan ibu kota. Maka Bandung juga selalu memiliki kiblatnya sendiri, seperti ketika Batavia berkembang sebagai ibu kota Indonesia, orang Bandung malah senang meniru orang Eropa/Belanda. Semata karena kotanya disiapkan sebagai pengganti Batavia yang didesain menyerupai kota Eropa. Dari situ istilah Paris Van Djava muncul. Maka itu walaupun berdekatan, Bandung akan selalu berbeda dengan Jakarta.
Terlepas dari semua kenyataan di atas, hemat saya mau tidak mau skena musik Bandung pada akhirnya harus mampu beradaptasi dengan “kecepatan” Jakarta. Tol Cipularang adalah contoh awal yang sudah terjadi. Memangkas perjalanan lima jam melaui gunung Puncak berliku menjadi lewat jalan lurus 2,5 jam yang dibuka sejak 2006 adalah berkah sekaligus kutukan. Kota dengan daya cipta kreatif yang tinggi harus berdampingan dengan ibu kota yang sangat kapital, dengan ritme kerja yang super cepat. Bandung yang ritmenya selow (santai) dengan cuaca sejuk, dikelilingi pegunungan harus beradaptasi dengan ibu kota yang akan menggilas siapapun yang tidak bisa mengikuti kecepatannya.
mau tidak mau skena musik Bandung pada akhirnya harus mampu beradaptasi dengan “kecepatan” Jakarta
Bandung lalu dipenuhi wisatawan plat B setiap akhir pekan dan berefek baik pada roda perekonomian. Tempat-tempat nongkrong ngopi dan kuliner pun bermunculan menangkap peluang ini. Tentunya dengan memasang harga Jakarta yang turut menaikan biaya nongkrong di Bandung. Padahal Bandung masih bergantung pada kultur nongkrong. UMR kepala tiga komaan yang ditetapkan pemerintah pun dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ini. Jangankan mencukupi, sudah rahasia umum kalau penghargaan nominal pada pekerja kreatif Bandung sendiri belum begitu ideal dan hal ini adalah problem lain yang masih terjadi hingga kini.
Bayangkan entah apa yang terjadi dengan kultur kreatif dan musik di Bandung jika kereta cepat Jakarta-Bandung sudah ada. Jangan sampai warga aslinya terpinggirkan oleh orang Jakarta yang akan memilih tinggal di Bandung dan bolak balik ke kantor dengan kereta cepat. Seperti yang kini lumrah terjadi di daerah-daerah pegunungan Bandung atas. Ketika warga aslinya harus pindah atau mengalah menjadi ART/tukang di lingkungan tinggalnya sendiri karena tanahnya sudah dijual dan daerahnya sudah dipadati oleh orang kota Bandung.
penghargaan nominal pekerja kreatif Bandung sendiri belum ideal dan ini problem lain yang masih terjadi
Jika Acin menyimpulkan masalah ada di pihak EO, saya rasa bentuk promosi dan komunikasi skena band Bandung sendiri bisa diperbaiki. Terlebih di era media sosial yang bergantung dengan komunikasi dan bahasa visualnya. Untuk urusan visual ini masih banyak seniman yang bisa diajak bekerja sama yang memang lebih paham urusan estetika visual. Dan dibutuhkan kepekaan terhadap tren. Salah satu poster Records Day Out Bandung ini contohnya. Memakai gambar duo elektronik yang awal tahun sempat menggemparkan dunia karena membubarkan diri, sebagai ilustrasi perayaan rekaman fisik di pertengahan 2021? IMHO, bisa memilih objek lain sih.
Soal beban semu kejayaan Bandung 90an adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dokumenter Saparua menjadi salah satu contoh pembuktian bahwa apa yang terjadi di era 90-2000an adalah perlawanan terhadap kemapanan. Terjadi karena pada saat itu kaum muda arus samping ingin menjadi budaya tandingan, menyuarakan kalau punya pilihan hidup yang berbeda. Bisa dibilang saat itu Bandung berusaha melawan arus utama, dan menembus Jakarta. Lalu apa yang dilawan saat ini? Karena internet distribusi musik lebih gampang, video musik pun idem. Bahkan kini label rekaman besar pun memutar otak ketika harus bersaing dengan arus samping dalam distribusi karya di dunia internet dan medsosnya.
Alih-alih menerima uluran tangan dari abang-abangan yang resah, mereka tentu lebih memilih melakukan resistensinya sendiri dengan selow namun tetap konsisten berkarya
Perlu diingat juga generasi skena independen 90an Bandung pada saat dulu berhasil karena upaya keras tanpa ada bantuan/ketergantungan dari pihak lain alias DIY (do it yourself). Saya merasa ini juga yang terjadi di anak sekarang. Alih-alih menerima uluran tangan dari abang-abangan yang resah, mereka tentu lebih memilih melakukan resistensinya sendiri dengan selow namun tetap konsisten berkarya. Juga kalau melihat dengan yang pernah terjadi di tahun 70an, ketika Bandung diramaikan oleh musik dan media seperti Aktuil, hal ini terjadi lagi di 90an/2000an dengan Pure Saturday, The Sigit dan majalah Trolley dan Ripple. Jadi mungkin siklus ini akan berulang dua-tiga dekade ke depan? Akankah terjadi letupan budaya kreatif Bandung di 2020-2030? Kita lihat saja nanti.
Records Store Day Bandung 2021 yang seharusnya digelar Juni ini (ditunda karena kasus positif Covid19 yang meningkat tajam) membuktikan skena musik Bandung masih ramai. Rencananya diisi oleh 20-an tenant, 10 band yang akan merilis album (sebelum pandemi jumlahnya dua kali lipat), keriaan ini sebetulnya membuktikan kalau skena musik Bandung memang baik-baik saja kok. Dan yang utama tidak perlu membanding-bandingkan dengan kota lain (Jakarta).
____
Eksplor konten lain Pophariini
Lirik Lagu Hari Yang Mantap Tercipta Sangat Personal oleh Gusti Irwan Wibowo
“Hari Yang Mantap” jadi salah satu lagu dari album ENDIKUP milik mendiang Gusti Irwan Wibowo yang paling banyak berseliweran di media sosial sejak kepergiannya. Tak hanya karena musik dan liriknya yang ringan, tapi juga …
Vendaz Tuangkan Kejujuran Emosional dalam Single 111
Proyek musik solo asal Tulungagung, Vendaz kembali menyapa pendengar lewat rilisan terbaru berjudul “111”. Dirilis hari Jumat (01/08), lagu ini menjadi ruang paling personal bagi Fendy, otak di balik Vendaz untuk menyampaikan keresahan terdalamnya …