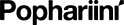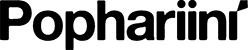1998 Dalam Rekaman Pop Bawah Tanah Indonesia

Sampai saya berbincang dengan Alexandra J Wuisan akhir April lalu, saya tak pernah tahu kalau “Biara” yang dia gubah bersama Sieve adalah refleksinya pada kondisi Indonesia 1998. Sebagai salah satu fragmen ‘detik-detik jang menentukan’ dalam sejarah bangsa, momentum jatuhnya kekuasaan Orde Baru 22 tahun silam memang ditangkap dalam banyak bentuk. Tak hanya orasi dan aksi, dia juga menjelma pada komik, puisi, film, dan yang menjadi bahan tulisan ini: musik.
Sandra –sapaan Alexandra– masih ingat betul saat terjadi gonjang ganjing 1998 di Indonesia dia sedang di Hong Kong. Berangkat pada 1997 untuk magang, Sandra tak bisa pulang. Padahal di tengah ketidakpastian 1998, yang diembannya di rantau tak cuma rindu tapi juga khawatir pada sanak saudara yang ada di tanah air.
“Saya enggak mau political tapi masa itu memang sangat berpengaruh ya,” kata Sandra.
Di usia yang masih cukup muda dan tertahan di negeri orang tentu bukan sesuatu yang mengenakkan baginya. Tapi bagaimana lagi, pulang bukan pilihan. Orang tuanya melarang karena alasan keamanan. Sandra pun hanya bisa menumpahkan sedu sedannya pada bait puisi yang memang biasa dia tulis. Puisi yang kemudian dia ubah jadi lagu dan direkam saat membentuk Sieve bersama Regina Rina dan Richard Riza di tahun 1999.
“Akhirnya jadilah lagu “Biara” yang juga jadi judul dari mini album tersebut,” ucap dia.

Sieve era 2000 an / foto: Benny Kusnoto
Tahun 1998 memang bisa dilihat dari sudut mana saja kau berdiri. Itu tentu bukan waktu yang mudah buat semua. Jika banyak orang merekamnya pada peluh aksi dan teriakan orasi, maka yang Alex rekam adalah kebutuhan atas rasa aman. Aman yang dia analogikan bisa didapat dengan munajat di biara, bertawakal pada sang Maha. Maka terciptalah itu bait syahdu:
Sampaikan salamku / Di alam rantau, dimana / Jarak bertemu dan sayap / Meranum
Sementara di tahun yang kurang lebih sama, Nyoman, Helmy, Aldy, Aroel, Ekky, dan Molly yang saat itu tergabung dalam band Planet Bumi merekam memorinya atas 1998 dari gelanggang aksi.
Planet Bumi memang bukan band politis. Tetapi pengalaman hampir tiap hari turun ke jalan turut memberi inspirasi bagi kekaryaan mereka. Apalagi di tahun segitu Planet Bumi masih kenceng-kencengnya naik panggung bersama sejumlah kompatriot indies Jakarta era awal seperti Pestolaer, Wondergel, Rumahsakit, dan lain-lain.
Kepada saya, Nyoman, vokalis Planet Bumi menyebut setidaknya ada dua lagu yang mereka rekam berdasarkan pengalaman 1998. Lagu itu berjudul “Aku Tetap” dan “Jarum Pentul”. Dua lagu ini masuk ke mini album kedua mereka “Lihat Kebunku Penuh Dengan Bunga” (1998) yang dirilis secara mandiri dan debut album penuh mereka “Dunia Cermin” yang dirilis label dua tahun setelahnya.
Sekadar informasi, saat itu Nyoman dan Molly masih berkuliah di Universitas Indonesia. Dua personel lainnya Aroel dan Aldy di Trisakti.

Planet Bumi di era 90an / dok. Planet Bumi
“Lagu-lagu ini dibuat sebelum Mei. Soeharto belum turun. Akan lah. Jadi memang sudah kelihatan tanda-tandanya. Tinggal menunggu waktu,” kata Nyoman.
Seperti kita semua tahu, beberapa tahun sebelum 1998 memang gelagat kemuakan rakyat atas tirani Orde Baru sudah mulai terasa. Mimbar bebas banyak digelar berkelindan dengan represi aparat yang mulai gencar mengincar. Ini ditangkap Planet Bumi dalam bagian awal lirik “Jarum Pentul”: Tak ada kebebasan untuk bicara, kawan dan lawan tak ada beda.
Lantas mereka seolah meramal kejatuhan rezim pada bagian lirik: “Yang berjaya akan kalah yang tersudut kan menang. Semua menjadi sama rata!”
“Makanya dinamain “Jarum Pentul”. Kan tajam gitu. Jadi biar kecil tapi nusuk,” ucap Nyoman soal lagu tersebut.
Keresahan atas kondisi sosial politik Indonesia di masa-masa itu tentu tak hanya dirasakan di Jakarta atau di negeri orang hingga tak bisa pulang. Di Bandung, Pure Saturday pun merekam keresahan yang sama.
Lagu dengan tema sosial politik sebetulnya sudah dikenal sejak kuintet Suar, Ade, Arief, Adhi, dan Udhi memulai debutnya pada 1995. Sebut saja “Enough” yang bercerita tentang perang atau “Coklat” yang menganalogikan aparat dalam warna hingga bahasa beatnik. Kentara pada lirik “Coklat berlari bagai babi”.
Tapi pada sophomore mereka “Utopia” yang dirilis setahun setelah Soeharto lengser, nampaknya tema ini cukup punya tempat. Tema sosial politik dan transisi diri menyambut zaman baru cukup pekat.

Pure Saturday era 90an / dok. istimewa
Jika mengacu pada tulisan Idhar Resmadi di “Pure Saturday; Based on a True Story” (UNKLBooks, 2013), para personel Pure Saturday terutama Suar dan Adhi memang cukup larut dalam gerakan reformasi saat itu. Mereka sebetulnya bukan aktivis kampus, tapi di masa itu, mahasiswa yang turun ke jalan tak pandang bulu.
“Rasanya, pada masa itu, mau aktivis atau bukan mahasiswa memang kerap turun ke jalan untuk ikut demonstrasi,” kata Suar.
Adhi menambahkan kalau saat itu memang masa-masa suram. Dia yang saat itu masih berkuliah di ITB menyebut kerap menginap di tenda massa bersama kawan kampunya Arian (Seringai) dan Herry Sutresna (Morgue Vanguard). “Ini kan memang masa-masa suram, zaman Soeharto.”
Lewat situasi ini maka muncullah “Kaca” yang liriknya tegas menggambarkan bagaimana carut marut saat itu. Selain “Kaca” lagu-lagu lain juga saya asumsikan punya semangat sama. Meski kebanyakan diambil dari perspektif diri pada kondisi yang terjadi.
“Gala” misalnya dibuka dengan lamunan indah “Cerah nian mimpi di sana” tapi kandas karena “telah hilang semakin jauh palingkan muka”. Lalu “Labirin”. Berdurasi 8 menit dengan intro depresif sepanjang satu menit 50 detik. Bait terbaiknya ada sejak awal: “Buta sudah rasa di mana? Telah lelah kita percaya. Pergi semua sakit jauh dari sini”.
Diakhiri dengan lirik introspektif yang dinyanyikan berulang: “Adakah ini akan berakhir ataukah ini adalah akhirnya”.
Indiepop dan Politik
Menjadi politis dalam indiepop sebenarnya lazim. Bukankah menjadi independen dalam konteks 1986 (era birth of indie) adalah politik itu sendiri?
Tembang The Orchids “Defy the Law” misalnya merekam kepincangan kebijakan poll-tax Margaret Thatcher yang mengundang protes sepanjang 1989 hingga pecah aksi di Maret 1990. “Clearer” dari Blueboy ditulis melankolis sebagai kritik atas kebijakan kontroversial amandemen pasal 28 dalam Local Government Act 1988 di Inggris yang dinilai diskriminatif.
Yang mendedikasikan liriknya dan didapuk sebagai band politis juga ada. Sebutlah McCarthy yang kemudian berevolusi jadi Stereolab, The Housemartins, atau yang mahsyur seperti Manic Street Preacher. Oh iya, jangan lupa juga Pulp. Sulit disangkal kalau “Common People” adalah bentrok kelas dan “Cocaine Socialism” adalah sindiran bagi sosialis sampanye.
Di konteks lokal mungkin tak sebanyak itu. Paling yang cukup konsisten Efek Rumah Kaca. Lain yang cukup lekat di ingatan saya adalah “Unperfect Sky” dari Elemental Gaze bersama Sigit dari Tigapagi. Tapi tak bisa juga saya sebut hanya mereka, karena makna di balik lagu tak semua saya tahu.
Sementara 22 tahun berlalu sejak reformasi ternyata lukanya masih terasa. Efek Rumah Kaca merekam asa korban yang setia berdiri setiap Kamis di depan Istana dalam “Hilang” (2011). The Panturas mengungkitnya dalam cita rasa yang personal lewat “Sunshine” (2018).
Ironis memang. Bahkan, lagu-lagu yang diulas di awal tulisan ini pun masih relevan.
Refrain “Kaca” milik Pure Saturday misalnya masih pas kita nyanyikan dengan lantang di hari-hari ini. Saat kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah cenderung plin plan dan membingungkan publik, layaklah kita sangsikan apakah negeri ini masih sanggup berdiri?
Pun begitu dengan “Jarum Pentul”. Entah oleh siapa, tapi baru saja saya dengar kalau ternyata masih ada ancaman pembunuhan kepada pewarta karena berita.
Sampai sini saja? Oh tentu tidak. Karena kalau dirunut daftarnya tentu akan lebih panjang. Sepanjang jejak putar balik fakta yang dilempar pendengung di linimasa setiap harinya.
Sejenak saya lepas keyboard dan merenung: Apakah mungkin sebenarnya kita hidup di dunia yang tak pernah kemana-mana? Hanya berganti kuasa tapi berakhir dengan luka sejarah yang sama.
Lalu entah kenapa terngiang lagi bait terakhir “Labirin”: “Adakah ini akan berakhir ataukah ini adalah akhirnya?”.
Eksplor konten lain Pophariini
MAKO. Rilis Single dan Video Musik Hidupmu
Setelah mempersembahkan single perdana “Angkasa” Februari lalu, musisi sekaligus dokter muda Rayhan Maditra, yang dikenal dengan nama panggung MAKO. kembali melanjutkan langkahnya lewat perilisan single “Hidupmu” bersama Redrose Records sebagai naungan. Berbeda …
Supergrup Bandung, BandSAT! Lepas Crazy In Love
Grup musik baru asal Bandung, BandSAT! resmi memperkenalkan diri lewat perilisan single perdana bertajuk “Crazy In Love”. Single ini sekaligus menjadi penanda awal dari perjalanan musikal proyek kolaboratif lintas generasi yang terdiri dari lima …