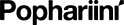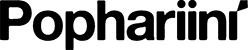Spotify dan Betapa Narsisnya Kita

Betapa enaknya mencari musik di zaman sekarang. Tinggal buka Youtube, Spotify, Joox, atau piranti streaming services lainnya. Dalam hitungan detik, voila, musik yang Anda cari semudah menggeser telunjuk tangan Anda. Coba bayangkan saat saya remaja dulu. Untuk mencari musik yang diinginkan saya mesti blusukan ke loakan di Cihapit dan Dipati Ukur, bolak-balik mengamati senarai “thanks list” sebagai satu-satunya kanal informasi di kaset/CD, melihat daftar ulasan di majalah musik, mendengar radio setiap pagi, hingga nongkrongin MTV sepulang sekolah.
Itu pun tidak semua musik yang saya sukai itu ada. Kalau sedikit beruntung, kita menitip pada teman yang sering ke luar negeri. Selain lewat cara di atas, juga sudah mulai muncul “budaya berbagi”: saling pinjam meminjam kaset/CD, barter mixtape, memesan barang-barang cokro (hacking), MP3 traders, hingga menitipkan hard disk eksternal kita ke seorang teman untuk berbagi koleksi yang seringkali disisipkan berbagai “bonus” yang disukai Kaum Adam. Perlu banyak usaha untuk memuaskan hasrat keduniawian mengonsumsi musik.
di Indonesia, 88% responden mendengarkan musik melalui streaming service dan sekitar 51% di antaranya menghabiskan waktu satu sampai empat belas jam per minggu untuk memanfaatkan layanan tersebut
Segala sesuatu serba terbatas. Kalau Anda bukan orang yang “ngulik” dan punya pergaulan luas, maka konsumsi musik Anda hanya sebatas apa yang tersedia di radio, TV, atau toko-toko rekaman yang ada. Sungguh membosankan!
Saat revolusi digital mulai memasuki industri musik, cara kita dalam memproduksi dan mengonsumsi musik ternyata turut berubah. Pada 1999, revolusi musik digital dimulai. Seorang anak muda Amerika bernama Shawn Fanning menciptakan Napster yang membuat semua orang di berbagai penjuru negara bisa saling berbagi lagu. Napster menandai suatu era baru bahwa secara radikal musik bisa didapatkan secara “gratis”. Akses terhadap konsumsi musik pun berubah. Industri musik kehilangan kontrolnya karena akses itu membuat siapapun (selama memiliki koneksi internet) bisa memperoleh musik secara cuma-cuma – saling berbagi lagu secara ilegal.
Genderang perang antara industri musik melawan pembajakan digital pun seolah dimulai. Puncaknya, ketika band Metallica menuntut hukum Napster. Bagi industri itu tindakan amoral karena melanggar hukum. Sedangkan, bagi kami yang saat itu haus dengan informasi dan konsumsi musik, kemunculan teknologi peer-to-peer seperti suatu berkah tersendiri. Pada akhirnya revolusi digital itu menciptakan akses demokratisasi.
Sejak saat itu kelindan antara industri musik dan teknologi digital kian berkembang. Beragam perangkat mulai muncul dari iPod, iPod Touch, MP3 players, smartphones, iTunes, dan lain-lain. Seiring perkembangan waktu, cara kita mengonsumsi musik kemudian dipengaruhi oleh kelindan teknologi digital: digital download, ringtone, ring back tone, dan yang saat ini sedang tren yaitu online streaming services.
Kita sebagai pendengar musik kemudian seperti terjebak pada satu labirin panjang yang diciptakan oleh berbagai penemuan teknologi digital.
Tak bisa kita pungkiri bahwa saat ini keberadaan piranti online streaming services semacam Spotify, Joox, dan Apple Music menjadi digdaya di industri musik digital. Keberadaan mereka merevolusi cara industri musik bekerja, termasuk juga mengendalikan pasar musik digital terbesar saat ini.
Secara global, Spotify telah memiliki 70 juta premium subscriber, diikuti Apple Music dengan 30 juta pelanggan di akhir 2017. Kemungkinan akan terus bertambahnya subscriber sangat masuk akal dengan makin banyaknya tawaran program, inovasi, dan kemudahan cara bayar dari setiap piranti streaming services tersebut. Untuk di Indonesia sendiri, berdasarkan Online Music Streaming Survey 2018 oleh Daily Social kepada hampir dua ribu responden di Indonesia, 88% responden sudah mendengarkan musik melalui streaming service dan sekitar 51% di antaranya menghabiskan waktu satu sampai empat belas jam per minggu untuk memanfaatkan layanan tersebut. JOOX menjadi layanan streaming terpopuler di Indonesia dengan angka 70,37% pengguna, disusul oleh Spotify (47,70%), LangitMusik (28,51%), SoundCloud (19,75%), dan Apple Music (16,50%).
Melalui kehadiran streaming services ini memang kita sebagai pecinta musik dimanja tanpa ampun. Dengan jutaan katalog lagu yang tersedia, saya bisa mencari lagu-lagu dari berbagai era dan dari beragam genre musik. Saya kini tak perlu lagi blusukan untuk mencari musik. Bahkan saya bisa mencari musik sambil rebahan di kamar atau di depan laptop saat bekerja. Meski itu semua tak didapatkan secara gratis tentu saja. Kalau Anda punya sedikit uang lebih, Anda bisa berlangganan secara premium agar mendapatkan beberapa keistimewaan dibandingkan versi gratisan. Biaya yang terhitung sangat murah (kisaran lima puluh ribu per bulan) agar Anda dapat menyelami jutaan lagu di dalamnya dengan kualitas musik lebih baik dan musik tanpa jeda iklan yang sangat menganggu.
Kehadiran streaming services ini pun bukan tanpa kritik. Kemajuan teknologi ini menyisakan satu persoalan baru. Para musisi menjerit bahwa nilai royalti yang terlampau kecil (bayangkan hanya sekitar Rp 8 rupiah per stream), Musisi sekaliber Thom Yorke (vokalis Radiohead) mengecam industri streaming services sebagai “The last desperate fart of a dying corpse”. Sudah tak ada harapan lagi di industri musik dunia. Kita sebagai pendengar musik kemudian seperti terjebak pada satu labirin panjang yang diciptakan oleh berbagai penemuan teknologi digital.
kebudayaan dematerial: corak kebudayaan baru konvergensi dari segala sesuatu yang semula fisikal (material) beralih rupa menjadi logika-logika biner dalam bentuk digital
Seperti yang dijelaskan oleh Jacques Attali dalam buku Noise: The Political Economy of Music (2009) bahwa penemuan berbagai teknologi dalam musik akan mengubah transformasi sosial yang ada dalam masyarakat: “In a half-century’s time, an invention that was meant to stabilize a mode of social organization became the principal factor in its transformation. Beyond music, the process of this technologizal and ideological mutation brought on an entire transformation of a paradigm and a world vision”. Kehadiran piranti streaming services itu mungkin membantu kita memudahkan mencari musik yang kita inginkan. Namun, kehadiran streaming services itu pun memunculkan suatu keniscayaan baru bahwa algoritma dan kecerdasan buatan mampu mengonstruksi pilihan dalam selera musik kita di masa yang akan datang.
Dematerial dan Personal
Revolusi digital mengubah cara mengonsumsi musik menjadi kian “dematerial” dan “personal”. Kita sudah memasuki “kebudayaan dematerial”. Sebuah corak kebudayaan baru di mana terjadi konvergensi dari segala sesuatu yang semula berupa fisikal (material) kemudian beralih rupa menjadi logika-logika biner dalam bentuk digital. Dari waktu ke waktu rasanya cara orang mengonsumsi musik telah berubah dari semula yang kita dengarkan melalui piringan hitam, kaset, dan CD kemudian semua sudah beralih rupa menjadi online music streaming.
Musik jadi kian kehilangan fungsinya sebagai ruang reflektif, kontemplatif, atau membentuk kesadaran kita. Musik tak lebih hanya sekedar “latar” yang dengan serba mudah kita skip
Bagi orang-orang reverie nostalgic mendengarkan musik melalui piranti musik fisik (kaset, piringan hitam, atau CD) memiliki keseruan dan kekhusyukan tersendiri yang tidak tergantikan ketika mendengar lewat streaming services. Ada keasyikan ketika mulai memutar kaset atau piringan hitam sambil menikmati Minggu sore. Mengamati ilustrasi artwork dengan penuh apresiasi. Atau membolak-balik sleeve cover demi menghapal lirik lagu favorit kita. Ada satu sensasi di mana kita hampir melibatkan semua indera dalam tubuh kita: mencium bau kertas, memandang artwork, hingga mendengarkan lengkingan gitar yang keluar dari perangkat audio. Ada totalitas tubuh kita ketika mendengarkan secara fisikal.
Bagi para kaum luddites tentu memandang keberadaan online music streaming services sebagai “dying corpses”. Keberadaan budaya dematerial ini bukan tanpa konsekuensi. Pada akhirnya budaya dematerial ini kian menegaskan musik makin kehilangan “aura”-nya. Pesona musik jadi kian hilang dan tak jauh sebatas fungsi-fungsi banal semata. Musik jadi kian kehilangan fungsinya sebagai ruang reflektif, kontemplatif, atau membentuk kesadaran kita. Musik tak lebih hanya sekedar “latar” yang dengan serba mudah kita skip. Saking mudahnya juga kita tak peduli siapa musisi yang sedang kita dengar. Kita tak lagi peduli bagaimana ilustrasi artwork dari cover album tersebut. Apalagi kita sudah tidak lagi mempedulikan secara saksama lirik lagunya. Kita hanya membutuhkan musik untuk menemani kita di café, berkendara di mobil, atau saat sedang bekerja di depan laptop. Akhirnya dematerialisasi ini mengubah musik sama banalnya dengan minum kopi, kendaraan pribadi, dan perkakas rumah tangga yang lebih dipertimbangkan unsur “fungsionalnya”.
Dematerialisasi ini juga mengakibatkan kreativitas musisi yang terkonstruksi dari kebutuhan yang dibentuk oleh piranti digital ini. Muncul genre musik terbaru yang disebut “Spotify-Core”. Istilah ini merujuk pada kreativitas musisi yang mengacu pada kebutuhan akan industri musik streaming. Dalam artian, seorang musisi akan mendapat uang dari musik-musik yang melayani kebutuhan tersebut. Musik yang hanya butuh intro singkat, chorus “nendang”, dan durasi pendek.
Keberadaan teknologi digital
justru membuat kita makin narsistik!
Hal ini lah yang membuat kebudayaan dematerial ini menjadi sebuah world-view baru. Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang, kita akan kehilangan musik progresif rock dan art-rock yang terbiasa dengan intro panjang dan berbelit. Atau musisi jazz yang penuh improvisasi dan intuisi yang “njelimet”. Mungkin saja para musisi tak perlu lagi membuat sebuah lagu seperti maha-karya “Bohemian Rhapsody”. Streaming services ini hanya akan mengonstruksi para pendengar dan pasar baru: instan, pendek, cepat, dan “nendang”.
Kebudayaan dematerial akan membuat kita, sebagai pendengar musik, akan kehilangan musik dengan satu konsep storytelling yang utuh. Salah seorang teman saya, seorang musisi folk yang jenius, menegaskan dia hanya akan merilis singel saja. Menurutnya, di era digital sekarang, konsumen hanya memerlukan singel ketimbang satu album utuh. Daripada capek-capek bikin album dengan waktu lebih lama dan biaya lebih mahal, lebih baik merilis singel yang lebih efektif di era sekarang. Toh, kalau pun ada album biasanya yang didengarkan juga singel-singelnya saja. Bahkan singel-singel itu yang kemudian masuk ke dalam beragam playlist yang dikurasi oleh streaming services untuk dikonsumsi kepada kita dengan beragam tajuk seperti “Indie Akustik”, “Lagu Galau”, “Playlist Senja”, atau “Kopi Sore”.
Pandangan teman saya, sang musisi folk jenius itu, bukan cuma dia seorang. Strategi ini kemudian mulai populer ketika beberapa musisi saat ini lebih memilih merilis singel ketimbang album. Boleh jadi, kita mungkin akan kehilangan sebuah album konsep yang jenius di masa yang akan datang. Kalau saja David Bowie hidup di era streaming ini, mungkin tidak akan ada The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars atau kita tidak akan menemukan lagi album konsep semisal Tales of Mystery and Imagination dari The Alan Parsons Project.
Ketakutan saya kemudian muncul. Musisi terbelenggu kreativitasnya dan menghamba logika yang dibangun budaya dematerial ini. Mereka lebih memilih berkarya mengikuti logika pasar streaming. Mereka lebih mengulik big data ketimbang makna musik itu sendiri. Pada akhirnya kita sebagai pendengar musik hanya akan mengonsumsi musik-musik yang dibentuk oleh logika tersebut.
Teknologi digital juga membentuk suatu kecenderungan baru bahwa musik jadi kian personal. Streaming services berhasil digemari karena kian relevan dengan personalisasi medium yang tampak hype dalam beberapa tahun terakhir ini. Kebudayaan digital telah mengubah informasi yang semula bersifat push information menjadi pull information. Jika dulu informasi itu menjejali kita, maka saat ini kita bisa memilih media dan informasi yang relevan dan sesuai kita inginkan. Alasan itu pula yang membuat saat ini kita lebih tertarik mengikuti (follow) para selebgram, blogger, atau vlogger. Kita cenderung menyukai sesuatu yang sesuai persona kita dari musik, fesyen, kopi, make up, hingga otomotif.
Di tengah budaya digital yang konon serba terbuka, serba luas, dan serba demokratis justru yang terjadi cenderung paradoks. Kita jadi lebih sempit. Kita memiliki kecenderungan untuk membangun imaji melalui medium-medium yang kita bentuk sendiri. Keberadaan teknologi digital justru membuat kita makin narsistik!
Kita akan kehilangan musik progresif rock dan art-rock atau musisi jazz yang penuh improvisasi dan intuisi yang “njelimet”
Piranti streaming services mampu membentuk imaji yang kita inginkan melalui beragam fitur-fitur di dalamnya. Alih-alih mencoba untuk mengeksplorasi musik-musik lainnya. Fitur-fitur dalam streaming services itu membuat kita justru terjebak pada selera diri kita sendiri. Dengan logika algoritma saja kita terus menerus dihadapkan pada musik yang kita dengar dan kita sukai. Melalui beragam rekomendasi yang serupa, tanpa sadar sebetulnya kita itu makin narsis.
Selain itu, streaming services juga membuat kita “terjebak” pada pilihan-pilihan yang kita buat. Melalui piranti streaming, kita bisa membuat senarai playlist yang sesuai dengan keinginan kita pribadi. Kita bisa membuat beragam momen untuk diri sendiri. Kita bisa membuat beragam soundtrack untuk diri kita sendiri. Streaming services memungkinkan kita membuat senarai playlist yang bisa kita buat dan relevan menemani keseharian kita: dari mulai semangat pagi, ngopi sore hari, obat galau, hingga menemani kala senja. Kita kemudian keranjingan untuk terus membuat senarai playlist dari setiap momen kita pribadi: playlist liburan, playlist kerja, playlist pacaran, dan playlist di jalan, dll. Daniel Ek, selaku CEO dari Spotify, bahkan berujar bahwa apa yang mereka lakukan lebih menjual “momen” ketimbang “musik” itu sendiri: “We’re not in the music space, we’re in the moment space”.
Gejala narsistik makin akut ketika kita bisa mempertontonkan snobisme kita. Streaming services memfasilitasi kita untuk men-share playlist dan lagu yang tengah kita dengarkan untuk membentuk persepsi dari pengikut (follower) media sosial kita. Semua itu makin memperkuat bahwa kehadiran streaming services ini justru bukan menjual musik itu sendiri, tapi lebih kepada membentuk citraan dan narsisme kita pribadi. Bahwa citra diri kita itu lah yang “dijual”. Bukan musik itu sendiri. Gejala narsistik akut ini lah yang kemudian muncul dari personal medium yang dibentuk oleh beragam streaming services tersebut.
Saat ini kita lebih tertarik mengikuti (follow) para selebgram, blogger, atau vlogger
Teknologi adalah suatu keniscayaan. Di masa yang akan datang teknologi digital sudah bukan semata perangkat untuk problem-solving atau sekedar “extensions of man” semata. Dia sudah menjelma menjadi “world-view” baru yang ternyata mengubah semua elemen dasar kehidupan kita. Sejak teknologi itu sendiri muncul kita memang tidak pernah memiliki kebebasan dalam menentukan hakikat diri kita sendiri, termasuk juga pilihan-pilihan bebas dalam menentukan selera musik kita. Seseorang pernah berkata jika dalam benak kita memandang bahwa dunia itu sebuah palu, maka apapun yang kita lihat itu terdiri dari paku.
____
Eksplor konten lain Pophariini
5 Band Cirebon Pilihan Restu Yawendra Losing Fight
Setelah bulan lalu mengangkat band-band Wonosobo pilihan Budi ‘Youthfall’, bulan ini kami mendaulat Restu Yawendrs, vokalis/gitaris Losing Fight untuk memberikan rekomendasi band dan musisi asal kotanya, Cirebon. Lagi-lagi kami mendapat nama-nama baru berbagai genre …
Compass Luncurkan Kampanye bersama Kiki Ucup, Denisa, dan Coki KPR
Merek sepatu lokal kebanggan Indonesia, Compass, resmi meluncurkan kampanye terbaru bertajuk “Selangkah, Searah” pada hari Senin, 7 Juli 2025. Kampanye ini menjadi perayaan atas perjalanan pribadi, arah yang sejalan, serta kekuatan dalam terus melangkah …