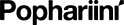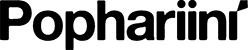Dangdut Tahan Banting Karenamu, Terima Kasih Remy Sylado

Tulisan ini dibuat untuk mengenang seorang jenius bernama Japi P. A. Tambayong atau kalangan musik mengenalnya sebagai Remy Sylado. Pada tulisan ini, saya mengelaborasi adu pendapat antara Remy Sylado dan William H. Frederick terkait musik dangdut sebagai penghormatan kepada Remy Sylado yang wafat pada Senin lalu (12/12/22).
“Mau saya satroni itu William.
You ngawur, Bill!
Tak begitu caranya meneliti sosiologi musik.
Pakek kuping, mata, data, nalar!”
Remy Sylado
Nukilan di atas adalah reaksi Remy Sylado yang naik pitam terhadap doktor sosiologi Universitas Ohio, USA[1], William H. Frederick karena ihwal dangdut. Ia menuliskan protesnya pada kolom kontak pembaca majalah Tempo empat Agustus 1984 terhadap tulisan William yang terbit sekitar sebulan sebelumnya. William menulis esai pendek yang bertajuk “Mengapa Dangdut Rhoma jadi Penting” pada majalah Tempo 30 Juni 1984. Di dalam tulisannya, William menuliskan “Ingat, Remy Sylado pernah mencap bahwa dangdut adalah ‘musik tahi anjing’”. Sebagai balasan, Remy menggunakan hak jawabnya, “Bukan saya yang ngatain dangdut ‘musik tahi anjing’, tapi Benny Soebardja”.
Remy berhak marah karena tuduhan William, tetapi William juga tak bisa disalahkan. Apalagi William tak persis menuduh Remy sebagai orang yang mengatakannya, melainkan ‘mencap’ akan umpatan itu. Jika merujuk ke pemaknaan, kata mencap memiliki makna yang begitu beragam, mulai dari memberikan cap, melegitimasi, atau mengamini—bisa dikaitkan pada konteks Remy sebagai redaktur majalah terkait; maupun menganggap, menyatakan, atau menamai—agaknya makna kedua ini yang menyinggung Remy. Atas apa yang mereka pahami atas terma “mencap”—apalagi ada perbedaan suku bangsa di antara keduanya—, adu pendapat antara mereka berdua mengenai dangdut lebih dalam dari sekadar saling tuduh.
William H. Frederick menulis esai pendek yang bertajuk “Mengapa Dangdut Rhoma jadi Penting” pada majalah Tempo 30 Juni 1984. Di dalam tulisannya, ia menuliskan “Ingat, Remy Sylado pernah mencap bahwa dangdut adalah ‘musik t*hi anjing’”.
Pasalnya William tahu betul jika bukan Remy lah yang mengutuk dangdut sedemikiannya. Sebagai bukti, pada artikel William yang bertajuk “Rhoma Irama and The Dangdut Style: Aspects of Contemporary Indonesian Popular Culture” (1982), ia menuliskan jika “musik tahi anjing” itu Ia dapat dari kutipan di dalam naskah Remy yang bertajuk “Musik Pop Makin Ndeso”(1980). Sekali lagi, William dapat umpatan itu dari kutipan di dalam naskah Remy, bukan langsung Remy yang mengucapkannya. Alhasil William telah membaca esai tersebut dengan saksama dan memahami betul bagaimana kutipan itu terjalin di dalam naskah Remy.
Alih-alih berburuk sangka dengan menganggap William tengah lalai atau luput, Saya justru mengira jika William berlaku demikian karena ia membela Rhoma mati-matian. Apalagi William telah meneliti Rhoma Irama beberapa tahun sebelumnya dan menerbitkan artikel ilmiah legendaris yang bertajuk “Rhoma Irama and The Dangdut Style: Aspects of Contemporary Indonesian Popular Culture” (1982). Di lain soal, Rhoma juga tahu betul siapa yang membelanya, bahkan nama William juga masih ia sebut di podcastnya hingga hari ini (dengar di Bisikan Rhoma #51 bersama Ketua Umum dan Pembina FORSA yang diunggah 4 November 2022 di YouTube). Singkat kata, mereka punya hubungan yang baik, dan tentu William memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan apa yang Ia teliti. Maka, berfriksi dengan Remy pun William jabani.
Sebagai balasan, Remy Sylado menggunakan hak jawabnya, “Bukan saya yang ngatain dangdut ‘musik t*hi anjing’, tapi Benny Soebardja”.
Memang dari trajektorinya, Remy terkesan menyudutkan dangdut. Bagaimana tidak, ketika Remy tengah menjadi redaktur Majalah Aktuil (1970-1975) dan redaktur majalah Top (1973-1976), omongan miring terhadap dangdut bak mengalir deras. Bahkan ketika perkataan Benny Soebardja “dangdut musik tahi anjing” itu dimuat di majalah Top tahun 1975, Remy tengah bertugas sebagai redaktur di majalah tersebut. Yang artinya, perkataan Benny telah diketahui Remy sebelumnya dan direstui untuk terbit. Lebih lanjut, di bawah naungan Remy, majalah-majalah itu menjadikan dangdut sebagai bahan cercaan.
Atas dasar itu, tulisan “Mengapa Dangdut Rhoma jadi Penting” pada majalah Tempo 30 Juni 1984 karya William adalah upayanya membela Rhoma Irama dari pelbagai tuduhan miring para intelektual dan kritikus ketika itu. Jika kita membaca tulisan William yang jadi muara kemarahan Remy, tersemat rasa kesalnya kepada mereka yang menjadikan Rhoma sebagai bulan-bulanan. Ada beberapa hal yang disoal, seperti soal kekaryaan yang dianggap imitasi, menghamba pada selera massa, tak menjaga patokan kebudayaan yang semestinya, mengomersialkan seni dan agama, serta mencampurkan politik ke arena hiburan. Maka William berusaha keras mengartikulasikan jika sukses yang didapat Rhoma Irama bukan sebuah kebetulan seperti yang dituduhkan, melainkan sudah ia persiapkan. Satu per satu persoalan coba William tuntaskan, semisal menunjukkan bagaimana kejelian meramu lagu, kekayaan musikalitas, kesadaran kontekstual dalam penciptaan lirik dan keberpihakan—yang terbalut sebagai kegeniusan seorang Rhoma Irama.
Ketika Remy tengah menjadi redaktur Majalah Aktuil (1970-1975) dan redaktur majalah Top (1973-1976), omongan miring terhadap dangdut bak mengalir deras. Bahkan perkataan Benny Soebardja “dangdut musik t*hi anjing” dimuat di majalah Top tahun 1975, saat bertugas sebagai redaktur di majalah tersebut
Sudah barang tentu, tulisan tersebut untuk menyerang balik para intelektual dan kritikus musik yang menempatkan musik populer sebagai musik yang remeh dari segi konteks hingga ihwal estetika, dan Remy Sylado dianggap sebagai salah satunya. Maklum, musik populer sebagaimana bagian dari skema pasar diletakkan di posisi yang tak mengenakkan lantaran tak bisa ditempatkan sebagai magnum opus yang mencerahkan manusia. Remy pun ikut mengartikulasikannya secara lebih gamblang pada artikel panjangnya yang bertajuk “Musik Pop Indonesia: Satu Kebebalan Sang Mengapa” di majalah Prisma pada 6 Juni 1977. Di dalam tulisannya, Remy membukanya dengan, “Dan barangkali ini celakanya: pop sudah diterima sebagai suatu aib. Orang tak suka lama-lama menyiapkan hati pada diskusi pop, lantaran khawatir kehilangan penghargaan umum terhadap kesungguhannya berpikir” (1977, p. 23). Berabe bukan!
Beberapa sorotan yang penting di dalam naskah Remy adalah (1) “Pop Indonesia adalah melodi Amerika tapi lirik Indonesia”. (2) Musik pop adalah musik niaga yang niscaya muaranya hanya berkutat soal laba. (3) Mendudukkan pop musik dari pola musik, kecenderungan diksi, dan sebaran tema lagu. (4) Musik pop membicarakan cinta tanpa sikap penyelesaian, dan mayoritas lagu yang ujung-ujungnya pada pertanyaan mengapa. Dengan gaya pesimistis bak tulisan Theodor Adorno pada “The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception” (1944) atau “On Popular Music” (1941), musik pop telah habis dikuliti Remy. Jika Anda penggiat kajian musik pop, Anda wajib membacanya.
Beberapa sorotan penting di dalam naskah Remy adalah (1) “Pop Indonesia adalah melodi Amerika tapi lirik Indonesia”. (2) Musik pop adalah musik niaga yang niscaya muaranya hanya berkutat soal laba. (3) Mendudukkan pop musik dari pola musik, kecenderungan diksi, dan sebaran tema lagu. (4) Musik pop membicarakan cinta tanpa sikap penyelesaian, dan mayoritas lagu yang ujung-ujungnya pada pertanyaan mengapa
Lantas, apakah Dangdut juga menjadi sasaran? Remy memang tak secara spesifik menelaah musik dangdut di dalam tulisan tersebut. Bahkan kata dangdut hanya ditemukan tiga kali saja, itupun dalam satu konteks yang sama, yakni: dangdut sebagai perwujudan sosial Indonesia yang frustrasi atau kekanak-kanakan namun mendatangkan untung. Hal ini membuat musik dangdut dikomodifikasi sedemikian rupa. Namun tetap saja, tulisan Remy ini memiliki resonansi yang jelas pada dangdut. Apalagi Remy menguliti modus operandi dari musik pop Indonesia, yang kecenderungannya nyaris serupa dengan tema dan lirik pada musik dangdut. Alhasil, di bawah naungan Remy, konstelasi yang terjadi di medio 1970-1980an ini memosisikan dangdut di posisi yang tak strategis. Beruntung majalah Tempo justru berlaku sebaliknya, memberi tatapan positif pada musik dangdut dan orang-orang di dalamnya. Beberapa seri majalah ini justru memberikan beberapa edisinya khusus untuk menerjemahkan dangdut dengan lebih optimis.
Memang tak bisa disangkal jika Remy memang terkesan keras terhadap dangdut, tetapi saya pikir itu yang menarik untuk ditanggapi lebih, apalagi tulisannya selalu berdasar dari penelusuran dan riset yang Ia lakukan. Maka itu Ia tak segan mengkritisi pelbagai musik dengan percaya diri. Hal ini juga berlaku pada dangdut. Remy pada kolom kontak pembaca Tempo menulis,
Kata dangdut digunakan pertama kali Billy Silabumi di Aktuil 1970 sebagai ejekan. Kemudian saya pakai dalam kritik musik, kebetulan menandai gejalanya dengan pengamatan sosiologis atas daerah-daerah underdog (Sylado, 1984, p. 3).[2]
Remy memang tak secara spesifik menelaah musik dangdut di situ. Bahkan kata dangdut hanya ditemukan tiga kali saja dalam satu konteks yang sama, yakni: dangdut sebagai perwujudan sosial Indonesia yang frustrasi atau kekanak-kanakan namun mendatangkan untung.
Tercermin jika sikap Remy percaya diri dengan amatannya. Selain itu dari nukilan tersebut, terjelaskan dari mana muasal Remy memulai kritik demi kritiknya terhadap dangdut, yakni dangdut sebagai ejekan. Hal tersebut semakin diperkuat dengan posisinya menjadi redaktur majalah Aktuil, Top, serta lain sebagainya di tahun-tahun friksi antara dangdut dan yang bukan dangdut terjadi. Lantas pemahaman tersebut terkonfirmasi dari daerah-daerah pinggiran dan underdog yang ia telusuri.
Selain itu, “corak pop dengan sejumlah rasa sedih yang buntu tanpa jalan keluar, yang dimulai dari Patah hati itu, setidaknya telah menjadi pengalaman baru bagi semua cukong perekaman untuk mengeruk laba lewat kecengengan” (Sylado, 1977, p. 30). Industri kecengengan ini yang membuatnya merasa dangdut dan musik sejenis ditempatkan pada posisi yang hidup segan mati tak mau. Massa yang tak merdeka secara ekonomi juga menjadi alasan tak adanya kesadaran lebih. Hal ini juga membuat “kesempatan untuk melatih kuping pada musik-musik yang mulia, seperti musik Bach, Handel, Mozart atau Beethoven yang hadir dari sikap etis yang jelas, tak kunjung sampai (Sylado, 1977, p. 31). Alhasil masyarakat tidak dapat mengkritisi dan merdeka memilih musik yang mereka dengar karena urusan besok makan apa lebih merongrong pikiran. Dan hal tersebut teresonansi dari tulisan Remy yang ditujukan untuk Rhoma Irama juga dangdut,
Hal ini membuat musik dangdut dikomodifikasi sedemikian rupa. Namun tetap saja, tulisan Remy ini memiliki resonansi yang jelas pada dangdut. Apalagi Remy menguliti modus operandi dari musik pop Indonesia, yang kecenderungannya nyaris serupa dengan tema dan lirik pada musik dangdut. Alhasil, di bawah naungan Remy, konstelasi yang terjadi di medio 1970-1980an ini memosisikan dangdut di posisi yang tak strategis.
Waktu itu, bukan hal tersembunyi bahwa dangdut merupakan bagian tak terpisahkan dari dunia lampu merah, sebagai pelepasan semu dari suasana tenahak, frustrasi, dan luka sosial (Sylado, 1984, p. 3).[3]
Di mana dangdut menjadi bagian yang integral dari masyarakat dan menjadi wahana penghibur dari mereka yang kecewa serta kalah dalam bab kehidupan, khususnya ekonomi atau sosial. Atas dasar itu lah, Remy menyangsikan musik populer untuk dapat memberikan pencerahan.
Pikiran ini tentu sarat dengan Adorno di dua naskah yang saya sebut sebelumnya. Tentu kini hal tersebut dapat dikritisi, sejalan dengan pikiran Adorno yang juga sudah dikritisi oleh scholar lainnya, semisal Jurgen Habermas—bahkan kritik Habermas pun juga telah dikritisi oleh scholar yang lebih baru. Hal ini membuat kita dapat memosisikan dangdut lebih jernih dan tak senaas apa yang dipikirkan oleh Remy Sylado. Terlepas dari itu, amatan Remy tentang musik populer tentu menjadi jelas muasalnya. Dan tentu, Ia bukan orang yang menaruh dendam pada dangdut hingga memosisikan dangdut sedemikiannya. Saya justru menaruh simpati pada amatannya. Di mana hal tersebut justru membuat dangdut berkembang dengan was-was dan awas.
Namun, dangdut kini tak sama dengan yang 10 tahun silam. Dan, memang Rhoma Irama pula yang mengangkatnya, membenahinya, dan menyempurnakannya. Dan menurut pengamatan saya, pembenahan itu sedikit banyak, ada sangkut pautnya dengan makian Benny Soebardja itu (Sylado, 1984, p. 3). [4]
Bahkan Remy turut mengakui perubahan pada kualitas dangdut sejak kemunculan terma dangdut sebagai ejekan di majalah yang ia naungi. Remy secara terang-terangan menuliskan,
Namun, dangdut kini tak sama dengan yang 10 tahun silam. Dan, memang Rhoma Irama pula yang mengangkatnya, membenahinya, dan menyempurnakannya. Dan menurut pengamatan saya, pembenahan itu sedikit banyak, ada sangkut pautnya dengan makian Benny Soebardja itu (Sylado, 1984, p. 3). [4]
Sebagai peneliti dangdut, tentu sanjungan Remy ini sungguh membahagiakan untuk saya. Pun tak sering Remy memuji musik yang sudah ia lucuti sebelumnya. Hal ini mengejawantahkan bagaimana Remy menyimak kembali dangdut di era tahun 1980-an. Secara jelas, Remy juga memberikan perhatian lebih pada Rhoma Irama yang sudah “mengangkatnya, membenahinya, dan menyempurnakannya [Dangdut]” dari ‘kubangan’ cercaan.[5]
Jika merujuk tahun 1984 di mana Remy memberikan pujian tersebut, Rhoma Irama memang sudah berbuat banyak untuk dangdut. 13 album bersama Soneta Group, 16 soundtrack film, tiga album solo, dan masih banyak proyek musik lainnya, membuat Remy akhirnya berpikir ulang atas apa perkataan atau wacana yang ia giring selama ini. Dari lagu-lagunya pun, Rhoma memang berkembang pesat dalam wacana lagu yang dibawakan, hanya dari sekadar cinta hingga persoalan moral hingga bangsa. Atas apa yang telah dicapai Rhoma, Remy telah mengakuinya dengan menuliskan,
Jika merujuk tahun 1984 di mana Remy memberikan pujian tersebut, Rhoma Irama memang sudah berbuat banyak untuk dangdut. 13 album bersama Soneta Group, 16 soundtrack film, tiga album solo, dan masih banyak proyek musik lainnya, membuat Remy akhirnya berpikir ulang atas apa perkataan atau wacana yang ia giring selama ini
Apa yang dilakukan Rhoma Irama adalah tonggak musik populer Indonesia abad depan. Musiknya telah mencapai tingkat mutu yang memuaskan, baik estetis maupun etis (Sylado, 1984, p. 3).[6]
Agaknya perdebatan telah usai setelahnya. Misi William tuntas, asumsi Remy telah berubah, dangdut dapat tidur dengan pulas. Walaupun, jika Remy menilik musik dangdut hari ini, mungkin asumsinya akan kembali berubah. Dapat saya bayangkan apa yang akan ia tuturkan.
Pun dari tulisan ini, saya tidak sedang menatap akan bagaimana asumsi Remy yang berubah-ubah, melainkan sikap kedewasaan dan ksatria Remy terhadap musik yang ia telisik sebelumnya. Berubahnya asumsi Remy dari adu pendapat dengan William membuktikan jika pendapat bisa terus berganti sejalan dengan faktor estetis dan etis pada konteks ruang serta waktu yang jelas. Dari sudut pandangnya, menurut hemat saya, Remy justru menjadi salah satu orang yang membuat dangdut dan Rhoma Irama mencapai titiknya kini. Ia menjadikan dangdut terus bertumbuh kembang, bak dalam lagunya yang bertajuk “Evolusi”, //rumusnya siapa kuat dia hidup//. Dan saya pikir Dangdut telah lolos melaluinya. Atas dasar itu, terima kasih Remy, karenamu Dangdut tahan banting.
Soal Kajian Musik Kita
Tak hanya untuk aktivitas dangdut, pentingnya adu pendapat antara William dan Remy, saya pikir juga penting untuk kajian musik dangdut dan juga kajian musik Indonesia. Remy memang sempat mengungkapkan jika “Dan barangkali ini celakanya: pop sudah diterima sebagai suatu aib. Orang tak suka lama-lama menyiapkan hati pada diskusi pop, lantaran khawatir kehilangan penghargaan umum terhadap kesungguhannya berpikir” (1977, p. 23). Namun hal ini tentu bertolok dari konstelasi kajian musik yang memang tak menaruh perhatian pada jenis musik tersebut. Dari sini jugalah William tergelitik untuk menuliskan esai pendeknya di Tempo, “Mengapa Dangdut Rhoma jadi Penting” (1984, p.79). Wiliam juga mengartikulasikan balada pengkaji Indonesia yang tidak menaruh perhatian serius dalam mengkaji budaya populer, salah satunya Rhoma Irama. Bagi William, Indonesia punya persoalan mendasar soal itu.
Kecemasan William memang tidak dapat disanggah. Bahkan kajian musik Indonesia hingga tahun 1990-an memang belum melihat dangdut sebagai kajian yang perlu diselisik secara serius. Pendidikan tinggi Indonesia memang lebih berfokus pada musik yang [dianggap] pure, adiluhung, dan sarat dengan tradisi. Pun saya menelusuri perpustakaan digital kampus, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Sebelas Maret yang menghasilkan karya ilmiah, baik skripsi, tesis, ataupun disertasi. Dari penelusuran tersebut, penelitian mengenai dangdut baru ditemukan pada tahun 1999 di Prodi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada yang ditulis oleh Sumiyoto dengan tajuk “Gendhing Dangdut Pembentuk dan Pengaruhnya terhadap kehidupan Karawitan Jawa di Sragen”. Tulisan ilmiah lainnya baru mulai dikerjakan di tahun 2000an.
Antropolog seni, G.R. Lono Lastoro Simatupang saja harus pergi dan menempuh studi di Monash University, Clayton, Victoria, Australia untuk dapat mengkaji dangdut dengan serius. Hal itu ia lakukan bukan di tahun 1980-an, pasca William mengkritik kajian musik Indonesia, melainkan di pertengahan tahun 1990-an. Tesisnya terbit tahun 1996 dengan tajuk The Development of Dangdut and Its Meanings: A Study of Popular Music in Indonesia. Ia sempat kesulitan mencari sumber data dari tulisan ilmiah ketika itu di Indonesia, tetapi ia turut menjelaskan jika tulisan dangdut banyak diproduksi di majalah dan tabloid. Dua produksi itu dapat menjadi data sekunder, tetapi jika diperuntukkan sebagai analisis, maka tunggu dulu. Singkat kata, iklim pengkajian musik di Indonesia memang punya soal mengenai dangdut dan musik populer yang menjadi objek material penelitian.
Alhasil tulisan William menjadi penting untuk mengutarakan posisi dangdut dan musik populer yang perlu ditilik lebih lanjut. Alih-alih berdiri sendiri, jawaban Remy di kolom kontak pembaca justru menjadi energi positif. Ia menerangkan jika,
Pandangan saya tentang dangdut, terutama atas musik Rhoma Irama, cukup jelas dalam pengantar Pensi 83. Dangdut memang musik hiburan. Tapi ia harus dikaji serius. Apa yang dilakukan Rhoma Irama adalah tonggak musik populer Indonesia abad depan. Musiknya telah mencapai tingkat mutu yang memuaskan, baik estetis maupun etis. Dengannya, Rhoma adalah mahasarjana. Saya dapat menikmati musiknya di antara Penderecki dan Zappa, Xenakis dan King Curtis, Stravinsky dan Phil Collins, Albeniz dan Ritchie Blackmore (Sylado, 1984, p. 3).[7]
Remy dengan tegas mengungkapkan jika dangdut harus dikaji secara serius baik dari kualitas estetis maupun etis. Hal ini telah mengamini jika konstelasi kajian musik pop Indonesia tidak menaruh perhatian pada dangdut sebelumnya. Dan ucapan Remy yang lazim menjadi oposisi, ikut mendorong musik dangdut untuk diafirmasi setiap pihak untuk diperhatikan secara lebih. Tentu pernyataannya di tahun 1984 tidak mengubah langsung arah kajian musik kita, tetapi pernyataan Remy mengejawantahkan lubang besar kajian musik yang memang perlu kita tambal dan perbaiki dari waktu ke waktu.
Bagi saya, sebagai founder www.dangdutstudies.com, perdebatan ini telah menjadi kurikulum kami dalam membentuk kajian musik dangdut. Dan saya pikir pikiran Remy tentang musik—baik pikiran ataupun bantahan—di pelbagai medium harus menjadi bagian vital penyusunan kurikulum dari rencana besar pengkajian musik populer Indonesia. Sepeninggal Remy, sudah sepantasnya kita mewarisi dan mengobarkan api kajian musik populer Indonesia. Tak mudah, tapi patut dicoba. Tak perlu sendirian, karena kita bersama. []
Penghargaan
Terima kasih kepada Mas Kabut dari Surakarta yang sudah membagi arsipnya kepada saya, terkhusus kolom surat pembaca dari Remy Sylado pada Tempo 4 Agustus 1984.
Referensi
Frederick, William H. (1982). Rhoma Irama and the Dangdut Style: Aspects of Contemporary Indonesian Popular Culture. Indonesia 34, 103-130.
Frederick, William H. (1984). Mengapa Dangdut Rhoma jadi Penting. Tempo, 18 (30 Juni 1984), 79.
Sylado, Remy. (1977). Musik Pop Indonesia: Satu Kebebalan Sang Mengapa. Prisma, 6, 6 (June 1977), 23-31.
Sylado, Remy. (1980). Musik Pop Makin Ndeso. Dialog, 33 (4-17 February 1980).
Sylado, Remy. 1984. Rhoma Irama: Pengamatan Remy Sylado. Tempo, 22 (4 Agustus 1984), 3.
[1] Afiliasi William H. Frederick mengacu pada tulisannya di Majalah Tempo 30 Juni 1984. Dari penelusuran kini, jabatan terakhir sebelum William pensiun adalah Profesor di bidang Sejarah di Universitas Ohio, USA.
[2] Cetak tebal dari penulis.
[3] Cetak tebal dari penulis.
[4] Cetak tebal dari penulis.
[5] Tipikal logika purist yang menempatkan adanya hal buruk, dan hal buruk tersebut harus diubah agar hidup dapat beroperasi kembali dengan sebagaimana mestinya.
[6] Cetak tebal dari penulis.
[7] Cetak tebal dari penulis.
Eksplor konten lain Pophariini
Lirik Sambutlah The Jeblogs sebagai Anthem Anak Muda
Di artikel lirik kali ini Pophariini memilih lagu “Sambutlah” dari The Jeblogs untuk mengetahui bagaimana barisan kata-katanya bisa tercipta menjadi lirik yang kuat dan dinyanyikan dengan penuh penghayatan dalam setiap aksi mereka di panggung. …
WYAT, The Skit, Teori, dan Barmy Blokes Turut Menyukseskan Latihan Pestapora Solo
Setelah rangkaian workshop dan talkshow berlangsung tanggal 12-14 Juni 2025, Latihan Pestapora Solo persembahan Boss Creator akhirnya terlaksana hari Minggu, 15 Juni 2025 di Pamedan Mangkunegaran. Latihan Pestapora Solo kali ini berhasil mengumpulkan sekitar …