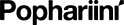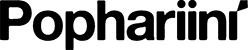Hati dan Emosi: 20 Tahun Album Debut The Brandals

Lagu pembuka yang dahsyat seringkali telah memenangkan setengah perjalanan sebuah album. Dua puluh tahun lalu, rilis Desember 2003, The Brandals meletakkan “Marching Menuju Maut” di urutan pertama debut albumnya.
Dari intro pukulan gitar dua chord yang renyah di senar-senar bawah, datang drum berderu primitif, lalu power chord dari gitar kedua menghajar bagai Pete Townshend membaling-balingkan tangannya di atas kriwil kabel hitam. Kemudian gitar pertama tadi mulai memainkan melodi pendek yang lekas diingat, ditebalkan gitar kedua dan cymbals yang jadi titik-titik hujam, hingga muncul vokal gusar-kasar-mentah bersama lirik yang sangat gerah.
Jejakkan kaki di tanah / Berbaris ke satu arah / Menuju dataran merah / Basah merah bersimbah darah // Pantang mundur, maju terus / Makin ke depan semakin seru / Siapkan nyali di hati / Api berkobar tak pernah mati
“Marching Menuju Maut” bergerak untuk semakin meledak-ledak, Menemani vokalis Eka Annash meneriakkan “menuju datangnya ajal” dengan ujung yang pecah, pemain bas Doddy Widyono telah memerosotkan jarinya untuk jerit bulat lebih tinggi, sebagai selamat datang pada interlude gitar sonik belantah.
Lagu pembuka yang dahsyat seringkali telah memenangkan setengah perjalanan sebuah album. Dua puluh tahun lalu, rilis Desember 2003, The Brandals meletakkan “Marching Menuju Maut” di urutan pertama debut albumnya
Seingat gitaris Bayu Indrasoewaeman, awal lagu “Marching Menuju Maut” tercipta saat jamming di Bogor, di hari belum ada The Brandals. Bayu, gitaris Tony Dwi Setiaji, pemain drum Rully Annash, Doddy, bersama vokalis Edo Wallad pada awalnya membentuk band bernama The Dictator, kemudian berganti menjadi The Motives.
“Gue iseng bikin chord intro, terus Rully masuk isi drum, habis itu yang lain ngikut. Seperti biasa, Tony yang bikin reff-nya,” kenang Bayu tentang “Marching Menuju Maut”.
Ketika Edo digantikan Eka, The Motives berubah nama menjadi The Brandals, Eka menggarap lirik hingga menggenapkan lagu itu, terinspirasi dari beberapa film perang produksi Hollywood yang muncul di akhir 1990an seperti Saving Private Ryan, The Thin Red Line, Three Kings, juga geger insiden 9/11 dan Bom Bali.
“Kayaknya di era itu kita ikut terperangkap phobia global tentang terorisme yang sialnya terkonotasi dengan Islam. Jadi, kita sebagai negara muslim terbesar di dunia kena getahnya. Liriknya mengadaptasi kondisi masyarakat Indonesia yang masih jadi korban. Walaupun pemerintahan berganti dari era Orde Baru beralih ke pasca reformasi dengan kulit luar berbeda, tapi masih dijalankan lewat tangan opresi yang sama. Suatu saat kekuatan rakyat akan menggulingkan rezim tirani yang berkuasa untuk kedua kalinya. Dan gue ngebayangin lagu ini bakalan jadi soundtrack-nya. Begitu kira-kira,” jelas Eka akan buah penanya.
Saya pertama kali menonton The Brandals pada 15 Februari 2003 di BB’s Café yang menjadi “rumah” bagi kemunculan band-band independen Jakarta gelombang baru saat itu. Nama acara malam itu adalah “Kita” dengan empat identitas tertera— Batman, Culap, David, Nestee— yang siap memutar musik-musik kegemaran kita. Lalu ada juga DJ Keke, dan tiga band penampil: Seringai, The Upstairs, The Brandals.
“Awal 2000 kita lagi sering puter VCD film Indonesia 1970an di mana personifikasi karakter anak cowok digambarkan liar, selalu bersama kelompok gang, naik motor trail, dan pemberontak. Berandalan banget. Akhirnya kita pilih nama The Brandals,” jelas Eka Annash.
The Brandals main pertama. Saya lihat wajah-wajah tak asing di panggung. Eka Annash sebelumnya telah diketahui sebagai vokalis Waiting Room, band yang awalnya dikenal di scene sebagai “spesialis bawain Fugazi”, kemudian pada 1997 berhasil merilis album yang banyak terpengaruh oleh ska-punk dengan single populernya, “Ruang Tunggu”.
Tony dan Doddy, duo teman sejak kecil itu, saya terakhir bertemu mereka ketika kasak-kusuk bikin band bernama Anti-climax Neon Light, sempat pula bermain di “acara indie” yang pada awal 2000an telah berpindah tempat, dari era rutin Poster Café yang dilanjuti M-Club pada 1990an, menjadi antara lain Iguana dan Nirvana Café.
Anti-climax Neon Light seperti ingin menjadi jelmaaan electronic-indie rock-goth dalam percobaan oplosannya. Berhubung Tony merasa “masih agak bingung mau ke arah mana” dengan band itu, “karena terlalu banyak instrumen yang nggak umum, mau pakai Groovebox-lah”, maka Tonny pun ingin membentuk kelompok musik baru yang dalam istilahnya, “Band yang lebih santai materi instrumennya.”
Maka terkumpul Tony, Edo, Bayu, dan Rully. Seingat Bayu, di masa awal itu, formasi mereka masih berempat di mana Bayu menjadi pemain bas, lalu kemudian Doddy bergabung. Bayu pindah alat jadi bermain gitar.
Saat SMA, sekitar 1993, Bayu dan Rully sempat tergabung dalam sebuah band bernama The Peniti yang antara lain membawakan lagu-lagu dari The Exploited dan Sex Pistols. Saat demam Britpop pada pertengahan hingga akhir 1990an, Rully, Bayu, dan Edo tergabung dalam Brownsugar yang antara lain membawakan lagu-lagu Oasis dan Menswear. Sekitar pada masa itu pula Tony dan Doddy tergabung dalam band Underwear yang memainkan Inspiraal Carpets dan Pulp.
Sebelum Underwear, Tony tergabung dalam band Den Aidit yang membawakan Sex Pistols dan Rancid.
Di masa awal formasi Tony, Bayu, Rully, Doddy, dan Edo, mereka memainkan nomor-nomor Britpop untuk mula berlatih.
“Terus, gue lagi doyan-doyannya the Velvet Underground dan the Clash. Nah, Bayu menyambut, suka yang sama. Dari situ, mulai bikin lagu. Nggak lama, Rully dengerin the Strokes dari Eka waktu Eka balik dari Australia. Sesuatu yang baru buat kita semua. Makin PD kita bikin lagu-lagu garage-punk, dan akhirnya merekam dua lagu awal, plus ganti nama dari the Dictator jadi the Motives,” kenang Tony.
Setelah Eka menggantikan Edo, nama band diubah menjadi The Brandals.
“Ingin punya nama band berbahasa Indonesia tapi bisa dilafalkan dalam bahasa Inggris juga. Awal 2000, rumah gue jadi base camp anak-anak dan kita lagi sering puter VCD film Indonesia 1970an di mana personifikasi karakter anak cowok (via aktor Roy Marten, Robby Sugara, Barry Prima) digambarkan liar, selalu bersama kelompok gang, naik motor trail, dan pemberontak. Berandalan banget. Akhirnya kita pilih nama The Brandals dengan menghilangkan ‘E’ supaya lebih lugas dan bisa dilafalkan dalam bahasa Inggris,” jelas Eka.
Rully dan Bayu kemudian membuat logotype dengan font Lambretta yang diimbuhi efek wave dari Photoshop.
Malam di BB’s 15 Februari 2003 itu adalah pertunjukan kedua bagi The Brandals, setelah sebelumnya mereka bermain di acara “Bakar-bakaran” IKJ. Penonton belum tahu persis apa yang akan segera disuguhkan. Lagu pertama yang dibawakan The Brandals? Langsung meledak-ledak. Kami kemudian tahu bahwa itu adalah “Marching Menuju Maut”.
Album debut The Brandals dapat dikatakan berwarna sangat utuh. Kental. Gelap-pekat. Mentah, gusar, tapi juga puitis seperti potret akan blangsaknya Jakarta dan dunia yang ditelan anak muda di usia awal pekerja memasuki tahun 2000.
Para penonton, yang jumlahnya masih belum seberapa, segera mendeteksi bahwa band ini berbahaya! Bahkan setelah 20 tahun, mungkin sampai masa depan nanti, “Marching Menuju Maut” masih sering jadi pembuka panggung The Brandals dengan efek dobrak teruji.
Malam itu pula pertama kali saya menonton Seringai. Tak lama setelah membubarkan Puppen, vokalis Arian 13 berkongsi untuk membuat band baru bersama Ricky (dikenal sebelumnya gitaris alternative rock, Chapter 69, lalu bersama band hardcore, Stepforward). Seperti meleburkan Bandung-Jakarta, Arian mengajak Khemod di posisi drum, sementara Ricky mengajak Toan pada bas, dari unit black metal, Finsternis.
Lagi-lagi wajah-wajah familier dalam wujud band baru. Sementara The Upstairs, sampai sekarang dikenal dengan ujung tombak duo Jimi-Andre “Kubil”. Nama pertama di tahun 1990an adalah pemain drum, Be Quiet, nama kedua sempat menjadi gitaris, Frontside. Mereka dahulu memainkan hardcore.
Inilah gempuran mutakhir pada scene independen Jakarta. The Brandals lahir tepat di pusarannya.
Saya bertanya ke Eka, “Buat lo, apa bedanya era album pertama Waiting Room dengan era album pertama The Brandals?”
Eka mengetik panjang di WA,” Jelas signifikan bedanya. Era album pertama Waiting Room (1997) masih terbilang amatir dan primitif. Baik dari faktor produksi rekaman, distribusi, promosi dan jaringan panggung/tur. Belum ada pakem struktur yang kita ikuti, semuanya dilakukan mandiri degan segala hambatan dan kegagalannya. Tapi dari situ justru banyak pengalaman dan ilmunya. Pengalaman dan ilmu tadi gue terapkan waktu memulai kembali dengan The Brandals.”
Eka menambahkan, “Sebenernya rentang 1997 sampai era The Brandals mulai (2001-2002), belum begitu mencolok perbedaannya. Band independen masih berkutat dan bergulat di kubangan yang sama. Tapi sudah ada jaringan antar komunitas dan kolektif antar kota yang terjalin (setidaknya di Pulau Jawa) karena bantuan internet. Lalu media mainstream lebih membuka pintunya, memberi ruang buat band-band indie kecil seperti The Brandals untuk diliput. Studio musik rekaman pun banyak bermunculan untuk diakses membuat materi yang lebih proper dengan harga yang jauh lebih terjangkau.”
“Pergeseran lansekap preferensi pendengar musik juga jadi katalis penentu. Di dekade sebelumnya band dan musik UK/US masih jadi parameter bahkan diduplikat dengan akurat. Di awal 2000an mulai muncul kesadaran untuk tampil dengan materi kreasi sendiri dan menyanyikan lirik Indonesia bertema lebih relevan dengan nilai lokal. Trend ini menjadikan awal 2000an sebagai titik tonggak kedua renaissance perombakan drastis industri musik Indonesia menjadi lebih dinamis, orisinil, dan independen,” pungkasnya.
Bila “Marching Menuju Maut” jadi pembuka yang panas, maka lagu urutan kedua di debut album, “Lingkar Labirin” adalah yang membawa nama The Brandals untuk semakin lebar dikenal dengan video musiknya yang berotasi tinggi. Bersama video musik “Lingkar Labirin”, The Brandals bahkan dijadikan artist of the month oleh MTV.
Video musik “Lingkar Labirin” digarap oleh The Jadugar yang berisi duo seniman Anggun Priambodo dan Henry Foundation, alias Batman.
“Kayaknya gue yang kesengsem awalnya,” jawab Anggun mengingat bagaimana The Jadugar menggarap The Brandals. “Kita yang pingin, tapi mereka juga sudah tipis-tipis ngicer juga,” tambahnya.
Sebelumnya, The Brandals sudah membuat video musik untuk lagu “100 km/jam” bersama sutradara Platon, di mana Anggun menjadi salah satu crew dalam produksinya.
“Itu pas setahun The Jadugar resmi aktif jadi video music maker, jadilah gayung bersambut dari dua belah pihak,” tambah Anggun. The Brandals memilih “Lingkar Labirin” untuk dibuat video musiknya.
Anggun datang dengan ide stop motion karya dari kertas kosong sampai penuh, terinspirasi dari melihat sebuah foto di sampul buku.
“Bersamaan dengan itu, karena kita anak seni rupa, pingin kasih lihat gimana sih proses karya dari A-Z,” tambah Anggun.
“Stop motion sedang menjadi sesuatu yang menarik saat itu karena ‘raw’, pas dengan beat lagu mereka, ketukan mereka. Gue dan Batman juga memang suka gambar-gambar, pas lah, ” jelas Anggun lagi.
Mereka pun mengadakan sesi pemotretan di rumah Bayu. The Brandals diminta berpakaian seperti layaknya fashion mereka di atas panggung. Foto-foto itu difotokopi perbesar sampai ukuran A1.
“Pecah-pecah, sengaja. Semakin raw, semakin asik,” kata Anggun.
Teman-teman The Jadugar dari ruangrupa turut membantu men-cutter dan menggunting. Kertas-kertas berukuran A1, A2, A3 digarap.
“Yang paling detail kerjanya adalah Oomleo,” ingat Anggun.
Syuting berlangsung dua hari di halaman belakang Galeri Air, Menteng, Jakarta. The Jadugar bekerja leluasa karena saat itu teman-teman mereka, Tandun dan Adi “Cumi” memiliki sudio grafis dan indekos di sana.
“Yang paling nempel banget dari membuat video musik ‘Lingkar Labirin’ adalah kita pertama kali menggunakan kamera digital. Pada saat itu benar-benar sesuatu yang baru. Anggun baru beli kamera poket Canon Ixus,” kenang Henry Foundation.
“Kalau dipikir-pikir sekarang, kamera itu jeprut banget, cuma berapa mega-pixel. Tapi karena saat itu sesuatu yang baru, jadi kayak semacam ‘culture shock’ gitu. Sebelumnya kita terbiasa pakai kamera analog yang cuma 32 frame, terus tiba-tiba ada kamera digital yang lo bisa motret ‘seenak jidat’, dan ada preview-nya. Kita excited banget mendapatkan teknologi itu. Makanya konsep stop motion di ‘Lingkar Labirin’ juga salah satunya muncul karena kita baru punya kamera digital. Kita bisa bikin still photo bebas, ratusan frame, kalau salah bisa di-delete, bisa diulang.” tambah Henry.
Hasilnya, sampai sekarang, selain lagunya yang telah menjadi legendaris, “Lingkar Labirin” juga kerap “menempel” dengan video musiknya yang tak kalah klasik. Pada video musik ini pula, salah satunya dengan citraan teks “crot-crot-crot”, identitas sound gitar debut album The Brandals yang mentah semakin tampil terasa.
“ Gue di The Brandals banyak belajar teknik lead, chord gitar, sound. Rekaman sambil belajar. Gue dapat masukan banyak dari operator Doors Studio, Mas Yuli, yang sekarang jadi sound engineer-nya d’Masiv,” ingat Bayu.
Bayu mengaku sebenarnya saat awal itu dia hanya bisa bermain bas dan gitar ritem, cuma karena tidak ada yang bisa main lead guitar di band, ia jadi belajar memainkan solo.
“Gue dengerin Hendrix, walaupun gak ada yang nyampe ilmunya hahaha…” kata Bayu.
“Kalau sound, sih, keluar gitu aja, karena waktu itu belum punya pedal board, jadi cuma mengandalkan distorsi dari ampli, paling sama pedal booster buat nge-lead, itu juga dipinjemin sama Juan (gitaris Waiting Room). Intinya masih minim alat. Makanya kalau manggung gue selalu minta ampli Marshall JCM 900. Praktis, knobnya gak banyak, sound-nya dapat yang gue mau,” kata Bayu lagi.
Pada urutan ketiga di debut album The Brandals, kita bertemu dengan “100 km/jam” yang lugas dan seruntulan. Seperti halnya “Marching Menuju Maut”, lagu ini juga mulai diciptakan sejak era The Motives.
“Gue bikin chord gitar sama patern bas-nya, Tony nyumbang bridge. Sebenernya di kepala gue, musiknya kaya Black Sabbath, tapi karena Rully cara mainnya lain, jadinya malah lebih seru,” kenang Bayu akan lagu yang malah jadi ngebut itu.
Dari pertama mendengar “100 km/jam” di panggung sampai di kaset debut, saya selalu menoleh saat bas Doddy menyelonong simple-mengena.
Sementara di lagu keempat, “Hati Emosi”, musik dan dunia seperti bergoyang bersama endapan resah. Energi romantik khas The Brandals yang sesekali dimunculkan— bila datang, sukses mencuri perhatian. Untaian ”dari mata turun ke hati, dari hati tak mau pergi” laksana jilid pertama dari bait pembuka “berkali-kali kau buat tidurku tak nyenyak” pada “24:00 Lewat (Lagu Luna)” di soundtrack film Lovely Luna (2004) dalam album Audio Imperialist (2005).
Keseluruhan debut album The Brandals dapat dikatakan berwarna sangat utuh. Kental. Gelap-pekat. Mentah, gusar, tapi juga puitis. Album debut The Brandals seperti potret akan belangsaknya Jakarta dan dunia yang ditelan anak muda di usia awal pekerja memasuki tahun 2000, yang tumbuh liar bersama musik, film, buku, dan nongkrong.
Lagu “Stagnansi vs Reformis” hadir bagaikan potongan hidup itu sendiri.
Terbangun lagi matahari sudah tinggi / Tak ada rencana untuk hari ini / Percuma mandi harapan sudah mati / Terduduk lagi pandangi awan tinggi / Ke mana kaki kulangkahkan? / Jauhi terik mentari
Ke mana kaki kulangkahkan? / Bisingnya deru sang waktu / Ke mana kaki kulangkahkan? / Sangitnya bau badanku // Ke mana kaki kulangkahkan? / Nikotin ke paru-paru
Secangkir kopi tanpa gula gelap pekat / Ayo lari cepat, seminggu terus terlambat / Masuk kantor, siap jadi penjilat / Ulangi lagi sampai hati ini berkarat
Kemana kaki kulangkahkan? / Menunggu datang jam lima // Ke mana kaki kulangkahkan? / Berdesakkan tukar keringat // Ke mana kaki kulangkahkan? / Hari ini seperti kemarin // Ke mana kaki kulangkahkan? / Lupa makan jadi masuk angin
Eka mengingat momentum tumbuhnya ide lirik lagu ini, “Lagi di Metro Mini S602, berangkat kerja, desak-desakan.”
Dalam album debut The Brandals, Eka mengaku bahwa itu adalah “Episode pertama menulis semi-autobiografi, artikulasinya dipikirkan sekali.”
Ia mendapat pengaruh dari Iwan Fals dan Slank. ”Nggak mungkin lirik seperti ini dikarang-karang,” katanya.
Bila kita membaca seluruh lirik di album ini, banyak kita menemukan persinggungan akan hari-hari saat itu dalam hidup penulisnya. Gusarnya. Kelamnya. Liar impiannya.
Metro Mini juga yang mengantarkan Eka dalam menulis lirik lagu “Anjing Urban (Sang Korban II)”. Saat menunggu alat transportasi itu, Eka melihat seorang copet digebukin di lapangan bola Kampung Melayu, Jakarta. Eka kerap membeli kaset bekas di sana.
“Pas digebukin, kedengeran dia ngomong ’Ampun, Bang’ dengan logat Batak,” ujar Eka. Dari situ ia mendapat gambaran bahwa ‘tokoh copet’ itu seorang rantau. Jakarta keras sampai menampolya.
Dua puluh tahun lalu album The Brandals diluncurkan. Dari kredibilitas panggung ke panggung sampai akhirnya kemudian album penuh beredar, dengan artistiknya yang memikat anak muda, maka dinamit itu tak terelakkan. The Brandals menjadi fenomena.
Sementara lagu “Mutasi Urban (Sang Korban I)”, dalam ingatan Bayu, adalah lagu yang pertama kali tercipta. Digarap bersama masih saat era The Motives dengan judul awal “Sang Bintang”, Eka kemudian memberikan lirik baru sekaligus mengganti judulnya.
Semenjak kalimat pertama, tergambar sudah porak-poranda…
Bising terdengar bunyi sirine terus meraung-raung / Debu jalanan tebal bergulung-gulung / Sesak napasku diracun toksik kota / Mata merah, berkali-kali buang ludah
Sampai lirik menghujamnya: “Tiap hari cari BD, yang ketemu OD’, lagu ditutup dengan empat baris kelam…
Akulah sang korban / Korban hancur jaman / Penuhi otakku / TV, pornografi, amphetamine selalu
The Brandals merekam debut albumnya di Doors, studio milik Giox, pemain perkusi Waiting Room era album Propaganda, yang kemudian menjadi pemain bas Superglad.
Bayu mengingat jumlah hari merampungkan rekaman debut album The Brandals yang kerap berjeda, bila ditotalkan, kurang lebih sekitar dua pekan.
“Rekamannya nyicil. Ada duit, baru rekaman,” terang Bayu. “Pokoknya pas-pasan banget. Kadang sehari bisa tiga lagu dijadiin.”
Pernah para personil The Brandals ikut tampil dalam video musik Project Pop, “Dangdut is the Music of My Country” untuk mendapat honor.
“Habis dapat uang, lusanya rekaman,” Bayu mengingat.
“Kalau gak salah, lagu terakhir yang direkam adalah ‘Vague and Hollow’,” Tony bercerita.
“Lagu ini kebetulan gue yang nemuin ide awal, di rumah Bayu. Kalau gak salah, pakai gitar akustik, tiba-tiba nemu nada ok, nih, menurut gue hahaha, Habis itu bareng Bayu nuntasin sampe jadi satu lagu. Gue inget bagian blues-nya yang di-ending itu idenya Bayu,” tambah Tony.
Bahkan diletakkan hampir penghujung sisi B kaset, disimak hari ini pun, “Vague and Hollow” masih memancarkan kembang rock. Rully mengahajar drum ditemani tamborin itu sedap sekali. Dan bagian blues di belakang, oh, siapa peduli berapa bar solo gitar berlangsung; bagai sudah basah keringat badan terbuai.
The Brandals membungkus album ini dengan foto sampul yang dijepret Eka. Sekitar awal 2003 ia baru bekerja di daerah Mampang Raya. Ide berawal lagi-lagi dari atas Metromini, yang kerap ditumpanginya untuk bolak-balik kantor.
“Sebelum lewat stasiun kereta Manggarai, di sepanjang jalan banyak tukang loak dan barang bekas yang majang dagangannya di trotoar. Ditumpuk-tumpuk jadi kayak karya instalasi. Selalu menarik perhatian gue setiap kali lewat. Akhirnya suatu hari gue memutuskan bawa kamera, turun sebentar di spot itu, dan foto-foto. Nggak ada maksud apa-apa, cuma untuk didokumentasikan aja,” kisah Eka.
Ketika hendak rilis album di akhir tahun, Eka teringat akan foto itu, maka di-crop untuk cover depan dan belakang.
“Pakai base warna cokelat muda dan font type warna kuning supaya ada karakter vintage,” jelas Eka.
Eka menguliti sampul itu, “Pemilihan image tumpukan barang bekas pas banget menurut gue sebagai cover. Simbolisasi The Brandals sebagai figur anak muda Jakarta saat itu yang lagi haus informasi dan referensi (sub) kultur. Mengimpor dan mengadaptasi dari berbagai sumber, lalu ditabrakin dengan aspek dan nilai ke-Indonesia-an kita. Jadi mutasi objek yang unik, aneh, dan keren, tapi liar dengan unsur jalanannya.”
Debut album The Brandals dirilis oleh Sirkus Rekord. Indie label itu didirikan band rap-rock Kripikpeudeus (KP) pada akhir 2000. Awalnya, agar KP punya bendera sendiri untuk merilis album perdananya. Nama Sirkus terinspirasi dari grup rap Insane Clown Posse/ICP yang konsepnya a la sirkus; ICP berciri dandan badut.
Vokalis KP, Fandy mengenang, “Waktu itu kita ngegarap kompilasi Desain Trisakti, Indiesain, di tahun 1999. Kebetulan gue dan Andy LMT (gitaris/founder KP) meng-handle teknisnya. Dari studio sampai cetak dan penggandaan kaset. Gak lama kemudian KP rekaman dan decide untuk ngasih nama Sirkus Rekord. Mimpinya kita pengen rilis berbagai genre/rumah bagi mereka yang ingin berkarya tapi belum punya label.”
Sepulang studi dari Australia, Eka sempat membuat fanzine bernama Cosmic.
“Eka mewawancarai KP, waktu itu sebelum bikin The Brandals,” ingat rapper KP, David akan awal persinggungan temu Sirkus Rekord dengan The Brandals.
Sementara Fandy malah telah mengenal Eka sejak di bangku SD, berlanjut masa SMP.
“Waktu dia dengar KP rilis secara mandiri dan bisa diterima di radio, majalah, serta bisa masuk MTV, Eka pun menyampaikan niatnya untuk kerjasama The Brandals dengan Sirkus Rekord. Walaupun kita sudah memberi informasi vendor produksi hingga distribusi, tapi Eka tetap merasa kita bisa lakukan bareng,” jelas Fandy.
Selain Kripikpeudeus dan The Brandals, Sirkus Rekord juga merilis album-album dari Ape on the roof, Pop Minor, The Upstairs, hingga Alithia dari Jerman. Saat ini Sirkus Rekord dijalankan oleh Tori Sudarsono, merilis single dari di antaranya Damon Koeswoyo, Pureseven, Kxngscap, dan Happiest Lokal.
Dua puluh tahun lalu album The Brandals diluncurkan. Dari kredibilitas panggung ke panggung sampai akhirnya kemudian album penuh beredar, dengan artistiknya yang memikat anak muda, maka dinamit itu tak terelakkan. The Brandals menjadi fenomena.
Hari ini, hanya Eka personil tersisa dari rekaman debut album, yang masih aktif bermusik bersama The Brandals. Bagi mereka yang dekat dengan segenap lini awak The Brandals, dari cikal bakal awal sampai siapa saja yang berjalan bersama band itu hingga sekarang, The Brandals melebihi energi musik, tapi pertemanan.
Kepada Rully Annash yang lebih dahulu mendahului kita, doa terbaik senantiasa untukmu, kawan.
Eksplor konten lain Pophariini
Say:Kou Lepas Single K.a.R.M.A yang Terinspirasi dari Momen Mumet
Unit alternative rock asal Tangerang, Say:Kou merilis single terbaru “K.a.R.M.A” tanggal 13 Juni lalu. Single ini menjadi medium para personel Say:Kou untuk melepas keluh kesah hidup yang menumpuk. Say:Kou digawangi oleh Fauzy …
TWCLWS Rayakan Kebebasan Diri Lewat Single Terbaru Yeaiy!
Solois asal Jakarta Pusat, Riant dengan nama panggung TWCLWS resmi melepas single terbaru berjudul “Yeaiy!” hari Jumat (04/07). Single ini menjadi cara Riant untuk merayakan kemerdekaan diri sendiri sekaligus merangkul siapa pun yang punya …