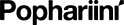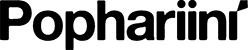Ketika Kritik Musik Merambah Media Sosial

“kritak-kritik musik, kritak-kritik musik,” “fafifu wasweswos,” “band ini jelek.” Ketiga kalimat tersebut belakangan kerap riuh dibicarakan di media sosial, terutama Twitter, media sosial yang kini dimiliki sang megalomaniac Elon Musk.
Yang pertama mengacu pada—barangkali—kejenuhan para warganet karena pembahasan mengenai kritik musik itu sudah berbusa-busa kerap kali dibicarakan di ranah media sosial.
Yang kedua mengacu kepada bagaimana ketika seorang kritikus musik dituding sedang melakoni onani pengetahuan dengan menulis tulisan kritik musik yang banyak menyelipkan teori-teori atau ulasan yang komprehensif (yang sayangnya kerap dipahami sebagai tulisan yang berat).
Sementara yang ketiga mengacu pada bagaimana sekarang banyak orang berani menahbiskan diri—atau ditahbiskan oleh banyak orang—sebagai “kritikus musik” hanya dengan berbekal umpatan “band ini jelek” di cuitan Twitter, dan sudah gitu aja tanpa ada analisis atau penjelasan lebih lanjut.
Bagaimana sekarang banyak orang berani menahbiskan diri—atau ditahbiskan oleh banyak orang—sebagai “kritikus musik” hanya dengan berbekal umpatan “band ini jelek” di cuitan Twitter
Ketiga hal ini memunculkan pertanyaan penting: memang sepenting apa sih kritik musik itu? Hingga perlu merambah ranah media sosial. Baik untuk musisi, atau untuk para penikmat musik pada umumnya.
Saya pernah membuat analogi bahwa jika musisi adalah sebuah badan eksekutif seperti presiden dan unsur pemerintahan lainnya yang mengemban tugas mengatur negara, maka kritikus musik adalah ibarat badan legislatif yang tugasnya mengingatkan musisi (badan eksekutif) agar bekerja sebagaimana peraturan perundang-undangan yang benar. Kritikus musik atau badan legislatif berfungsi menjaga agar kualitas musik yang digubah para musisi tetap memiliki unsur estetis dan berada di koridor penciptaan musik yang baik.
Bicara kritak-kritik musik memang tidak akan bisa lepas dari sejarah panjang perkembangan musik itu sendiri. Di dalam bukunya Jurnalisme Musik dan Selingkar Wilayahnya, akademisi Idhar Resmadi mengungkapkan bahwa mulanya kritikus musik kerap nyambi bekerja sebagai jurnalis. Idhar juga menjelaskan bahwa kritik musik di era kiwari lahir dari kebutuhan adanya diskursus pendamping dalam ekosistem industri musik. Maka, kritik musik adalah perpanjangan tangan dari industri itu sendiri, agar bisa mencetak musik-musik yang laris manis bak kacang goreng.
Kenapa tulisan-tulisan kritik musik di media-media besar ini bisa dibilang penting dan secara kualitas bermutu bagus? Karena para penulisnya bekerja di media dengan reputasi besar
Itulah kenapa selama beberapa dekade ke belakang, kritik musik selalu hadir di media-media massa besar yang memiliki reputasi besar. Misalnya di majalah Rolling Stone, atau kolom kritik musik di The Guardian dan New York Times. Ini karena para kritikus musik biasanya ya para jurnalis yang bekerja di kantor media tersebut. Kritik musik juga kerap hadir di media-media yang lebih niche seperti di Pitchfork, atau kalau di Indonesia jangan lupakan almarhum Jakartabeat.net yang kerap menghadirkan kritik-kritik musik yang tajam dan berkualitas.
Kenapa tulisan-tulisan kritik musik di media-media besar ini bisa dibilang penting dan secara kualitas bermutu bagus? Karena para penulisnya bekerja di media dengan reputasi besar. Maka, mereka harus patuh pada parameter tulisan yang bagus sesuai yang dianut media tersebut. Atau kalaupun kritikus musik itu bukan awak media, namun penulis di luar media seperti misalnya Amir Pasaribu, atau Remy Sylado, tulisan kritik mereka bisa sangat tajam, bernas, tanpa tedeng aling-aling hingga bisa bikin musisi yang dikritik menangis bombay dan memutuskan menghentikan karier bermusiknya. Sosok seperti Remy Sylado adalah contoh kritikus yang bisa menulis kritik musik dengan komprehensif tanpa perlu takut dituding sedang melakukan fafifu wasweswos.
Jujur, secara pribadi saya benci sekali dengan istilah fafifu wasweswos ini. Kenapa? Karena bagaimana kritik musik di Indonesia bisa maju kalau ketika seorang kritikus musik menulis sebuah kritik dengan kerangka ilmiah, atau menyelipkan satu dua teori sosial politik atau filsafat di tulisannya dalam rangka membuat tulisan itu makin berbobot, ia akan langsung dituding sedang melakukan fafifu wasweswos. Apapun arti sebenarnya, fafifu wasweswos adalah sebuah ejekan tidak bermutu yang merendahkan dan justru membikin kritik musik—atau banyak hal lain di dunia ini—mengalami stagnasi atau jalan di tempat.
Jika kritikus musik yang menulis musik serius dengan tulisan yang serius lalu dituding fafifu wasweswos, maka kritik musik akan selalu ketinggalan jauh dari kritik film yang lebih dinamis dan progresif
Jika kritikus musik yang menulis musik serius dengan tulisan yang serius lalu dituding fafifu wasweswos, maka kritik musik akan selalu ketinggalan jauh dari kritik film yang lebih dinamis dan progresif. Di Indonesia, terbukti bahwa kritik film selalu beberapa langkah lebih maju dari kritik musik. Kritik-kritik film yang bagus di Indonesia selalu mengedepankan interdisipliner. Artinya, mereka tidak hanya membahas segi sinematografi dari sebuah film. Namun, dengan berani kritikus film di Indonesia menggunakan banyak teori dan disiplin ilmu interdisipliner untuk membedah sebuah film. Baik itu di situs kajian film seperti Cinema Poetica, maupun sebatas cuitan di Twitter, kritik film selalu tampak cerdas dan tajam mengupas tuntas sebuah karya gambar bergerak.
Buntutnya, kritik film sudah sampai di level ketika Festival Film Indonesia (FFI) atau piala Citra sejak 2022 memberikan kategori penghargaan pada karya kritik film terbaik. Artinya di film, kritik sudah dianggap sebagai sebuah karya tulis yang tak kalah penting dengan karya film itu sendiri. Kritik film menjadi karya yang mengkritik karya, dan menjadi jembatan yang menghubungkan karya film dengan para penontonnya.
Lalu apa kabar dengan kritik musik? Ini akan nyambung dengan kalimat ketiga yang saya sebutkan di atas: “band ini jelek.” Dewasa ini tulisan kritik musik jarang dijumpai di media-media arus utama yang sudah mapan (baca: tua) seperti Kompas dan Tempo. Kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut saya ini terjadi karena lanskap media memang sudah berbeda. Di era kiwari, menulis cuitan di Twitter atau postingan di Instagram dianggap lebih mudah dan praktis ketimbang menulis misalnya tulisan kritik sejumlah 1000 kata, lalu mengirimkannya ke media. Seburuk apapun cuitan itu seperti cuma sekadar bilang “band ini jelek” tanpa menjelaskan lebih panjang kenapa band tersebut jelek, banyak orang yang merasa lebih nyaman menulis “kritik musik” di media sosial ketimbang menulis esai yang lebih lengkap dan komprehensif misalnya lalu mengirimkannya ke media massa.
Tulisan kritik musik jarang dijumpai di media-media arus utama yang sudah mapan. Menurut saya ini terjadi karena lanskap media memang sudah berbeda
Kondisi ini ada sisi positif dan negatifnya. Di satu sisi, terjadi demokratisasi dan desentralisasi. Artinya semua orang bisa menjadi kritikus musik lalu bebas menyampaikan pendapatnya di Twitter atau media sosial lainnya. Tidak dapat dimungkiri media sosial telah menjadi ruang demokrasi baru yang menjadikan semua orang bisa mengatakan apa pun yang mereka suka. Namun, di sisi lain ini jadi masalah juga karena kalau kita bicara kritik musik tadi, apakah makian “band ini jelek” di Twitter itu, yang tidak memiliki pisau bedah seperti analisis bentuk musik atau kajian organologi atau pembedahan semantik sebuah lirik, bisa disebut sebagai kritik musik?
Lalu kenapa lebih banyak orang gemar melakoni laku “kritik musik” di media sosial ketimbang menulis panjang dan memuatnya di media massa? Dalam pembacaan saya setidaknya ada tiga faktor penting.
Pertama, mereka-mereka yang gemar kritak-kritik musik di media sosial ini sebenarnya tidak punya kapabilitas dan kapasitas untuk menulis kritik yang panjang dan komprehensif. Maka, mereka tidak punya keberanian untuk menulis dengan baik dan mengirimkannya ke media massa. Maka, jadilah mereka sekadar ngetweet karena itu adalah cara termudah menyampaikan pesan di zaman sekarang.
Mungkin ini adalah senjakala kritik musik yang komprehensif. Kini orang lebih suka asyik-asyik kritik musik di media sosial. Apakah ini salah? Tidak juga, namanya juga internet, bebas lah mau ngapain aja.
Kedua, mereka-mereka ini sebenarnya tidak punya intensi memajukan ekosistem musik di Indonesia. Mereka tidak bermaksud melontarkan kritik sebagai pengingat agar musik yang diciptakan dibuat sebagus mungkin. Alih-alih, mereka ini hanya sekadar menggenjot clout, agar memperoleh pengikut (followers), engagement, dan dampak sosial yang besar di media sosial seperti Twitter.
Ketiga, Jangan-jangan sebenarnya banyak orang—terutama generasi muda—yang punya kemampuan menulis kritik musik dengan bagus. Namun, mereka takut atau sudah jiper duluan mau menulis kritik musik yang bagus lalu mengirimkannya ke media massa. Kenapa? Karena mereka takut tulisan mereka akan dituding fafifu wasweswos oleh orang-orang berpola pikir dangkal yang enggan belajar hal-hal substansial dan gemar menyerang orang dengan tudingan menyebalkan tersebut.
Iya, zaman sudah berubah, lanskap media massa sudah berubah, dan cara kita memaknai musik melalui kritik juga sudah berubah. Barangkali memang sudah saatnya kritik musik itu bukan lagi menjadi sebuah disiplin eksklusif yang hanya boleh dipraktikkan oleh praktisi seperti Amir Pasaribu, Remy Sylado, atau yang agak muda Nuran Wibisono dan Erie Setiawan. Kritik musik bebas dilakukan siapa pun. Mereka bisa dengan bebas mencerca album baru Reality Club, atau bilang bahwa Arctic Monkeys itu jelek di cuitannya. Semua orang bisa mengkritik musik di media sosial.
Mungkin ini adalah senjakala kritik musik yang komprehensif. Kini orang lebih suka asyik-asyik kritik musik di media sosial. Apakah ini salah? Tidak juga, namanya juga internet, bebas lah mau ngapain aja. Cuma, sebagai penutup saya akan mengutip pandangan pemikir dan kritikus musik Suka Hardjana bahwa estetika musik berarti memahami keseluruhan musik mulai dari proses penciptaan musik sampai musik itu diterima oleh pendengar. Musik bagi Suka Hardjana sebagai sarana ilmu pengetahuan atau informasi baru.
Pertanyaan terakhir untuk menutup tulisan ini: bagaimana bisa kritikus musik ini mampu menjabarkan proses kreatif sebuah musik dan menyampaikan bahwa musik adalah bentuk ilmu pengetahuan ke dalam kepampatan tweet yang cuma berjumlah 280 karakter? Apakah tweet “band ini jelek” sudah memberikan sumbangsih besar terhadap perkembangan musik di Indonesia? Wallahualam. Barangkali yang tahu cuma Tuhan, dan para kritikus musik yang beredar di media sosial ini.
Ilustrasi oleh Agung Abdul Basith.
Eksplor konten lain Pophariini
Jordy Waelauruw Kolaborasi bareng Kamga di Single Fighter
Setelah merilis “Baby (Let Me Go)”, menjadi kolaborator penuh Drewgon untuk album Koko Evav versi instrumental, dan terakhir menggaet Sun D dalam single “KAPITAN”, Jordy Waelauruw kembali lagi mengeluarkan materi terbaru berjudul “Fighter”. …
Lirik Lagu Hari Yang Mantap Tercipta Sangat Personal oleh Gusti Irwan Wibowo
“Hari Yang Mantap” jadi salah satu lagu dari album ENDIKUP milik mendiang Gusti Irwan Wibowo yang paling banyak berseliweran di media sosial sejak kepergiannya. Tak hanya karena musik dan liriknya yang ringan, tapi juga …