“Musik Menyelamatkan Saya” oleh Edy Khemod

Di lini masa Twitter beberapa waktu lalu, ada berita tentang pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda yang katanya tergabung dalam ‘geng’ tertentu. Kejadian ini bukan pertama kalinya di Bandung, dengan banyaknya kasus begal yang menyerang orang-orang secara acak di jalanan malam hari.
Dan bukan hanya di Bandung, di kota lain seperti Jogjakarta bahkan sempat menjadi trending topic di lini masa Twitter. Dengan adanya kasus klitih yang sampai menghilangkan nyawa korbannya. Berita-berita ini mengusik pikiran saya secara mendalam. Bukan karena saya pernah menjadi korban dari para pemuda berandalan ini. Justru, karena saya pernah menjadi pelakunya.
Saya tumbuh remaja di tahun 80an akhir / 90-an awal di Bandung, saat istilah ‘geng’ sedang tumbuh subur. Mulai dari geng motor dengan anggota yang cukup banyak sampai adanya geng di setiap kawasan dan komplek dengan karakteristiknya masing-masing. Untuk anak muda yang sedang mencari jati diri, dilengkapi dengan agresi darah mudanya, sulit untuk tidak terasosiasi ke dalam kelompok-kelompok ini. Mulai dari hanya sekedar ikut-ikutan ketika ada acara balapan di samping lapangan Gasibu, berteman dengan anggota dari geng-geng ini, atau bahkan ikut aktif di dalamnya.
Berita-berita geng motor dan klitih ini mengusik pikiran saya. Bukan karena pernah menjadi korban justru, karena saya pernah menjadi pelakunya.
Lalu apa saja kegiatan geng ini? Setiap kelompok punya tema dan karakteristiknya masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Tapi ingatan saya tentang kelompok-kelompok ini adalah tentang unjuk kejantanan. Mulai dari balap liar, perkelahian antar geng, sampai ke aktifitas kriminal seperti membegal dan mencuri. Masih segar ingatan saya terjebak dalam sebuah perkelahian besar di jalan Surapati antar dua geng, padahal saya tidak tergabung dalam geng tersebut.
Saya sendiri secara organik terseret ke dalam geng yang ada di sekitar rumah saya. Dorongan untuk diterima di pergaulan, membuat saya mengamini berbagai nilai negatif yang ada di antara teman-teman. Entah kenapa kelompok di komplek dekat rumah saya ini memiliki tendensi rasis terhadap etnis tertentu, dan kami kerap kali melakukan pembegalan pada orang-orang yang lewat daerah kami di malam hari.
Saya tidak ingat siapa yang pertama kali mencetuskannya. Tapi seperti tekanan pergaulan, anak muda di kawasan rumah saya serentak mengamini nilai-nilai keliru ini. Sambil saling menantang, siapa yang lebih berani di antara kami. Siapa berani membegal anak SMP yang pulang sekolah di siang hari. Untuk mencegat mobil yang lewat di daerah komplek rumah kami dan mengancam mereka untuk memberi uang. Rasa malu dan menyesal muncul saat saya menulis ini, membayangkan kebrengsekan yang saya lakukan di masa lalu.
Saya sendiri secara organik terseret ke dalam geng yang ada di sekitar rumah saya. Dorongan untuk diterima di pergaulan, membuat saya mengamini berbagai nilai negatif yang ada di antara teman-teman.
Mungkin ini terdengar klise, tapi kata-kata “musik menyelamatkan hidup saya” benar-benar terjadi di kasus saya. Seiring waktu berjalan, saya ternyata memiliki ketertarikan lebih terhadap musik. Mulai membuat band bersama beberapa teman, mulai hadir di acara-acara musik independen yang saat itu mulai tumbuh.
Waktu lowong saya yang tadinya banyak dihabiskan dengan nongkrong di jalan, sekarang mulai tersita dengan latihan band, datang ke acara di GOR Saparua dan manggung. Perlahan saya tidak lagi datang ke balapan liar di Lapangan Gasibu. Ditambah dengan seringnya saya bermain ke skena skateboard di Taman Lalu Lintas Bandung, memperluas pergaulan saya dengan teman-teman dari berbagai etnis. Tidak lagi terjebak dengan tekanan pergaulan di geng komplek dan nilai-nilai negatifnya, saya seperti menemukan jalur lain untuk menyalurkan agresi darah muda. Untuk menemukan jati diri baru, untuk diterima di pergaulan.
Waktu lowong yang tadinya banyak dihabiskan nongkrong di jalan, sekarang mulai tersita dengan latihan band, datang ke acara musik di GOR Saparua dan manggung.
Dengan beredarnya narasi dan literatur skena musik independent dan hardcore punk dari luar negeri lewat fanzine dan obrolan di antara teman, menambah wawasan saya tentang rasisme yang selama ini meracuni saya. Ternyata musik-musik yang saya suka, membawa pesan-pesan kesetaraan sosial, anti rasisme, hal-hal yang selama ini justru saya lakukan.
Hal ini juga sangat membekas dan berhasil mengubah sudut pandang saya. Karena nilai-nilai ini datang bukan dari otoritas seperti orang tua dan guru, tapi dari budaya populer dan tongkrongan baru yang ingin saya dekati.
Semakin membesarnya skena musik independen di Bandung, tampaknya juga mulai mengubah pola kegiatan anak-anak mudanya. Saya semakin sering melihat beberapa teman yang saya tahu adalah tokoh pentolan di sebuah geng motor, justru lebih sering berada di GOR Saparua. Antara tampil bersama bandnya atau hanya sekedar jadi penonton acara.
Ternyata musik-musik yang saya suka, membawa pesan-pesan kesetaraan sosial, anti rasisme, hal-hal yang selama ini justru saya lakukan.
Dengan rutinnya acara setiap minggu yang dihadiri sampai ribuan orang, mungkin berdampak juga pada menurunnya aktifitas geng motor di era 90an pertengahan sampai ke tahun 2000an awal. Mungkin agresi darah muda mereka yang tadinya disalurkan lewat perkelahian di jalan, kini tersalurkan lewat saling tabrak di moshpit atau berteriak di microphone bersama band punk mereka.
Sayangnya belum pernah ada kajian yang komprehensif tentang korelasi antara tumbuhnya skena musik dengan menurunnya aktifitas geng di tahun 90an. Paling tidak, ini yang terjadi untuk saya pribadi dan beberapa orang yang saya kenal. Belum pernah juga ada kajiannya, apakah ada hubungan antara tidak bisa dipakainya lagi GOR Saparua sebagai tempat pertunjukan di tahun 2001, dengan munculnya kembali pembegalan di jalanan kota Bandung di era 2006-2008.
Beberapa teman yang saya tahu adalah pentolan di sebuah geng motor, justru lebih sering berada di GOR Saparua. Antara tampil bersama bandnya atau jadi penonton acara.
Akhirnya ini hanya teori cocoklogi saya dan beberapa kawan. Tapi dengan berkurangnya prasarana anak muda untuk menyalurkan agresinya lewat berkarya tentunya tidak membuat situasi lebih baik. Sampai sekarang, Bandung saya rasa belum punya gedung pertunjukan yang terjangkau secara harga dan lokasi, yang mampu menampung massa sampai ribuan seperti GOR Saparua dulu.
Hal ini terbukti, sayangnya, salah satunya lewat kasus meninggalnya 11 orang di konser Beside di gedung AACC Bandung. Meskipun banyak faktor yang menyebabkan tragedi ini terjadi, tapi tidak adanya gedung memadai yang terjangkau menjadi salah satu penyebab kejadian ini. Dan berdasarkan pengamatan saya dan beberapa teman, pasca kejadian AACC dengan dipersulitnya perijinan acara anak muda, mulai muncul kembali beberapa kejadian pembegalan secara acak di jalanan Bandung di malam hari.
Sayangnya belum pernah ada kajian yang komprehensif tentang korelasi antara tumbuhnya skena musik dengan menurunnya aktifitas geng remaja di tahun 90an.
Kembali ke masa sekarang. Mungkinkah ada korelasi antara tiadanya acara bermusik dan ruang ekspresi anak muda dampak dari pandemi, dengan munculnya kembali aktifitas geng, klitih dan sebagainya? Dua tahun lamanya tidak ada sarana penyaluran agresi untuk anak muda, tidak adanya tempat untuk mereka bisa berkumpul dan berkarya, sehingga aktifitasnya kembali ke ‘jalan’? Saya tidak tahu jawabannya. Masih perlu penelitian yang lebih mendalam berdasarkan data untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi di luar itu, saya jadi berpikir apa hal yang mendorong anak muda untuk terlibat dalam ‘geng’ dan melakukan tindakan-tindakan kriminal mereka.
Berdasarkan pengalaman yang saya alami, teori sementara mengarah ke dua hal yang menjadi faktor pendorong utama; keinginan untuk diterima dengan nilai sosial yang tumbuh di lingkungan pertemanan, dan tantangan adu kejantanan. Bila nilai-nilai yang ada di lingkungan pertemanannya minim literasi tentang kesetaraan, berbensin kecemburan sosial, ditambah dengan tidak adanya saluran untuk adu kejantanan, menghasilkan aktifitas begal dan kriminal.
Berdasarkan pengamatan saya dan beberapa teman, pasca insiden AACC, dipersulitnya perijinan acara anak muda, muncul kembali beberapa kejadian pembegalan secara acak di jalanan Bandung di malam hari.
Ketika saya pindah pertemanan dengan nilai sosial yang anti rasisme, dengan penyaluran lewat bermusik, berganti pula pola perilaku. Bila sebelumnya membegal adalah hal ‘cool’ yang perlu dibuktikan ke lingkungan pertemanan, akhirnya berganti dengan nilai ‘cool’ yang baru, lewat berkarya. Karena ternyata hanya itu yang saya ingin buktikan. Terlihat ‘cool’ dan diterima di lingkungan pertemanan.
Apakah memfasilitasi anak muda untuk menyalurkan agresinya lewat berkarya dapat menyelesaikan masalah tindakan kriminal geng-geng ini? Terlalu naif untuk menyatakan hanya itu satu-satunya cara. Tapi mungkin bisa dimulai dari situ. Mungkin, dengan memudahkan mereka untuk menyalurkan energinya lewat berkarya, membuat mereka semakin sering berkumpul dengan lingkungan yang lebih produktif, dengan narasi yang lebih baik yang akan menjauhkan mereka dari nilai sosial yang merusak.
Apakah memfasilitasi anak muda untuk menyalurkan agresinya lewat berkarya dapat menyelesaikan masalah tindakan kriminal geng-geng ini?
Seburuk-buruknya orang melihat anak punk rock, narasi tentang kesetaraan sosial dan anti rasisme di kalangan mereka jauh lebih baik daripada narasi yang ada di geng tempat saya dulu tergabung. Kalau adu kejantanan mereka bisa diwakilkan lewat seberapa banyaknya orang datang menonton band mereka, bukan lewat seberapa banyaknya mereka berani membegal orang.
Mungkin, dengan memberi ruang ekspresi dan sense of purpose, kita bisa alihkan agresi darah muda dan pencarian jati diri mereka. Semua ini baru kemungkinan, saya juga tidak tahu jawaban pastinya apa. Yang pasti, topik tentang ‘geng’ ini masih membuat saya merasa bersalah. Saya masih merasa bersalah pernah menjadi anggota geng berandalan rasis tukang begal. Dan melihat fenomena yang terjadi kemarin ini di Bandung dan Jogjakarta, sedikit banyak saya paham apa yang anak-anak muda ini lalui. Apa yang mereka ingin buktikan.
Dan mungkin lewat tulisan ini, saya ingin menyelesaikan rasa bersalah saya. Kalau saya tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengubah perilaku saya ketika muda, paling tidak semoga tulisan pendek ini bisa mencegah anak muda lain untuk tidak terjerumus seperti saya dulu.
Artikel Terkait
Eksplor konten lain Pophariini
Lirik Lagu Terbuang Dalam Waktu Barasuara tentang Kehilangan dan Bersyukur
Saat ini film Sore: Istri Dari Masa Depan sedang jadi perbincangan di kalangan penonton film Indonesia. Karya dari sutradara Yandy Laurens yang tayang perdana tanggal 10 Juli 2025 ini turut menampilkan lagu “Terbuang Dalam …
Trisouls Rilis Single Cinta Tak Bertemu tentang Cinta yang Tak Bisa Menyatu
Setelah melewati masa vakum, trio vokal Trisouls resmi kembali ke industri musik Indonesia lewat perilisan single “Cinta Tak Bertemu”. Single ini sekaligus menandai babak baru perjalanan mereka bersama label POPS Music ID, dengan pendekatan …
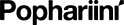

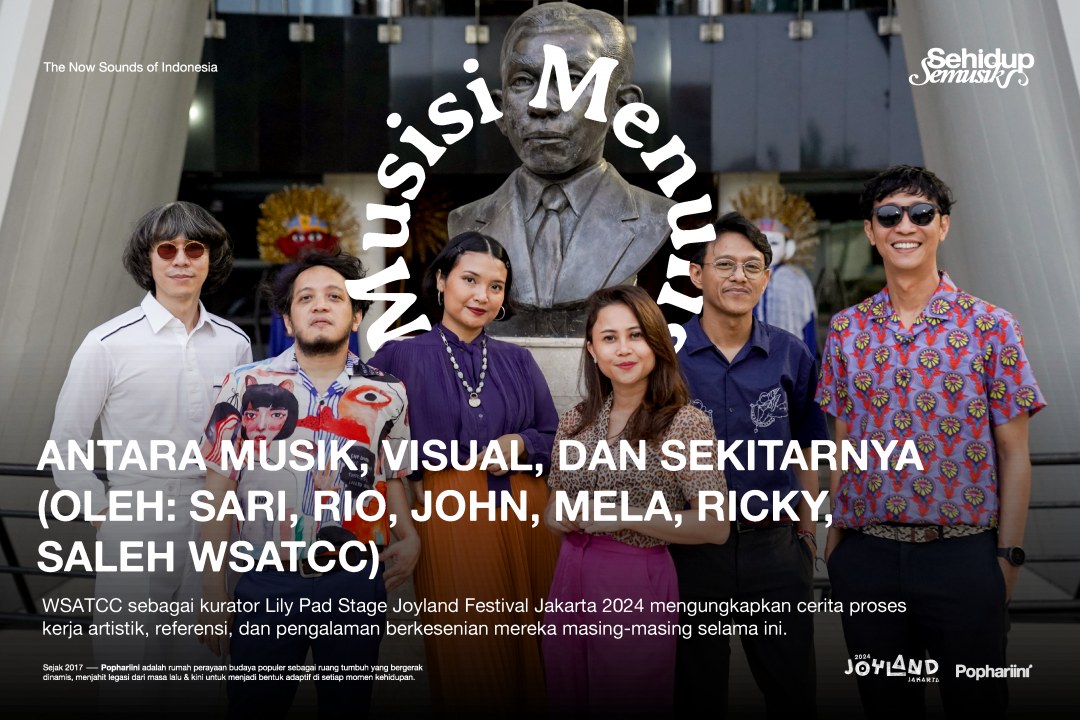



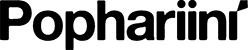

Kepsir, Kang! Gue banyak setuju atas apa yg lo tulis. Kenakalan juga mengalami transformasi di era dahulu dan sekarang. Satu yg gue khawatirkan skrg adalah arus politik identitas yg masih kental. Anak muda skrg akan semakin terjerumus ke dalam polarisasi mengarah rasisme yg dibuat elit politik. Persetan dgn mereka. Tapi semoga kultur musik, apapun genrenya, mampu mengubah paradigma generasi muda yg haus akan jatidirinya. Ya! Kami butuh konser utk menyalurkan energi ini! Salam 🤘😎