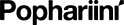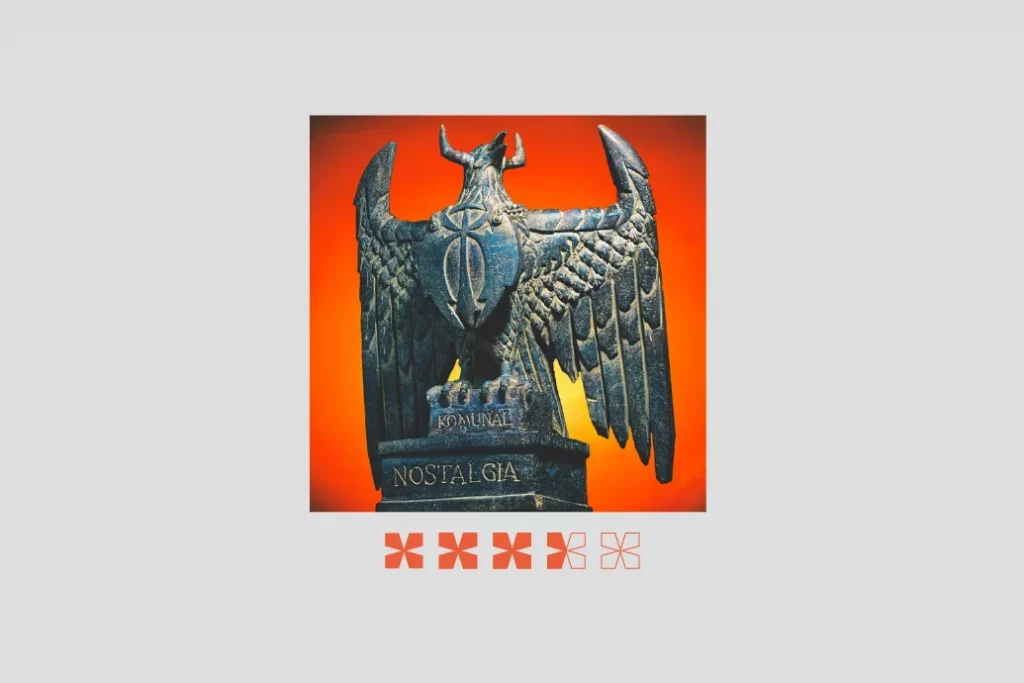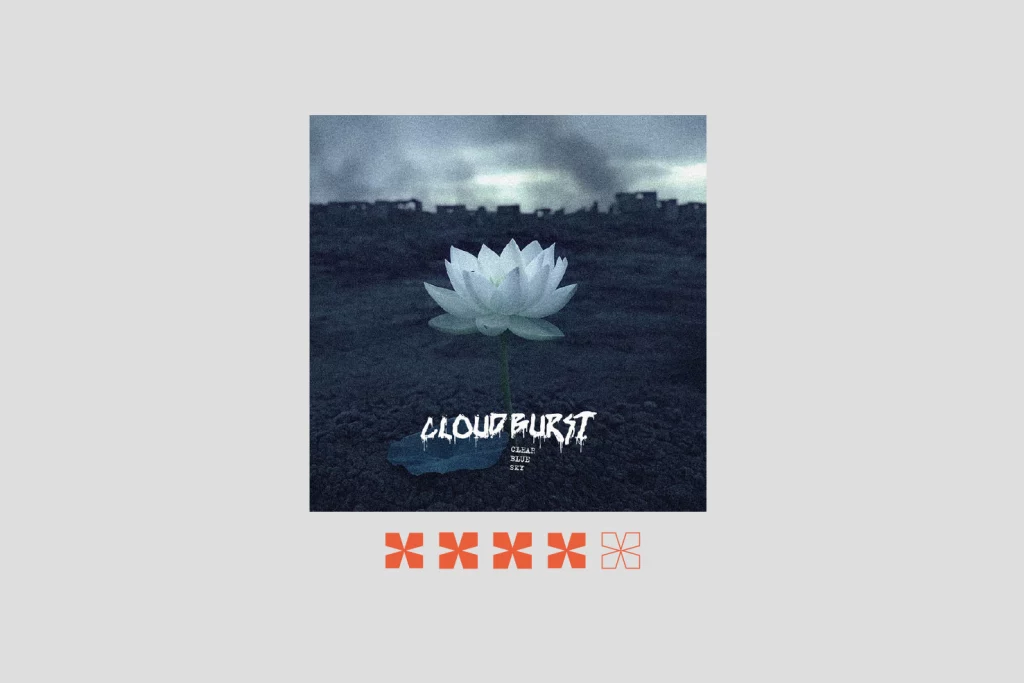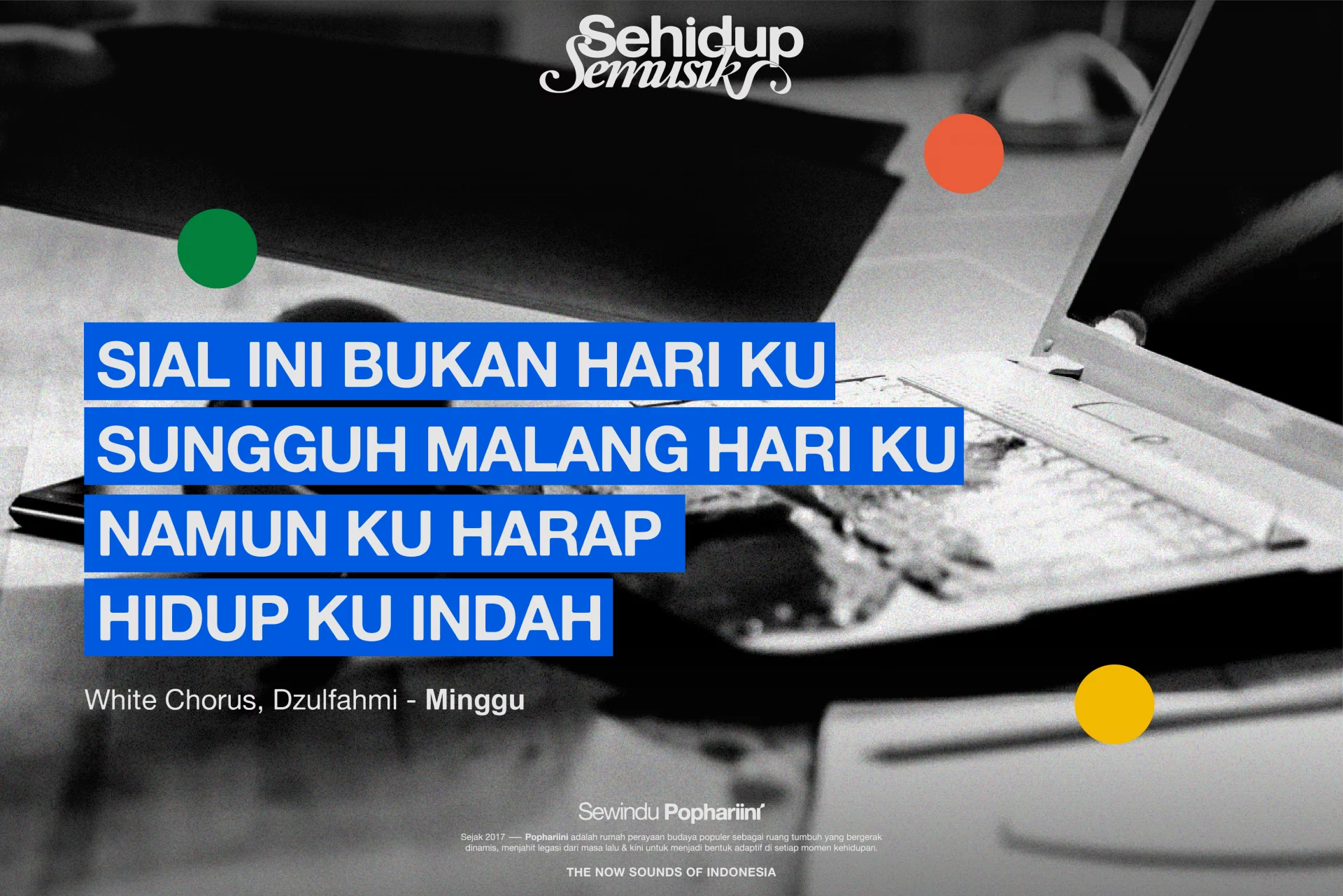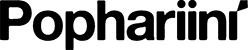Resensi: Sagas Midair – Loneliness & Decibels
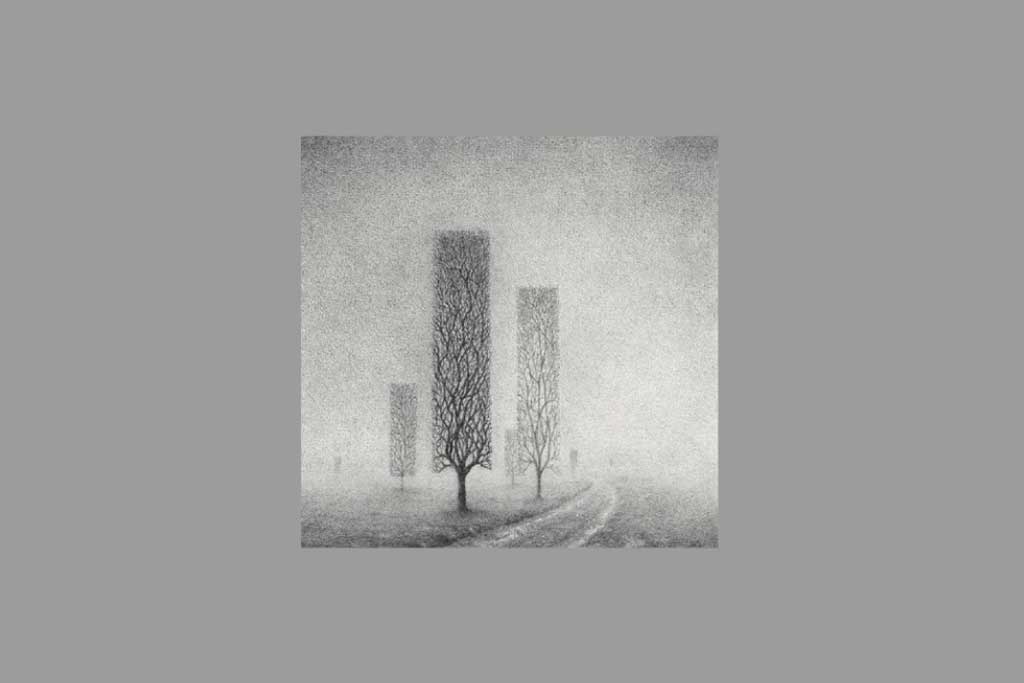
13 Agustus kemarin gitaris/vokalis/penulis lagu Iga Massardi merilis karya terbarunya, album solo bernuansa ambient, dengan moniker Sagas Midair berjudul Loneliness & Decibels. Delapan lagu instrumental dan semua direkam satu kali take, seluruhnya menggunakan instrumen gitar saja dan tidak ada proses overdub. Ini melengkapi katalog Iga yang telah merilis Taifun (2016), Pikiran dan Perjalanan (2019) bersama Barasuara, dua singel senang-senang “Krisis Hiburan” dan “Sesuai Titik” dengan nama Iga Massardi, serta tentunya perjalanan lampaunya dengan album Rasuk milik The Trees and the Wild di (2009).
Kita mengenal sosok Iga sebagai Barasuara, produser musik, penggemar kecepatan di atas sepeda roadbike nya, tak tertebak seperti merilis “Krisis Hiburan” dan “Sesuai Titik” yang fun itu, dan sebagai Youtuber yang mayoritas bicara efek pedal gitar. Namun kali ini kita akan melihat sosoknya yang berbeda. Tidak ngocol, tidak juga berapi-api namun sebaliknya, tenang dan menghanyutkan. Itulah mungkin mengapa ia memilih menggunakan nama Sagas Midair yang merupakan anagaram dari namanya sendiri sebagai kanvas baru area bermainnya.
Delapan lagu instrumental mengawang-awang dimuat ke dalam album berdurasi total 42 menit ini. Berbahasa Inggris seperti judul albumnya, masing-masing berdurasi 3 hingga yang terpanjang, 7 menit. Album ini juga dirilis bersamaan dengan video visualizer-nya yang digarap oleh seniman video Isha Hening. Menariknya ada unsur kelindan yang teramat merekat dihasilkan oleh kedua medium ini secara bersamaan. Dan menyimak albumnya sambil menatap video visualizer–nya -selain menggunakan headphone/speaker yang baik- adalah pengalaman yang direkomendasi.
Isha Hening sendiri adalah seniman visual dan video jockey (VJ) yang sudah banyak bergelut dengan dunia grafis bergerak (motion graphic) selain sudah sering bekerja sama dengan Iwan Fals, Raisa hingga tentu Barasuara. Maka itu tidak mengherankan bila Iga berbagi beban dan mempercayakan visual albumnya pada sosok seniman perempuan ini. Dan sungguh pilihan yang tepat. Mari bicarakan musiknya dahulu.
menyimak albumnya sambil menatap video visualnya -selain menggunakan headphone/speaker yang baik- adalah pengalaman yang direkomendasi.
Dibuka dengan “The Life We Knew”, Iga membuka album ini dengan bebunyian mengawang, perlahan dan merayap ke “Pendar, The Tree” hingga lagu ketiga mulai menunjukan tubuhnya lewat judul yang lebih eksplisit, ”We Are the Plague”. Bahwa wabah/pandemi ini sesungguhnya adalah manusia itu sendiri. Mood album lalu seperti kembali mengawang di lagu yang ditulis untuk kakeknya, “Good Night, Akung”.
Secara visual keempat lagu ini bagaikan puzzle magis yang tidak harus pas tapi bisa selaras. “The Live We Knew” digambarkan dengan visual bumi mengorbit yang di zoom in dan perlahan seperti terbakar. Lalu asapnya menebal dan menjembatani ke lagu berikutnya, “Pendar, The Tree” yang digambarkan dengan pohon yang meranggas seperti kebakaran hutan, kita akan melihat debu-debu beterbangan dalam gerak lambat, lalu diganggu oleh efek gerak masif melalui badai ombak di lautan yang saling menghantam dalam “We Are The Plague” cukup kontras dengan lagunya yang masih bertempo lambat. Kita lalu beralih pada lagu “Good Night, Akung” yang kembali ke elemen tanah dengan penampakan bunga matahari yang tenang disapu lembut oleh angin.
Inilah keindahan dari karya medium musik instrumental. Tafsir bebas terbuka lebar-lebar. Kata yang tersedia hanyalah judul album dan lagu.
Denting dawai gitar elektrik konvensional baru terdengar di lagu kelima, “Into The Valhalla”. Seolah menjadi menu utama, suara gitar elektrik polos terdengar begitu mahal. Visual paling gelap dalam pepohonan cemara di pegunungan yang berkabut memberikan kita ruang untuk menyimak petikan gitar yang tampil seolah telanjang bila dibanding lagu sebelumnya. Petikan gitar ini kembali terbungkus dengan berbagai bebunyian lain dalam “Mother Frequency”, dan divisualkan dengan hewan ubur-ubur yang bergerak dinamis, menjadi visual paling cantik. Menampakan detail, seluk beluk wujud ubur-ubur yang menari berenang ditingkahi musiknya. Berlanjut pada “Aria” yang diperuntukan untuk alm. Aria Baron, divisualkan dengan asap buatan yang diputar balik menjadi tampak menyusut, tentunya merespon suara gitar yang menggunakan efek terbalik (reverse). Dan ditutup oleh visual “Are We Afraid? We Are” meriah oleh ledakan kembang api, yang seolah merayakan rasa takut. Karena tentu, takut adalah hal manusiawi yang membuat manusia bertahan.
Semua pemaparan itu adalah kesan yang saya tangkap, dan tentunya bisa sangat berbeda interpretasinya dengan orang lain. Inilah keindahan dari karya medium musik instrumental. Tafsir bebas terbuka lebar-lebar. Kata yang tersedia hanyalah judul album dan lagu. Seperti halnya mencoba menebak makna album ini dari judul album Loneliness and Decibels, judul lagu “The Life We Know”, “Pendar, The Tree”, We Are The Plague, Good Night, Akung”, “Into Valhalla”, “Mother Frequency”, “Aria” dan “Are We Afraid? We Are” dan usaha mengaitkandengan elemen visual yang digunakan Isha dalam visualizer-nya secara berturut-turut yaitu, semesta, bumi, pohon meranggas/terbakar, badai ombak di lautan, bunga Matahari, pepohonan Cemara, ubur-ubur, asap yang bergerak mundur (terhisap) dan kembang api. Sekali lagi tafsir bebas terbuka lebar-lebar.
Keputusan Iga untuk menihilkan lirik di album ini menarik, mengingat eksplorasi yang berhasil di dua album Barasuara dan lirik bersenang-senang tanpa beban sudah terlewati. Maka menitikberatkan album ini pada kedua tangannya semata melalui rangkaian pedal efek yang juga santapan sehari-seharinya menjadi spesial. Sekaligus pembuktian kalau seorang diri mampu menghadirkan ragam bebuyian kontemplatif. Yang mampu membawa benak jalan-jalan jauh tanpa meninggalakan tempat duduk di rumah di era tanpa bisa ke mana-mana ini.
tapi album ini berkemungkinan membuka lembaran baru bagi gitaris di Indonesia. Kesendirian (loneliness) dan satuan ukuran yang digunakan dalam bebunyian (decibels) ini justru membuka probabilitas baru untuk seorang gitaris
Pandemi ini juga yang membuat Iga menumpahkan segalanya. Direkam kala dalam kesunyian isolasi mandiri ketika dirinya dinyatakan positif tanpa gejala. Awalnya mungkin hanya penyaluran semata, tapi album ini berkemungkinan membuka lembaran baru bagi gitaris di Indonesia. Kesendirian (loneliness) dan satuan ukuran yang digunakan dalam bebunyian (decibels) ini justru membuka probabilitas baru untuk seorang gitaris. Ada ribuan cara untuk berekspresi termasuk dengan gitar. Dan memainkan solo gitar meliuk panjang melengking dan meraung bagaikan dewa gitar bukan pilihannya kali ini.
Meskipun bukan yang pertama di dunia ini, dan banyak nama-nama lain yang telah dulu melakukan hal serupa, namun saya takutkan album ini berpotensi membuat konsep gitar rock menjadi seolah usang di Indonesia.
Lantas apakah era gitar rock Indonesia perlahan menemui ajalnya? Bisa jadi. Yang pasti dengan Loneliness and Decibels, Sagas Midair alias Iga Massardi turut berperan di dalamnya.
Eksplor konten lain Pophariini
Lirik Minggu White Chorus tentang Harapan di Hari Buruk
“Minggu” dari White Chorus adalah lagu tentang hari-hari buruk yang tetap kita jalani dengan harapan tipis. Lewat lirik yang jujur dan sederhana, lagu ini menggambarkan situasi yang sangat akrab, yaitu kesialan kecil, rasa jenuh, …
Sawung Jabo & Sirkus Barock Rilis Album Live Mengejar Bayangan Menangkap Angin
Sawung Jabo menandai 50 tahun perjalanan bermusiknya dengan merilis sebuah album spesial bertajuk Mengejar Bayangan Menangkap Angin: The Live Album, sebuah karya yang menyatukan kembali semangat teatrikal Sirkus Barock dalam balutan aransemen langsung yang …