Yamete Kudasai! Membela Musik-Musik “Jelek”

Di era digital ini, para pemusik memiliki kesempatan untuk merilis karya tanpa harus melalui label ataupun media yang akan menyaringnya terlebih dahulu sebelum dilempar ke pasar. Dampaknya, kita selaku pendengar memiliki banyak opsi yang sebelumnya mungkin hanya tergantung pada apa yang dipajang di toko kaset ataupun CD. Dengan mengunggah secara mandiri di kanal-kanal seperti Youtube, Spotify ataupun TikTok para pemusik dapat menampilkan musik “apapun”, termasuk yang selama ini dianggap tidak sesuai dengan “selera pasar” alias: “jelek”.
“Jelek” yang dimaksud di sini tentu diukur dalam kriteria tertentu, yang bisa jadi dalam kriteria lainnya, musik tersebut dapat dikatakan “bagus” – setidaknya jika salah satu tolok ukurnya adalah didengar oleh jutaan orang! Musik “jelek” yang dimaksud di sini misalnya lagu berjudul “Yamete Kudasai“, “Ye Tu Hantu” atau lebih mundur lagi, karya-karya dari band Kufaku.
Apa yang dimaksud “jelek” di sini mungkin lebih pada estetikanya yang cenderung tidak umum dikonsumsi dalam konteks “musik industri”. Musik-musik semacam ini mungkin populer, tetapi tidak terlalu umum di kota-kota besar, khususnya bagi kalangan menengah ke atas. Selain itu, “jelek” di sini juga bisa berarti harfiah misalnya, salah satu karya dari band Kufaku yang berjudul “Cuma Kamu”, benar-benar diisi oleh vokal yang nadanya meleset dari iringan! Mudahnya, musik “jelek” yang dimaksud di sini bisa diartikan “norak” bagi kalangan tertentu – ibarat gambar atau tulisan yang ada di badan truk, yang kelihatannya tidak mungkin ada di badan city car -.
Apa yang dimaksud “jelek” di sini mungkin lebih pada estetikanya yang cenderung tidak umum dikonsumsi dalam konteks “musik industri”. Musik-musik semacam ini mungkin populer, tetapi tidak terlalu umum di kota-kota besar, khususnya bagi kalangan menengah ke atas
Namun apa yang “norak” itu justru dikonsumsi dalam jumlah yang tidak main-main. “Yamete Kudasai” yang dinyanyikan oleh Dewi Isma Hoeriah misalnya, dalam waktu kurang dari dua bulan, sudah ditonton lebih dari dua juta penonton di Youtube! Sementara “Ye Tu Hantu” yang dinyanyikan oleh Azaz dan Fikri, yang diunggah tahun 2015 juga mempunyai jumlah penonton yang kurang lebih sama. Lagu lainnya, misalnya “Kok Elo Tega” yang berasal dari tahun 2012, ditonton oleh satu jutaan akun. Artinya, terlepas apakah penonton tersebut pada akhirnya tidak suka dengan lagunya, toh mereka tetap menontonnya – yang artinya, menyumbang pemasukan bagi si pengunggah -.
Menggugat Rezim Estetika
Fenomena di atas setidaknya menunjukkan bahwa ada semacam “irasionalitas” dalam dunia digital, yang membuat mereka-mereka yang sebenarnya “kurang istimewa” bisa menjadi viral. Kita tentu ingat fenomena Keong Racun dari Sinta dan Jojo tahun 2010 yang ditonton hingga 13 juta orang. Boro-boro mengunggah karya sendiri atau bahkan menunjukkan kemampuan bernyanyi, mereka berdua bahkan hanya melakukan lip sync dan berjoget!
Bagaimana kemudian kita membaca fenomena semacam ini? Pertama, bisa jadi ada kebosanan pada estetika musik yang selama ini diputar di arus utama. Arus utama ini tidak bisa dianggap netral, melainkan seperti punya wewenang untuk menentukan musik-musik seperti apa yang bisa dikonsumsi oleh kelas tertentu. Kita bisa ambil contoh pada tahun 1970-an, terdapat wacana bahwa musik rock identik dengan musik “kelas atas” sementara musik dangdut lebih dekat dengan “kalangan bawah”.
Kita tentu ingat fenomena Keong Racun dari Sinta dan Jojo tahun 2010 yang ditonton hingga 13 juta orang. Boro-boro mengunggah karya sendiri atau bahkan menunjukkan kemampuan bernyanyi, mereka berdua bahkan hanya melakukan lip sync dan berjoget!
Label-label besar tentu lebih memilih untuk memopulerkan musik rock karena dianggap sejalan dengan semangat ke-Barat-Barat-an yang waktu itu sedang marak. Namun sejak dua dekade belakangan, terutama sejak mencuatnya Inul Daratista di awal tahun 2000-an, dangdut pelan-pelan dikonsumsi secara lebih luas dan tidak melulu identik dengan “kalangan bawah”.
Bisa jadi, orang-orang kemudian muak dengan selera yang terus disetir oleh kekuasaan tertentu. Dengan adanya internet, ada semacam pembebasan terhadap selera. “Kelas atas” bisa menikmati musik “kalangan bawah” dan juga sebaliknya, sehingga sekat-sekat pengkelasan justru menjadi tidak lagi relevan. Secara lebih kritis dapat diartikan bahwa ada semacam pemberontakan terhadap rezim estetika yang selama ini seperti “sok tahu” dalam memetakan selera pasar. Dalam hal ini, warganet seperti berbalik punya wewenang: “Mengapa kita harus melambungkan terus band-band yang sudah mapan, sementara kita bisa punya peluang menaikkan nama-nama ‘terpinggirkan’ seperti Dewi Isma Hoeriah ataupun Azaz dan Fikri?”
Representasi Nafsu Dasar
Analisis kedua dapat dibaca dari kenyataan bahwa musik-musik “jelek” tersebut seringkali dapat menghadirkan tema yang selama ini “disembunyikan” dari norma-norma pada umumnya. Untuk menganalisis ini, kita bisa meminjam pemikiran Sigmund Freud dalam bukunya yang berjudul Civilization and Its Discontents (1930). Di dalam tulisannya tersebut, Freud menyebutkan bagaimana peradaban seolah menganggap rendah mereka yang tidak bisa menahan nafsu-nafsu dasarnya. Orang-orang yang dianggap bagus dan produktif, adalah mereka yang memilih untuk menekan keinginannya untuk tidur, berhubungan seksual atau menunjukkan emosi yang tidak terkendali. Artinya, nafsu-nafsu dasar tersebut cenderung direpresi oleh lingkungan.
Dengan adanya internet, ada semacam pembebasan terhadap selera. “Kelas atas” bisa menikmati musik “kalangan bawah” dan juga sebaliknya, sehingga sekat-sekat pengkelasan justru menjadi tidak lagi relevan.
Musik-musik “jelek” ini ternyata mampu menangkap nafsu-nafsu dasar yang ditekan tersebut. Misalnya, dalam lirik “Yamete Kudasai”, ada ungkapan “ara-ara kimochi” yang tentu akrab bagi penggemar film porno Jepang. Demikian halnya pada lirik “Ye Tu Hantu”, diulang-ulang kalimat “Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, jadi hantu” yang tentu saja dianggap tidak bermoral jika diungkapkan dalam keseharian! Contoh bagus ada pada lagu berjudul “Kok Elo Tega” yang dengan keras menyindir konsep Tuhan dalam beberapa agama. Mungkin dalam bawah sadar kita semua, terselip keinginan untuk mengungkapkan hal-hal semacam itu, tetapi mana mungkin dalam dunia yang tidak memberi tempat bagi “nafsu dasar”?
Maka itu, suka tidak suka, musik-musik semacam itu akan terus bermunculan untuk memuaskan hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin jauh di bawah sadar, kita muak akan kehidupan yang terlampau formal, kaku dan penuh aturan. Diam-diam kita ingin meneriakkan “ara-ara kimochi” di tempat kerja pada saat dikejar deadline ataupun ingin mempertanyakan konsep Tuhan tertentu tetapi terlalu takut dimusuhi oleh teman-teman. Melalui musik-musik tersebut, perasaan kita menjadi terwakili dan bisa mengiyakan sambil cukup tertawa geli.
Siapa yang Diuntungkan?
Hal yang belum bisa terlalu dipecahkan mungkin adalah ini: siapakah sebenarnya para pencipta dan pengunggah musik-musik tersebut? Kita bisa mempertanyakan bahwa mungkin saja ada sejumlah sosok kreatif di balik Dewi Isma Hoeriah atau Azaz – Fikri. Orang-orang ini bisa saja sangat mengerti musik dan bahkan berprofesi sebagai pemusik profesional, tetapi memilih untuk membuat karya-karya “jelek” sebagai cara untuk menarik perhatian.
Saking cerdasnya, mereka mampu menampilkan semacam jukstaposisi antara ibu berkerudung dengan ekspresi yang muncul dalam film porno seperti dalam “Yamete Kudasai” dan terbukti disenangi
Jika memang ada “aktor intelektual” di balik produksi karya-karya semacam ini, pertama, tentu mereka adalah orang-orang cerdas yang mampu membaca selera pasar yang tengah jenuh. Saking cerdasnya, mereka mampu menampilkan semacam jukstaposisi antara ibu berkerudung dengan ekspresi yang muncul dalam film porno seperti dalam “Yamete Kudasai” dan terbukti disenangi. Kedua, timbul pertanyaan, apakah terjadi objektivikasi terhadap masyarakat kelas tertentu sehingga yang diuntungkan bukanlah “ibu berkerudung” yang “sebenarnya”, tetapi lebih pada ibu berkerudung yang mereka ciptakan. Ibaratnya, seorang perupa melukis perumahan kumuh sebagai objeknya, tetapi uang hasil penjualan lukisannya tidak disumbangkan pada perumahan kumuh yang ia jadikan objek, melainkan dikantongi untuk dirinya sendiri.
Namun soal yang terakhir ini hanya kecurigaan semata. Bisa jadi tidak ada “aktor intelektual” manapun di belakang mereka dan orang-orang ini, Dewi Isma Hoeriah ataupun Azaz – Fikri memang mengunggahnya atas dasar keisengannya sendiri. Ternyata, keisengan mereka berbuah manis.
Eksplor konten lain Pophariini
The Panturas Membekali Tur Asia dengan Maxi Single Knights of Jahannam / Soma Gospel
Jeda sekitar 8 bulan semenjak perilisan album mini Galura Tropikalia tahun 2024 lalu, The Panturas kembali dengan karya baru lewat perilisan maxi single Knights of Jahannam / Soma Gospel (11/07). Materi ini menjadi langkah …
Namoy Budaya dan Weaken Amore Rilis Single Aku Bisa Milik Flanella Versi Remix
Setelah melepas versi remix dari lagu “Thunder Boarding School” milik Teenage Death Star April lalu, DJ sekaligus produser musik asal Lampung, Namoy Budaya bersama Weaken Amore merilis lagu milik Flanella bertajuk “Aku Bisa” versi …
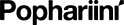





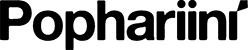

cool