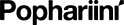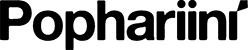Mengatasi Kebosanan Lineup Festival Musik Yang Itu-Itu Saja

Seperti biasa, malam itu aku sedang scrolling laman Twitter mengharapkan update teman-teman dan foto-foto editorial fashion cantik. Seperti biasa pula, yang kudapatkan adalah keributan (ekspektasiku pantas disalahkan). Kali ini, sejumlah orang sedang riuh membahas salah satu tweet yang telah mondar-mandir seharian di timeline. Dalam tweet yang sempat ramai tersebut, musisi asal Malang, Steffani BPM mengeluhkan reaksi negatif pengguna Instagram yang kecewa karena penampil yang telah ditunggu-tunggu di sebuah festival musik mendadak diganti dengan penampil lain yang bagi mereka kurang dikenal.
“Ngeri banget kalau ga tau performer-nya itu siapa masa langsung ngamuk dan ngatain,” jelasnya. Meskipun Steffani tidak terang-terangan menjelaskan festival musik apa yang dimaksud, beberapa orang di balasan tweet tersebut menambahkan bahwa hal itu kerap terjadi juga di acara-acara lain. “Pantesan acara musik sekarang line up-nya itu-itu aja ya,” tambah Steffani.
Musisi asal Malang Steffani BPM mengeluhkan reaksi negatif pengguna Instagram yang kecewa karena penampil yang telah ditunggu-tunggu di sebuah festival musik mendadak diganti dengan penampil lain yang bagi mereka kurang dikenal.
Sebagai seseorang yang pernah mengelola akun media sosial sebuah festival musik, membayangkan laman komentar Instagram dipenuhi makian dari pembeli tiket yang kecewa langsung membuatku bergidik. Namun, apakah berarti penyelenggara acara harus terus-terusan booking nama-nama “itu-itu saja” sebagai penampil untuk meminimalisir makian netizen dan memaksimalkan profit? Kalau memang itu yang terjadi saat ini, bagaimana dengan musisi lain yang belum punya nama sebesar headliner festival?

Perfomance art Bajra di gigs Pesona Lidah Kulon, yang diinisiasi oleh Mendadak Kolektif x Greedy Dust. / Foto: Adi Fikri
Menurut Rizkia Larasati atau Laras, vokalis dari duo R&B RL KLAV, keberadaan festival musik atau event musik yang mendukung talenta-talenta musik baru memang sangat langka. Kalaupun ada, jarang yang mau membayar para penampilnya dengan layak. “Kalau lagi di fase awal mungkin kita willing to sacrifice ya, tapi kalau begitu terus mau hidup bagaimana?” tambahnya.
“Ngeri banget kalau ga tau performer-nya itu siapa masa langsung ngamuk dan ngatain,” jelasnya. Beberapa orang di balasan tweet tersebut menambahkan bahwa hal itu kerap terjadi juga di acara-acara lain. “Pantesan acara musik sekarang line up-nya itu-itu aja ya,” tambah Steffani
Dalam narasi yang sepertinya sudah familiar bagi kita, industri musik “dipegang” oleh sejumlah gatekeeper yang berhak menentukan siapa yang bisa masuk dan siapa yang tidak. Mereka yang belum dipersilakan masuk rela melakukan berbagai upaya untuk menjadi part of the club, termasuk dengan sengaja membuat lagu yang ramah algoritma atau mereduksi karya mereka menjadi kampanye media sosial. Viral menjadi tujuan.

Penampilan Sugar Thrill di gigs Pesona Lidah Kulon, yang diinisiasi oleh Mendadak Kolektif x Greedy Dust / Foto: Nyoman Bayu
Angka streaming maupun jumlah followers adalah indikator kesuksesan yang dapat make it or break it. Industri yang kompetitif sejak awal makin diperkeruh dengan attention economy yang membuat pelakunya tak rela mengambil risiko selain mengulang formula-formula yang terbukti berhasil. Narasi yang dilandasi oleh kapitalisme ini cukup merefleksikan apa yang saat ini terjadi, namun ia bukan satu-satunya jalan yang harus kita ikuti.
Sebagai musisi yang juga memiliki pengalaman di balik layar sebagai pekerja label rekaman, Rasyiqa menyadari bahwa angka-angka streaming/followers menjadi salah satu hal terpenting yang dipertimbangkan oleh kurator atau programmer festival musik dalam menentukan layak atau tidaknya seorang musisi untuk tampil.
Sebagai musisi yang juga memiliki pengalaman di balik layar sebagai pekerja label rekaman, Rasyiqa menyadari bahwa angka-angka tersebut menjadi salah satu hal terpenting yang dipertimbangkan oleh kurator atau programmer festival musik dalam menentukan layak atau tidaknya seorang musisi untuk tampil. “Masalahnya, banyak artis-artis baru dan berbakat yang belum mendapat kesempatan naik panggung dan menunjukkan karya mereka pada calon-calon pendengar hanya karena jumlah streaming mereka dirasa belum cukup oleh penyelenggara acara,” tambahnya. “Meskipun streaming juga membantu musisi untuk dikenal audiens, kayaknya hal itu nggak sebanding dengan discovering musisi dari live performance-nya.”

Moneva di Salon RnB / Foto: Melina Anggraini
Solois Marcello Laksono yang juga dikenal sebagai cellosux merasakan hal yang serupa tentang ketergantungan industri terhadap angka. “Chord yang sama, ballad yang sama, loop 15 detik yang sengaja dibuat biar lagunya jadi algorithm-friendly. What’s the point of making art for an audience when the art you make finds the audience for you?” Meskipun begitu, ia percaya bahwa masih ada orang yang haus akan perspektif baru.
“Masalahnya, banyak artis-artis baru dan berbakat yang belum mendapat kesempatan naik panggung dan menunjukkan karya mereka pada calon-calon pendengar hanya karena jumlah streaming mereka dirasa belum cukup oleh penyelenggara acara,”
Karena itu, di tahun 2017 dan 2018 ia menggelar Pink Lemonade, sebuah festival mini yang menghadirkan musisi-musisi independen yang ia kurasi. Pink Lemonade juga menjadi ajang pertama Cello tampil sebagai cellosux. Bermodalkan kocek sendiri tanpa sponsor mana pun, Pink Lemonade sempat menghadirkan VVYND, The Boris Suit, Heidi (The Girl with The Hair), Ben Sihombing, dan Adrian Khalif yang baru memiliki satu single pada saat itu. Cello menambahkan bahwa ia memilih artis-artis tersebut karena ia percaya akan musik yang mereka buat dengan harapan orang lain juga berkesempatan menikmati karya-karya mereka. “Nggak perlu malu kalau gig kamu nggak profit. Kadang-kadang, keuntungan yang didapat nggak harus dalam bentuk finansial,” jelasnya.

Duo RL Klav di Salon RnB / Foto: Melina Anggraini
Di tengah kesenjangan akses, eksploitasi oleh layanan streaming, dan monopoli line up yang itu-itu saja, sepertinya tidak ada cara yang lebih baik selain membuat ruang tampil sendiri. Bennett dan Rogers (2016) memaknai unofficial music venues sebagai respon terhadap keadaan-keadaan tertentu. Salah satu contohnya adalah terbatasnya celah untuk tampil di platform seperti festival musik atau event yang berorientasi profit. Selain itu, hal ini juga muncul sebagai manifestasi keinginan sebuah kelompok atau komunitas yang mengharapkan pengalaman menikmati musik yang berbeda tanpa harus mengikuti selera dominan yang diusung oleh promotor besar.
Di tahun 2017 dan 2018 Cello menggelar Pink Lemonade, sebuah festival mini yang menghadirkan musisi-musisi independen yang ia kurasi. Pink Lemonade juga menjadi ajang pertama Cello tampil sebagai cellosux.
Berawal dari kesadaran akan terbatasnya ruang bagi penampil yang membawakan genre R&B di Indonesia, musisi RL KLAV, Moneva, dan Gavendri menggelar showcase kolektif pertama mereka di The Moon, Hotel Monopoli, Jakarta Selatan pada pertengahan Juli 2022 lalu. Bagi Laras, saat ini belum banyak platform yang dapat menampung artis-artis R&B dan genre-genre sejenis. “Artisnya sebetulnya ada banyak banget, tapi berasa individualis aja karena belum ada space yang bisa menyatukan.” Selain genre yang serupa, Salon RnB juga berniat untuk mengutamakan penampil perempuan dalam acara-acara mereka.

Gavendri di Salon RnB / Foto: Melina Anggraini
“Di skena musik ini peran cewe masih suka ketutup sama cowo-cowo, bisa terlihat dari line up acara yang seringnya didominasi laki-laki. Dengan Salon RnB ini kami jadi bisa showcasing talent perempuan biar lebih terlihat,” tambah Keshia Aita dari RL KLAV. “Karena dikelilingi feminine energy, di acara itu kita ngerasa lebih mindful dan safe sambil tetap bebas berekspresi.” Menurut Laras, penting untuk mengetahui visi dari space yang akan dibuat. “Harus tahu visi utamanya apa, then gather people with the same vision. Jangan cuma dibayangin, just do it.”
Di tengah kesenjangan akses, eksploitasi oleh layanan streaming, dan monopoli line up yang itu-itu saja, sepertinya tidak ada cara yang lebih baik selain membuat ruang tampil sendiri.
Ruang independen yang inklusif pada berbagai genre juga dapat ditemui di Surabaya dan sekitarnya. Mendadak Kolektif didirikan di tahun 2017 untuk membuat gigs skala kecil hingga menengah. Sholehuddin, salah satu penggagas Mendadak Kolektif, terinspirasi untuk mulai mengorganisir gigs bersama teman-temannya setelah sekian lama hanya menjadi penikmat di acara-acara lain. “Karena pertemanan makin menyebar dan kami ingin membuat ruang berdasarkan kesenangan kita semua, mungkin itu salah satu alasan kenapa kami memilih membuat kolektif sendiri,” ungkapnya.
Dari kesadaran akan terbatasnya ruang bagi penampil yang membawakan genre R&B di Indonesia, musisi RL KLAV, Moneva, dan Gavendri menggelar showcase kolektif pertama mereka di The Moon, Hotel Monopoli, Jakarta Selatan pada pertengahan Juli 2022 lalu bernama Salon RnB.
Kolaborasi menjadi nilai penting yang dianut Mendadak Kolektif. Selain gigs dengan band-band lokal Surabaya, mereka juga kerap membuat gigs untuk band asal kota maupun negara lain yang sedang tur. Di bulan Maret 2022 lalu, Mendadak Kolektif berkolaborasi dengan label Greedy Dust untuk memproduksi showcase Pesona Lidah Kulon yang menampilkan produser breakcore TamaT dan unit hardcore asal Malang, Keep It Real. Showcase ini juga mengangkat instalasi dan performance art oleh Bajra, kolektif perupa new media asal Pasuruan. Sholehuddin juga menekankan pentingnya keterbukaan pada musisi-musisi baru untuk mendorong regenerasi di skena. “Mereka yang bakal nerusin perjalanan ruang yang sudah kalian buat.”
Kolaborasi menjadi nilai penting yang dianut Mendadak Kolektif. Selain gigs dengan band-band lokal Surabaya, mereka juga kerap membuat gigs untuk band asal kota maupun negara lain yang sedang tur.
Menciptakan ruang-ruang baru yang inklusif dan beragam tidak hanya memberikan platform bagi musisi untuk bebas berkarya, tetapi juga mengekspos audiens kepada karya-karya yang mungkin luput dari sorotan New Music Friday dan For You Page. Masing-masing dari kita menikmati musik dari perspektif, pengalaman, kemampuan, dan tujuan yang berbeda, sehingga menurutku sangat disayangkan kalau kita membatasi diri dengan hanya mendengarkan musik yang telah disodorkan rapi dalam playlist yang dibuat oleh algoritma. Bisa jadi pada saat ini mereka belum hadir di deretan headliner festival, tapi kini kamu sudah tahu ke mana harus mencari ketika jenuh dengan line up yang itu-itu saja.
Referensi
Bennett, A., & Rogers, I. (2016). In the Scattered Fields of Memory. Space and Culture, 19(4), 490–501.
Eksplor konten lain Pophariini
Eksklusif Komunal: 13 Tahun Tanpa Album, Nostalgia Ini Ijazah
Sejak merilis album penuh Gemuruh Musik Pertiwi 13 tahun lalu, Komunal rasanya belum menunjukkan kembali eksistensi mereka lewat perilisan materi holistik sebagai statement keberadaan mereka. Memang, selain masih aktif menghibur KKK (Kawan-kawan Komunal) di …
False Theory Ceritakan Kisah Penyembuhan Luka Masa Lalu di Single Dua Atma
Unit pop punk asal Tana Paser, Kalimantan Timur, False Theory merilis single ketiga bertajuk “Dua Atma” pada Kamis (05/06). Lewat lagu ini, mereka mengangkat cerita tentang dua jiwa yang saling menyembuhkan dari luka masa …